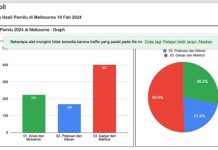Oleh Muhammad Ali Murtadlo
Oleh Muhammad Ali Murtadlo
Kita lagi-lagi dihebohkan oleh aksi teror yang mengatasnamakan agama. Serangan di kawasan Sarinah, Jakarta setahun silam adalah aksi teror pertama kali yang dilakukan secara terang-terangan di Indonesia. Bahkan, dramatisasi aksi baku tembak antara polisi dan pelaku menjadi sebuah tontonan bagi warga. Disusul kemudian rentetan bom panci di Bandung, di Kampung Melayu dan yang terbaru muncul pesan kaleng di Mapolsek Kebayoran Lama yang berisi ancaman akan menjadikan Jakarta seperti Marawi, Filipina (duta.co/04/17). ISIS (Islamic State of Iraq and Suriah) mengklaim rentetan aksi tersebut adalah ulah mereka. Sudah sedemikian parahkah aksi teror di Indonesia?
Bermula dari Ketidakadilan
Aksi terorisme bukan kali pertama ini terjadi. Terorisme sudah berusia renta. Selama berabad-abad, dunia tampaknya tak pernah sepi dari aksi-aksi yang dilakukan sekelompok radikal-ekstrem. Motivasi yang melandasinya saling campur aduk, dari politik, sosial hingga keagamaan. Keresahan sekelompok orang yang semakin menggumpal kemudian meledak dan terjadilah aksi brutal. Maka, banyak yang memandang, ada satu hal yang bisa dimanunggalkan sebagai motif terorisme, yaitu ketidakadilan.
Ini dapat diungkap dari sejarah kata-kata teror itu sendiri. Kata teror faktanya baru masuk dalam kosa kata politik pada masa revolusi Perancis. Selanjutnya di abad ke 19 hingga abad 20, istilah terorisme menjadi taktik perjuangan revolusi. Dari sinilah, banyak yang memahami bahwa pada awalnya terorisme lahir akibat kekisruhan politik yang konotasinya tak lepas dari hilangnya keadilan. (Said Aqil Siradj: 2014)
Namun kalau kita melihat apa yang dilakukan teroris selama satu dekade terakhir ini dengan melakukan aksi radikal bukan hanya dilatarbelakangi oleh faktor ketidakadilan. Ada faktor begitu kuatnya keyakinan kaum radikalis akan kebenaran ideologi agama yang mereka bawa. Sikap ini dibarengi dengan penafian kebenaran sistem lain yang akan diganti dalam gerakan sosial. Keyakinan tentang kebenaran program atau filosofi sering dikombinasikan dengan cara-cara pencapaian yang mengatasnamakan nilai-nilai ideal seperti kerakyatan atau kemiskinan.
Ada sejumlah benang merah yang bisa ditarik dari fakta radikalisme atas nama agama ini. Yaitu, pemahaman yang sangat literal terhadap ajaran Islam, keyakinan yang sangat kuat bahwa Islam adalah satu-satunya solusi bagi pelbagai krisis, perjuangan menegakan syariat Islam, resistensi terhadap kelompok yang berbeda pemahaman dan keyakinan, serta penolakan dan kebencian yang nyaris tanpa cadangan terhadap segala sesuatu yang berbau Barat. Namun, harus kita cermati pula bahwa pemahaman mereka itu tidak didasari oleh hati nurani dan fikiran terbuka. Mereka menolak sesuatu yang berbau Barat tapi menafikan bahwa aksi terorisme yang berkedok agama justru merupakan skenario Barat.
Padahal dalam kenyataannya, Islam di dunia, khususnya di Barat pasca tragedi 11 September 2001, menjadi agama dengan perkembangan terpesat. Peristiwa serangan teroris di Amerika Serikat dengan jatuhnya WTC (World Trade Center) ternyata tidak seperti yang disangkakan banyak orang. Bahwa serangan WTC itu sesungguhnya adalah wujud “kuburan dakwah” di Amerika Serikat. Justru sebaliknya, peristiwa kemanusiaan itu ternyata menjadi awal momentum kebangkitan kembali dakwah di Amerika dan Barat secara umum. Menurut estimasi yang ada, orang-orang Amerika yang memeluk agama Islam pasca tragedi 11 September 2001 naik minimal empat kali lipat dibandingkan sebelum peristiwa itu (Shamsi Ali: 2015).
Menjadi Agen Muslim
“Menjadi agen muslim” itulah yang harus kita lakukan sebagai umat Islam yang ingin merubah stigma buruk Islam di mata Barat. Seperti apa yang dikampanyekan oleh Hanum Salsabila Rais dan Rangga Almahendra dalam buku Bulan Terbelah di Langit Amerika yang sudah diadopsi menjadi sebuah film dengan judul sama. Buku tersebut mengabarkan kepada kita bahwa stigma buruk Islam di mata barat akibat adanya peristiwa teror 14 tahun lalu itu bisa diatasi dengan kita menjadi agen muslim yang baik. Bahkan ketika orang non-muslim ditanya “would the world be better without Islam?”. Mereka menjawab: ”No!”.
Mereka tidak sendiri mengampanyekan Islam yang berwajah damai tersebut. Shamsi Ali, Imam Besar Mesjid New York bersama Dompet Dhuafa, Urban Syiar, Elhijab (Elzatta), Fadhly (Padi Group), dan banyak lagi partner, termasuk Tali Foundation dan Insan Cendekia Madani, serta Darul-Qur’an, menginisiasi sebuah gerakan global dengan nama “Telling Islam to the world”. Gerakan itu telah Shamsi jalani di dunia Barat, khususnya di Amerika. Tapi, sadar akan tanggung jawab yang lebih besar sekaligus tantangan yang semakin kompleks, maka dirasa perlu untuk melakukan gerakan bersama dalam mengusung tanggung jawab ini.
Gerakan menyebarkan Islam ke seluruh dunia (“telling Islam to the world”) telah resmi diluncurkan di Jakarta pada 18 Desember 2015. Namun, implementasi utama digerakkan dari New York. Peluncurannya di Jakarta, ibu kota Indonesia, karena Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Tentu disadari atau tidak, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menyebarkan Islam yang sesungguhnya. Yaitu, Islam yang berwajah antitesis dengan wajah Islam yang dipersepsikan oleh dunia Barat saat ini. Oleh karena itu, gerakan “telling Islam to the world” yang akan mempertemukan antara Jakarta dan New York (connecting Jakarta to New York) dengan sinar Islam patut kita dukung dengan sepenuhnya. Bahwa Islam yang sejati adalah Islam yang berkarakter rahmatan lil-alamin. Islam yang ramah bukan yang penuh amarah. Islam yang seperti itulah yang dirindukan oleh dunia saat ini. Mari mengkampanyekannya!
*)Penulis adalah Awardee LPDP di UIN Maulana Malik Ibrahim dan Alumnus UIN Sunan Ampel Surabaya