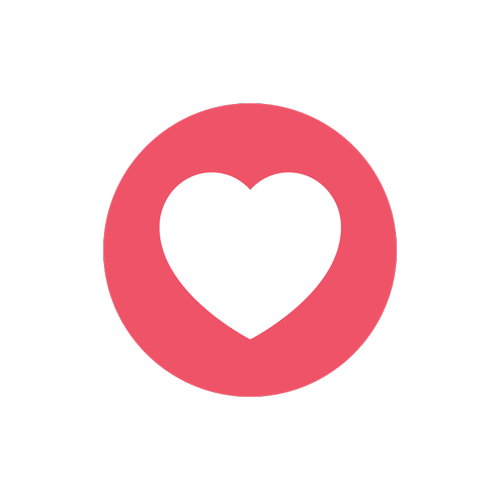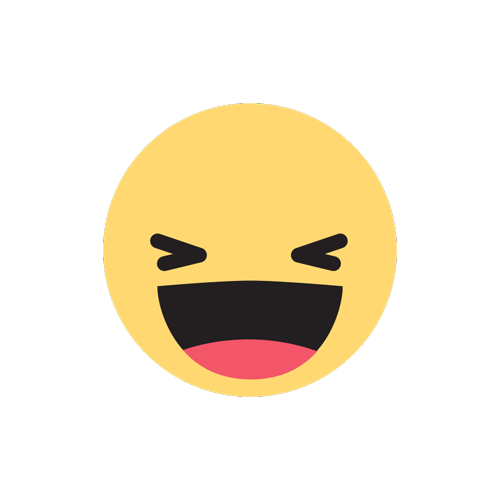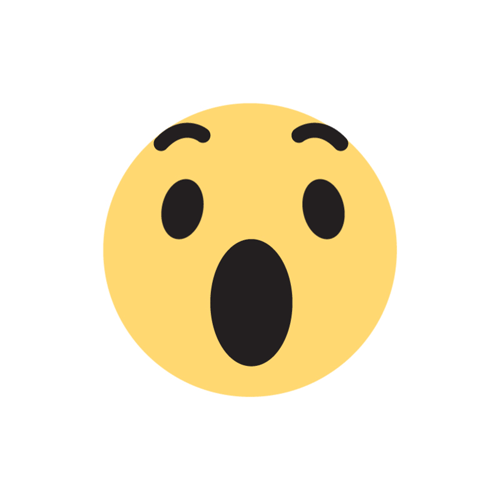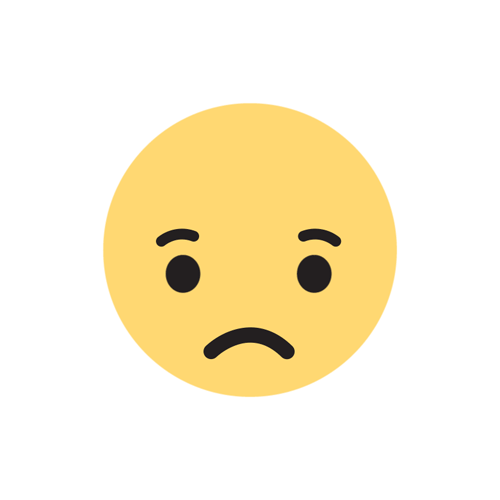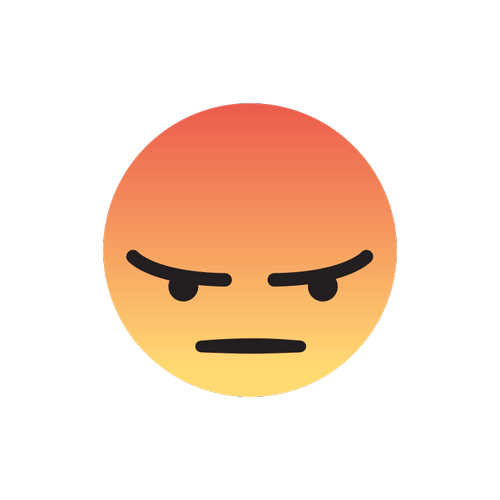Oleh: Dr. Ridwan Mahmudi MM., MAB
Dosen Magister Manajemen & Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Riau dan Pengamat Kebijakan Ekonomi & UMKM
Pemerintah baru saja mengambil langkah besar: mendepositokan dana Rp 200 triliun di bank-bank Himbara. Tujuannya mulia, mendorong agar kredit lebih deras mengalir ke sektor riil, sehingga roda ekonomi kembali berputar.
Namun, di balik kebijakan ini muncul pertanyaan yang menggigit, apakah pemerintah sedang menggerakan energi ke perekonomian, atau justru memindahkan masalah pelambatan ekonomi dari pundaknya sendiri ke pundak perbankan BUMN?
Latar Belakang Kebijakan
Kondisi fiskal Indonesia saat ini bisa dibilang serba terbatas. Belanja negara terus membesar (termasuk pembayaran hutang jatuh tempo dan bunganya), tapi ruang defisit kian sempit. Di saat yang sama, ekonomi juga lesu. Konsumsi masyarakat melemah, investasi belum pulih sepenuhnya, dan permintaan kredit tidak tumbuh signifikan.
Daripada menambah beban APBN lewat stimulus belanja baru, pemerintah memilih jalur “penempatan dana” di bank-bank milik negara. Dana Rp 200 Triliun ditempatkan di BRI, Bank Mandiri, dan BNI menerima masing masing Rp 55 triliun, kemudian BTN Rp 25 triliun, dan BSI Rp 10 triliun.
Argumentasinya sederhana, bank adalah jalur tercepat untuk menyalurkan likuiditas ke dunia usaha. Tambahan aturan pun ditegaskan. Yakni, dana Rp 200 T tersebut, tidak boleh digunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN). Artinya, uang itu benar-benar harus diputar lewat kredit, bukan sekadar parkir di instrumen keuangan.
Inilah pinternya Menkeu Purbaya. Dana Rp 200 Triliun itu tidak hilang, melainkan nitip taruh alias deposit dan mendapatkan bunga 4% per tahun, senilai Rp 8 Triliun. Sangat cerdik.
Sementara bagi bank, dana Rp 200 Triliun tersebut harus segera diolah menjadi kredit agar menghasilkan keuntungan untuk membayar bunga Rp 8 Triliun ke pemerintah. Bank bekerja keras menyalurkan kredit agar mampu membayar bunga ke pemerintah sekaligus menggerakkan Pembangunan yang jadi kewajiban pemerintah.
Bank Sebagai Mesin Eksekusi
Di atas kertas, strategi ini terlihat rapi. Pemerintah menggelontorkan dana murah, bank mendapat amunisi likuiditas, lalu menyalurkan kredit ke sektor prioritas seperti UMKM, manufaktur, dan pertanian.
Siklusnya diharapkan berlanjut, kredit cair, lalu berdampak produksi naik, lapangan kerja terbuka, orang berpenghasilan dan daya beli meningkat, sehingga secara keseluruhan ekonomi menggeliat.
Namun, realitas di lapangan tak sesederhana itu. Bank kini memikul beban besar sebagai “mesin eksekusi” kebijakan. Mereka harus mencari debitur yang layak, menyalurkan pinjaman di tengah permintaan yang belum pulih, sekaligus menjaga kualitas kredit agar tidak berubah menjadi kredit macet. Dengan kata lain, bola panas sudah ada di tangan bank.
Dalam situasi demikian, bank akan tarik gas kencang agar Rp 200 Triliun bisa terserap maksimal. Jika tidak, dia akan jadi beban bunga yang besar.
Tantangan dan Dampak pada Perbankan dan Ekonomi
Pertama, ada potensi mismatch antara suplai dan permintaan. Dana Rp 200 T tersedia, tetapi apakah dunia usaha benar-benar butuh kredit sebesar itu dalam kondisi ekonomi sekarang? Banyak pelaku UMKM masih berhati-hati memperbesar usaha karena daya beli masyarakat belum pulih penuh.
Kedua, risiko kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL). Jika bank dipaksa menyalurkan kredit secara agresif, peluang terjadinya kredit macet meningkat. Apalagi, pengalaman krisis mengajarkan bahwa ekspansi kredit yang dipaksakan biasanya berujung pada pembengkakan NPL.
Ketiga, tekanan terhadap rasio keuangan bank. Loan to Deposit Ratio (LDR) bisa melonjak, sementara margin bunga bersih (Net Interest Margin/NIM) bisa tergerus bila kredit disalurkan dengan bunga rendah. Artinya, kesehatan keuangan bank juga ikut dipertaruhkan.
Dampak pada perbankan dan ekonomi bisa memunculkan dua skenoria. Skenario optimistis, yaitu kebijakan ini berhasil. Kredit tersalur tepat sasaran, UMKM kembali bergairah, sektor manufaktur pulih, dan pertanian menyerap tenaga kerja. Ekonomi nasional terdorong tumbuh, sementara bank tetap menjaga kualitas asetnya.
Berikutnya, skenario pesimistis. Yakni, dana hanya berputar-putar di neraca bank tanpa terserap ke dunia usaha, atau malah tersalur tetapi menimbulkan kredit macet.
Dalam kasus ini, reputasi bank akan tercoreng, sementara ekonomi tetap stagnan. Lebih jauh lagi, publik bisa menilai pemerintah sekadar “lempar batu sembunyi tangan”—mengarahkan bank bekerja keras memutar ekonomi, sementara dirinya menghindari langkah fiskal yang lebih berat.
Analisis Teoritis
Dari sisi teori intermediasi keuangan, bank memang berperan sebagai perantara antara pemilik dana dan dunia usaha. Tetapi intermediasi tidak bisa bekerja optimal bila permintaan kredit lemah. Dalam kondisi ini, penempatan dana pemerintah lebih banyak menambah “supply of fund” ketimbang mendorong “demand for fund.”
Ada juga risiko crowding out. Ketika pemerintah menempatkan dana besar di bank, bisa saja bank menjadi terlalu fokus menyalurkan kredit berbasis penugasan, sementara pembiayaan ke sektor lain terpinggirkan. Efektivitas multiplier fiskal pun dipertanyakan, apakah injeksi Rp. 200 T ini memberi dampak nyata ke PDB, atau hanya menambah beban administratif di perbankan?
Penutup
Kebijakan mendepositokan Rp 200 T ke bank Himbara adalah langkah berani sekaligus penuh risiko. Jika berhasil, kebijakan ini bisa menjadi contoh inovasi fiskal-moneter yang saling menopang. Dan sebagaimana Menkeu sampaikan, mungkin akan ditempatkan dana yang lebih besar lagi.
Jika gagal, dana besar itu bisa menjadi simbol bagaimana pemerintah memindahkan masalah ke pundak perbankan. Pertanyaannya kini sederhana namun krusial, apakah bank mampu menanggung beban yang semestinya ditanggung oleh kebijakan fiskal langsung? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah jurus Rp 200 T tercatat sebagai terobosan, atau justru sekadar menunda masalah fundamental ekonomi kita.
Lebih dalam lagi, akan menghasilkan perdebatan mengenai peran negara vs perbankan dalam pemulihan ekonomi. Seharusnya, negara hadir dengan kebijakan fiskal langsung—misalnya mempercepat belanja infrastruktur atau subsidi targeted—bukan sekadar menitipkan tanggung jawab itu pada bank. (*)