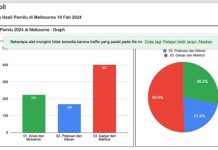Tatik Muflihah, S.Pd., M.Pd – Dosen S1 Pendidikan Bahasa Inggris
DALAM Wikipedia, genderuwo sebagai mitos Jawa sejenis bangsa jin atau makhluk halus berwujud manusia mirip kera yang bertubuh besar dan kekar dengan warna kulit hitam kemerahan, tubuhnya ditutupi rambut lebat yang tumbuh di sekujur tubuh.
Menyeramkan sekali, demikianlah jika disederhanakan. Seperti sontoloyo, kata genderuwo yang dimaksudkan Jokowi tentu tidak sama dengan makna menurut definisi Wikipedia.
Tentu tidak sulit bagi kita memahami untuk apa kata genderuwo diucapkan dan kepada siapa itu ditujukan. Mitologi Jawa mengartikan genderuwo merupakan sosok menyeramkan atau menakutkan yang dikaitkan dengan tempat-tempat wingit, gedung-gedung tua, rumah-rumah kosong dan lain sebagainya.
Orangtua Jawa biasanya menggunakan istilah genderuwo untuk menakut-nakuti anak agar tidak main di tempat-tempat seperti disebut, atau tidak keluar di waktu malam sendirian. “Awas ada genderuwo lho”, begitu peringatan para orang tua Jawa kepada anak-anak mereka.
Dalam kontestasi politik menjelang pilpres 2019 saling menyerang lawan secara verbal adalah hal biasa. Dua kosakata sontoloyo dan genderuwo oleh Jokowi tentu ditujukan ke lawan-lawan politiknya yang terus menyerang dirinya.
Jika sontoloyo ditujukan ke lawan-lawan politik yang dianggap ‘asal njeplak’(dalam bahasa Jawa) bicara (tanpa data), konyol, tolol dan sebagainya, maka kata genderuwo ditujukan ke lawan-lawan politik yang suka menakut-nakuti rakyat dengan melontarkan isu-isu negatif yang menyeramkan.
Dalam perspektif sosiolinguistik, setiap era kepemimpinan diyakini menghadirkan wacana kebahasaan yang berbeda dengan era kepemimpinan lainnya. Jokowi yang lahir dari keluarga Jawa, tumbuh dan hidup dalam kultur Jawa yang kental (Solo) mengenalkan istilah dalam bahasa Jawa yang hanya bisa dipahami secara utuh oleh orang Jawa. Istilah sontoloyo dan genderuwo dibawa dalam arena politik sebagai piranti meng-counter lawan politik menjelang pilpres.
Jokowi menggunakan dua kosakata khas itu bisa jadi karena sudah tidak bisa menemukan kosakata dalam bahasa Indonesia yang tepat untuk menggambarkan sosok lawan politiknya yang tidak henti-hentinya menyerang.
Pada kesempatan yang lain baru-baru ini, Jokowi melontarkan kata “tabok” kepada orang-orang yang selama ini menuduhnya sebagai anggota PKI, alias Partai Komunis Indonesia. “Tabok” juga kosakata khas Jawa (Detik.com 10/11/2018).
Berkali-kali Presiden Jokowi menjelaskan di berbagai kesempatan bahwa dia dan keluarganya bersih dari unsur PKI, bahkan ketika PKI memberontak tahun 1965 usianya baru 4 tahun. Namun demikian hingga saat ini tuduhan itu masih tetap saja terjadi. Apa artinya “tabok”? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “tabok” berarti memukul (kepala dan sebagainya) dengan telapak tangan, menampar.
Sebenarnya jika dibanding dengan kata “sontoloyo” dan “genderuwo” , makna kata “tabok” lebih keras. Dua kosakata sebelumnya ada unsur humornya, sedang kata tabok mengandung aspek kekerasan fisik. Mungkin Jokowi sangat geram ketika dituduh sebagai anggota PKI. Sebab, PKI adalah partai terlarang di Indonesia.
Bisa dibayangkan jika seseorang benar-benar terbukti menjadi anggota PKI, apalagi seorang pemimpin, maka habis sudah seluruh perjalanan kariernya. Sebab Partai Komunis dianggap melawan Pancasila, sehingga pantas dimusnahkan. Oleh Joko Santoso (Kompas,2/9/2017) praktik demikian disebut sebagai bahasa tuduh. Karena itu, kemarahan Jokowi sangat bisa dimaklumi. Ucapan itu menggambarkan bahwa kemarahan Jokowi sudah sampai puncak.
Di masa-masa akhir kekuasaannya yang mulai rapuh dan digoyang oleh berbagai kekuatan oposisi, Pak Harto pernah melontarkan kata “gebuk” untuk lawan-lawan politiknya. Tak pelak lontaran Pak Harto juga menghebohkan dunia perpolitikan tidak saja di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri.
Sebab, Pak Harto biasanya kalem dalam berbahasa dan jarang melontarkan kata-kata keras dan kasar. Pak Harto sepertinya sudah tidak kuasa menahan emosi ketika pemerintahannya mulai digoyang dan aksi-aksi dari yang tidak puas sudah mulai muncul di mana-mana.
Rupanya setiap pemimpin memproduksi kosakata khas sesuai keadaan masyarakat dan latar sosial-kultural sang pemimpin. Kita mungkin masih ingat ketika Gus Dur menjadi presiden (20 Oktober 1999-23 Juli 2001) dan Amien Rais sebagai Ketua MPR, yang sama-sama berasal dari organisasi keagamaan (Islam) besar, istilah-istilah khusus bermuatan agama juga muncul begitu deras, seperti istighosah, jihad, bughat, islah, bahtsul masail, tausyiah dan lain -lain.
Istilah-istilah itu tidak lepas dari latar sosial dan kultural Gus Dur yang lahir dan tumbuh dalam lingkungan pondok pesantren, dan sehari-hari berprofesi sebagai kyai. Anggota masyarakat yang tidak akrab dengan kultur pesantren bisa jadi bingung memahami istilah-istilah itu.
Oleh Artha (2002: 42) Gus Dur disebut menumbuhkan iklim religiopolitik, yang dapat ditafsirkan sebagai bangkitnya pengabsahan penggunaan simbol agama dan dalih agama untuk kepentingan politik. Karena wacana itu muncul dalam wujud verbal, lebih tepatnya Gus Dur disebut membangun iklim “religiopolitikolingusitik”, yakni fenomena bahasa bermuatan nilai-nilai agama yang digunakan dalam arena pertarungan politik, sehingga di dalamnya ada tiga komponen, yaitu agama, politik, dan bahasa hadir bersamaan dalam wadah wacana politik.
Sepertinya tidak mau kalah dengan Gus Dur, dalam himbauannya kepada para elite politik dan penyelenggara negara agar dapat menciptakan iklim politik yang sejuk, PB NU sebagai wadah organisasi massa terbesar di Indonesia juga tidak kalah aktifnya memproduksi istilah-istilah khas pondok pesantren, seperti taushiyah (nasihat), tawasuth (jalan tengah), tawazun (seimbang), dan tasamuh (toleran) (Kompas, 31/3/2001).
Jika Gus Dur yang berlatar belakang pondok pesantren dengan tradisi keislaman yang kental menumbuhkan fenomena “religiopolitikolinguistik”, maka Jokowi yang berlatar sosial dan kultural Jawa yang kental (Solo) tanpa disadari mengembangkan apa yang disebut sebagai “etnopolitikolinguistik”, yakni fenomena bahasa khas oleh etnik tertentu yang digunakan dalam arena politik.
Munculnya fenomena demikian menggambarkan masyarakat memiliki ruang ekspresi yang sangat longgar di tengah demokratisasi di Indonesia yang terus berlangsung. Di satu sisi kita merasa prihatin jika pertarungan para elite politik dapat memperkeruh suasana kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi di sisi yang lain kita dapat menyaksikan munculnya fenomena kebahasaan yang menarik. Sebab, bahasa hadir tidak saja sebagai alat komunikasi sebagai fungsi hakikinya, tetapi juga menjadi piranti perjuangan para elite politik.
Marsudi dkk (2013) menyatakan bahwa bagi penguasa, bahasa dapat digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya. Lebih jauh lanjut, mereka menyatakan bahwa untuk menguasai kekuasaan (pikiran) rakyat diperlukan alat komunikasi yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.
Dalam bahasa politik, bahasa penguasa dapat dimanfaatkan untuk membujuk dan merayu serta diajak melakukan tindakan-tindakan tertentu demi mencapai tujuan dan kepentingan pribadi penguasa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Khaidir Anwar (1984:59) bahwa bahasa politik dapat mencapai kehalusan yang tinggi, yaitu dapat membungkus yang busuk menjadi tidak busuk, yang jelek menjadi baik, dan ancaman dinyatakan dengan halus dan beradab.
Informasi, gagasan, pendapat, sikap politik, imajinasi dan pilihan kebijakan semuanya disampaikan dalam bahasa dan melalui bahasa. Secara akademik, fenomena demikian dapat mengembangkan kajian linguistik diakronik secara lebih leluasa. Selain media massa, figur publik adalah produsen bahasa yang efektif. Gaya bahasa elite biasanya ditiru pengikutnya, dan setidaknya bisa menjadi medan diskusi dari berbagai sudut pandang.
Pertanyaannya ialah efektifkah penggunaan istilah-istilah seperti itu untuk membangun kekuatan dalam kontestasi politik? Untuk menjawabnya para ahli bahasa dan ilmu politik bisa melakukan penelitian secara bersamaan.
Kajian bahasa secara diakronik bisa mempertemukan disiplin ilmu linguistik dengan disiplin lainnya tidak saja secara teoretik dalam ranah, tetapi secara praktik di lapangan. Seiring dengan kemajuan dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks, bertemunya dua atau lebih disiplin ilmu yang berbeda untuk melihat satu persoalan yang sama sudah bukan hal baru. Fenomena etnopolitikolinguistik adalah sebuah tawaran untuk direnungkan para ahli dan peminat studi bahasa diakronik untuk membangun masyarakat dengan bahasa yang santun di negeri ini. *