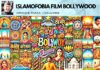Tanggal 19 Agustus 2021, Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, kemudian diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2021, selang satu hari setelah penetapannya.
Inisiatif dan pemikiran besar Kepolisian RI patut kita apresiasi karena telah melakukan terobosan baru dalam dunia praktik penegakan hukum dengan tidak lagi menjadikan pidana pemenjaraan sebagai instrumen untuk membuat pelaku kejahatan menjadi jera dan bertobat. Paling tidak, Kepolisian RI telah melihat segala aspek dan segala sisi dari pelaku kejahatan maupun korban dengan mencari jalan yang paling terbaik agar pelaku kejahatan tidak selalu berakhir di balik jeruji besi.
Kebijakan Kepolisian RI tersebut pasti menuai pro dan kontra dari berbagai macam kalangan. Bagi mereka yang memiliki cara pandang tentang pemenjaraan bukan satu-satunya tempat mendidik narapidanatentu akan setuju. Sebaliknya, bagi mereka yang memiliki cara pandang bahwa pemenjaraan sangat penting diterapkan bagi pelaku kejahatansebagai efek jera untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang, tentu tidak akan setuju dengan kebijakan tersebut.
Sanksi Pidana dan Efeknya
Topo Santoso (Seksualitas dan Hukum Pidana, 1997) dengan mengutip teori relatif dan teori tujuan menyatakan suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana, tapi harus dipersoalkan urgensi dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat dan pelaku kejahatan itu sendiri. Dasar hukum dari hukuman adalah pertahanan tata tertib masyarakat, dimana tujuan dari hukuman untuk menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Hukuman bisa bersifat menakutkan, memperbaiki, atau bahkan membinasakan.
Kita meyakinibahwa pidana penjara sebenarnya memiliki plus-minus bagi pelaku, keluarga pelaku, maupun korban dan keluarga korban. Artinya, bagi pelaku kejahatan besar sangat dimungkinkan menerima pemidanaan sangat berat sebagaimana kejahatan yang dilakukannya. Hukuman penjara yang begitu lama tentu dirasakan sangat menyiksa pelaku. Belum lagi, hukuman sosial dari mayarakat luas akan diterima keluarga pelaku sebagai konsekuensi yang tidak hanya sekedar “stigma negatif”, tapi jugaberdampak terhadap pembatasan pergaulan, pekerjaan, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan sosial-kemasyarakatan.
Disisi lain, kejahatan ringan yang tidak bisa diselesaikan secara mediasi antara korban dengan pelaku serta harus berakhir dengan sanksi pemenjaraan, lambat laun akan menimbulkan “tekanan batin” bagi korban itu sendiri, karena telah menjadikan sanksi pidana sebagai “balas dendam” terhadap pelaku secara langsung maupun keluarga pelaku secara tidak langsung. Dengan demikian, pidana penjara bagi pelaku kejahatan menjadi menakutkan atau bahkan sangat menakutkan, bisa juga menjadi perantara bagi pelaku untuk sadar dan berusaha memperbaiki diri, atau yang paling buruk akan membuat “binasa” pelaku, baik secara fisik, mental, maupun masa depan diri dan keluarga yang ditinggalkannya.
Restorative Justice: Kompromi Korban-Pelaku
Pasal 5 dan Pasal 6 Perpol tentang keadilan restoratif mengatur persyaratan materiil terhadap tindak pidana yang dapat direstoratif, yakni: (a) tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat: (b). tidak berdampak konflik sosial; (c). tidak berpotensi memecah belah bangsa; (d). tidak bersifat radikalisme dan separatisme; (e). bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan (f). bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.
Sedangkan, persyaratan formil yang harus dipenuhi, yaitu: (a). perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali tindak pidana narkoba, dimana perdamaian tersebut dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak. (b). pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali tindak pidana narkoba. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku dapat dilakukan dengan cara mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana, dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.
Karim (Ius Constituendum: Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice, 2019) menyatakan keadilan restoratif bertujuan memberikan rasa keadilan dengan tidak diproses sampai ke pengadilan, mengingat kejahatan yang dilakukan tidak sebanding dengan proses hukum yang dilalui. Dengan demikian, sangat tepat manakala perkara pidana yang tidak masuk dalam kategori tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Perpol tentang keadilan restoratif bisa diselesaikan melalui mediasi di tingkat kepolisian yang dilalui dengan kesepakatan/kompromi antara pelaku dengan korban.
Namun, bagaimana seandainya korban maupun keluarga korban tidak mau memaafkan pelaku? hal ini menjadi pertanyaan besar karena Perpol tersebut tidak mengatur “langkah-langkah khusus” aparat kepolisian (penyidik) untuk menghentikan proses pidana. Artinya, aparat kepolisian (penyidik) tidak bisa melakukan intervensi terhadap korban maupun keluarga korban, apalagi melakukan penghentian perkara secara sepihak, karena hal itu akan melanggar hak asasi korban, KUHAP, UU Kepolisian, dan juga Perpol itu sendiri.
Akhirnya, meskipun Perpol tentang keadilan restoratif merupakan terobosan yang luar biasa dari Kepolisian RI, tapi masih banyak kelemahan-kelemahan yang perlu dibenahi di dalamnya melalui masukan berbagai pihak dengan tujuan penerapan hukum di tingkat kepolisian lebih seimbang antara pencegahan (preventif) dengan penindakan (represif) dan tidak selalu diorientasikan terhadap pemenjaraan, melainkan melalui kesepakatan/kompromi yang legal. Wallahu A’lam !
*Direktur LBH Sahabat Keadilan Nasional&Alumni Magister Hukum UTM Bangkalan