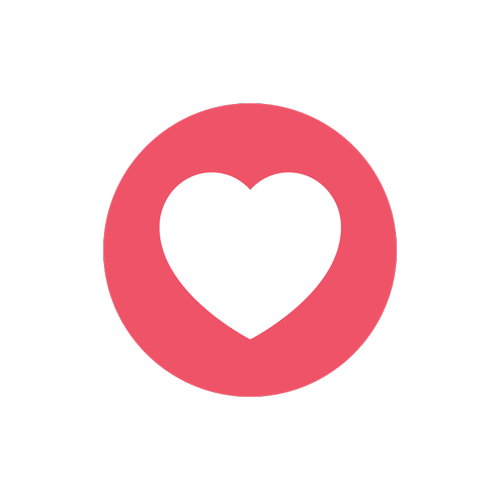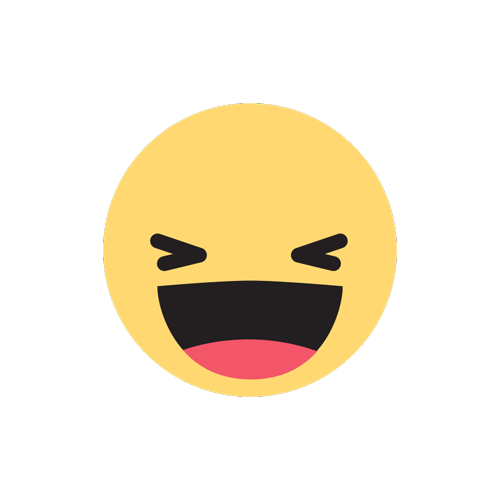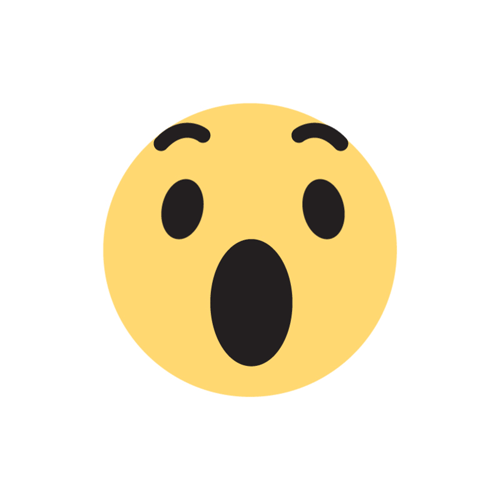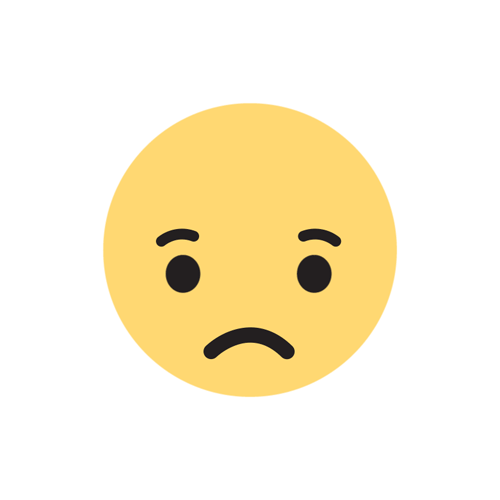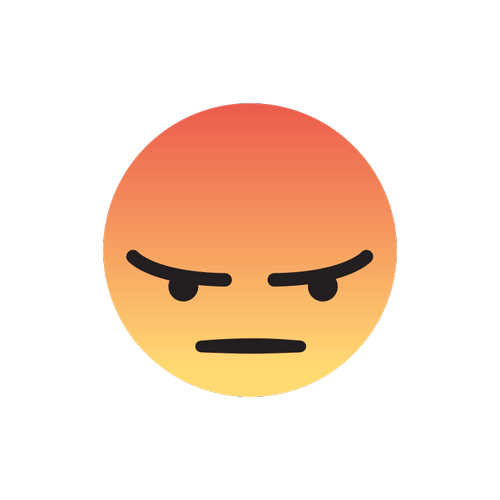“Jangan takut mati, sebab mati syahid menunggu bagi siapa yang berjuang membela tanah air.”
Oleh Irwan Setiawan*
KALIMAT itu menggema dari pesantren ke kampung-kampung Jawa Timur pada Oktober 1945. Sebuah seruan yang melahirkan gelombang besar perlawanan terhadap penjajah. Dari langgar dan surau, para kyai dan santri berduyun-duyun turun ke medan laga. Mereka membawa doa, tekad, dan bambu runcing — tapi semangatnya melampaui senjata modern mana pun.
Hari ini, delapan dekade kemudian, gema itu masih terasa. Setiap 22 Oktober, bangsa ini memperingati Hari Santri Nasional — hari di mana semangat jihad dan nasionalisme berpadu dalam satu napas perjuangan.
Sejarah mencatat, Resolusi Jihad yang dikumandangkan Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari bukan hanya fatwa keagamaan, tetapi juga panggilan kebangsaan. Seruan itu mendorong rakyat mempertahankan kemerdekaan dengan keyakinan bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman.
Dari sinilah api Perang 10 November 1945 menyala — perang heroik yang meneguhkan identitas bangsa: bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil keringat, darah, dan doa.
Kini, bentuk jihad memang berubah. Santri tidak lagi berhadapan dengan meriam dan senapan, tetapi dengan tantangan kebodohan, kemiskinan, disinformasi, dan krisis moral. Perjuangan hari ini bukan mempertahankan kemerdekaan fisik, melainkan memakmurkan kemerdekaan itu sendiri.
Pesantren sebagai model kecil dari sistem tata kelola yang ideal. Di sana ada kepemimpinan moral (kyai), ada struktur sosial yang tertib (santri dan asrama), dan ada etos pelayanan yang tinggi (pengabdian masyarakat).
Nilai-nilai ini — keikhlasan, disiplin, tanggung jawab, dan solidaritas — adalah soft power yang dibutuhkan birokrasi publik kita hari ini.
Birokrasi yang bersih tak cukup dengan regulasi, tapi butuh spirit moral seperti yang tumbuh di pesantren. Ketika santri menghafal Al-Qur’an, ia belajar disiplin. Ketika ia mencuci piring dan menyapu halaman, ia belajar tanggung jawab. Ketika ia hormat pada kyai, ia belajar tentang adab dan hierarki.
Nilai-nilai ini, jika diterapkan dalam administrasi publik, bisa melahirkan pemerintahan yang melayani, bukan dilayani.
Dalam perspektif akademik, ada beberapa teori yang menjelaskan peran strategis pesantren dan santri.
Pertama, Modal Sosial (Robert Putnam) — kekuatan jaringan, kepercayaan, dan gotong royong yang menggerakkan masyarakat. Pesantren memiliki semua itu dalam wujud nyata.
Kedua, Pendidikan Karakter (Thomas Lickona) — santri dididik untuk jujur, disiplin, dan tangguh, bukan sekadar pandai.
Ketiga, Transformasi Sosial (Paulo Freire) — pesantren memerdekakan manusia dari kebodohan, menumbuhkan kesadaran kritis, dan membentuk kemandirian.
Artinya, pesantren bukan hanya lembaga pendidikan agama, tapi mesin pembentuk peradaban.
Menatap visi Indonesia Emas 2045, peran santri tidak bisa diremehkan. Santri harus hadir di ruang publik, pemerintahan, bisnis, bahkan diplomasi global. Santri tidak boleh minder di era digital, karena sejatinya mereka adalah digital native of morality — generasi yang bisa memadukan teknologi dan akhlak.
Santri adalah jembatan antara masa lalu yang penuh nilai dan masa depan yang penuh tantangan. Mereka harus menjadi inovator sosial, penggerak ekonomi umat, dan penjaga moral bangsa.
Peringatan Hari Santri seharusnya menjadi momen reflektif: sejauh mana semangat jihad dan pengabdian itu masih hidup dalam diri kita.
Dulu, santri berjuang dengan bambu runcing.
Sekarang, santri berjuang dengan pena, data, dan gagasan.
Jihad santri hari ini adalah bekerja dengan jujur, melayani dengan ikhlas, dan berkarya untuk kemajuan bangsa.
Karena negeri ini butuh bukan hanya orang pintar, tapi juga orang benar — dan di situlah santri seharusnya berdiri.(*)
*Irwan Setiawan adalah Mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik Universitas Hang Tuah Surabaya, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim Periode 2009 – 2014 dan 2014 – 2019