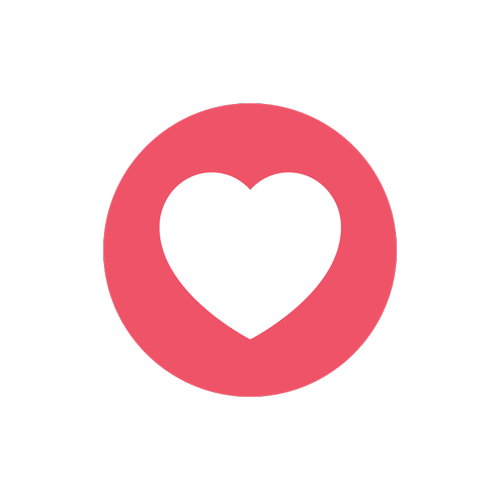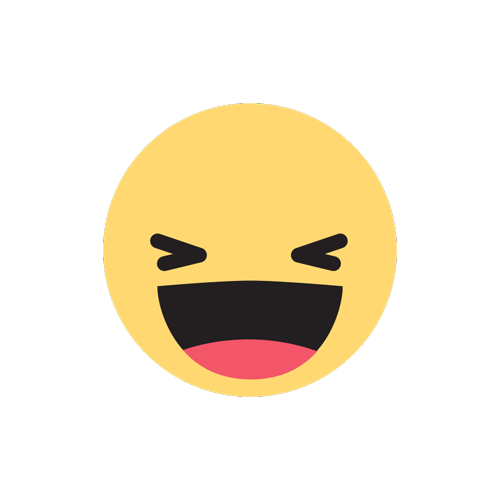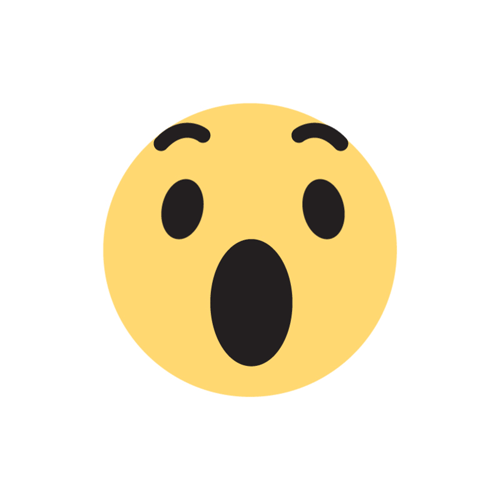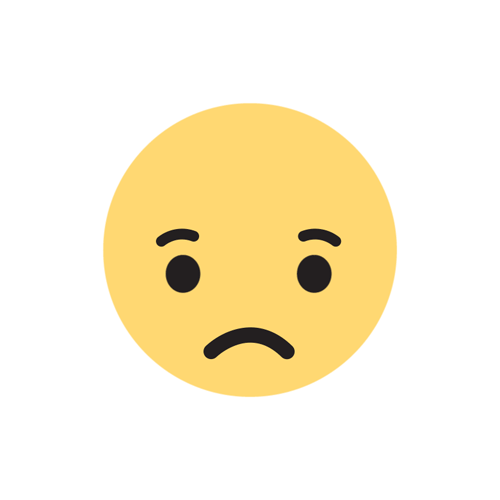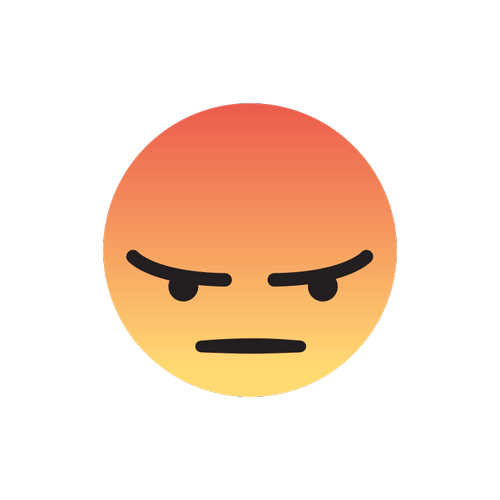“Dua peristiwa besar yang menggores nurani publik ini, memunculkan pertanyaan penting. apakah penyelesaian atas musibah ini cukup dengan pendekatan kearifan, atau penegakan jalur hukum?”
Oleh M Fadeli*
PERINGATAN Hari Santri Nasional (HSN) pada tanggal 22 Oktober 2025 merupakan momentum penting untuk mengenang perjuangan para santri dan kiai dalam menjaga keutuhan bangsa dan menegakkan nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin. Namun, menjelang peringatan HSN, dunia santri justru diuji dengan dua peristiwa besar yang mengguncang nurani umat dan menorehkan luka mendalam.
Pertama musibah yang menimpa Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Pada Senin, 29 September 2025, sekitar pukul 15.00 WIB, bangunan mushola di lingkungan pesantren tersebut roboh saat digunakan untuk salat Ashar berjemaah.
Operasi evakuasi berlangsung dramatis selama tujuh hari penuh. Tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI, Polri, serta ratusan relawan masyarakat bekerja siang malam menyelamatkan para korban selamat maupun meninggal.
Pada 7 Oktober 2025, operasi pencarian resmi ditutup dengan catatan 63 santri meninggal dunia dan 104 santri lainnya berhasil diselamatkan dalam kondisi luka-luka maupun trauma.
Duka mendalam menyelimuti keluarga besar pesantren, masyarakat Jawa Timur, hingga Umat Islam Indonesia. Tidak hanya ucapan simpati dan bela sungkawa yang mengalir, namun juga muncul komentar nyinyir dan sikap merendahkan. Sebagian kalangan di media sosial yang mendiskreditkan kehidupan tradisional pondok pesantren dan para pemangkunya.
Sejumlah pejabat negara turun langsung ke lokasi sebagai bentuk empati dan tanggung jawab. Hadir Menteri Agama, Menterian PUPR, Menteri Sosial, Kemenko PM, Gubernur Wakil Gubenrur Jawa Timur, serta Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo.
Tragedi ini menjadi pengingat semua pihak betapa pentingnya pengawasan terhadap infrastruktur lembaga pendidikan, khususnya pesantren yang kerap dibangun dengan swadaya dan minim pendampingan teknis. Tragedi Al Khoziny adalah luka kolektif umat Islam. Setiap nyawa yang hilang bukanlah sekadar angka, melainkan anak-anak bangsa yang tengah menuntut ilmu dan memperjuangkan masa depannya.
Kedua, belum kering air mata atas tragedi Al Khoziny, dunia pesantren kembali terusik oleh sebuah tayangan yang dianggap merendahkan martabat pesantren. Program “Xpose Uncensored” yang ditayangkan Trans7 pada Senin, 13 Oktober 2025, menyajikan segmen yang dinilai menyinggung Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri, Jawa Timur.
Salah satu pesantren tertua dan paling berpengaruh di Indonesia serta mencederai kehormatan KH Anwar Manshur selaku pengasuh utamanya. Kemudian tidak hanya menyinggung keluarga besar Ponpes Lirboyo Kediri akan tetapi juga melukai kehidupan pesantren di Indonesia.
Konten tersebut langsung menuai kecaman keras dari para santri, alumni, tokoh agama, dan masyarakat umum. Tayangan itu tidak hanya dianggap menghina salah satu tokoh karismatik dunia pesantren, tetapi juga memperlihatkan minimnya media terhadap pemahaman nilai-nilai luhur, nilai-nilai kultural komunitas pesantren di Indonesia.
Walaupun pihak Trans7 telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan mengakui adanya kelalaian dalam pengawasan terhadap konten yang diproduksi oleh PH (production house) mitra Trans 7. Namun, gelombang kekecewaan tidak mereda begitu saja. Tagar #BoikotTrans7 sempat menjadi trending topic nasional sebagai bentuk protes kolektif dari publik.
Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, menanggapi peristiwa ini dengan menegaskan bahwa pesantren merupakan pusat pembentukan moral, karakter, dan kemanusiaan bangsa. Juga mengajak semua pihak untuk menjaga marwah pesantren sebagai institusi yang telah berjasa dalam membentuk peradaban dan kebangsaan Indonesia.
Pemerintah harus hadir lebih konkret dalam menjamin keselamatan dan kualitas infrastruktur pendidikan agama, termasuk membenahi sistem izin, pengawasan, dan standarisasi bangunan pesantren. Media massa harus lebih sensitif terhadap nilai-nilai budaya dan keagamaan yang hidup di masyarakat, serta meningkatkan etika dalam penyajian konten. Sementara itu, dunia pesantren harus memperkuat integritas, profesionalisme, dan adaptasi kurikulum pengajaran sesuai kebutuhan zaman tanpa kehilangan jati dirinya.
Memahami bahwa memang Pesantren ada yang dikelola secara modern atau Pondok Moderen selain mengajarkan kitab kuning juga memiliki kurikulum formal, terdapat lembaga pendidikan formal. Disisi lain masih banyak juga pondok yang dikelola secara salafi atau pondok salafiah yang notabene hanya mengajarkan kitab-kitab kuning klasik tanpa kurikulum formal, biasanya tanpa sistim administrasi yang ketat dan dana sumbangan terbatas. Namun demikian pola komunikasi kultural menjadi pedoman atas keberlangsungan kehidupan Pondok Pesantren.
Dalam konteks budaya khas pesantren, yang dibentuk oleh nilai-nilai keislaman, tradisi lokal, serta relasi sosial yang bersifat hierarkis namun penuh penghormatan. Pola komunikasi ini tidak sekadar menyampaikan pesan verbal, tetapi juga melibatkan simbol, gestur, etika, dan nilai adab (sopan santun) yang sangat tinggi.
Artinya komunikasi kultural dalam dunia pesantren bukan sekadar bagaimana pesan disampaikan, tetapi juga bagaimana adab, makna, dan nilai disematkan dalam setiap tutur dan gestur. Menjadikan pesantren sebagai ruang pendidikan karakter yang otentik.
Dua peristiwa besar yang menggores nurani publik memunculkan pertanyaan penting apakah penyelesaian atas musibah ini cukup dengan pendekatan kearifan, atau penegakan jalur hukum?
Dalam konteks ambruknya Ponpes Al Khozini, penegakan hukum menjadi keniscayaan. Polisi perlu melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan. Jika ditemukan unsur kelalaian konstruksi yang mengakibatkan hilangnya nyawa, maka kemudian harus ada yang bertanggungjawab.
Namun, pendekatan hukum dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kearifan budaya pesantren yang selama ini menjadi pusat moral dan etika. Jika Polri perlu melakukan tindakan tegas namun tetap terukur, tidak menimbulkan stigma seolah olah pesantren “tidak profesional”. Pendekatan humanis berbasis dialog dengan para kiai dan tokoh lokal perlu diutamakan dalam proses komunikasi publik.
Langkah ini penting untuk menghindari generalisasi negatif terhadap pesantren secara keseluruhan. Kita tidak ingin tragedi ini berubah menjadi pembunuhan karakter kolektif terhadap lembaga pendidikan Islam tradisional yang justru telah lama berjasa mencetak generasi bermoral.
Terkait Program “Xpose Uncensored” tayang di Trans7, banyak pihak mempertanyakan apakah cukup dengan permintaan maaf? Apakah pendekatan tabayyun (klarifikasi) sesuai dengan tradisi pesantren sudah menyelesaikan masalah? Ataukah melalui jalur hukum melalui UU ITEatau UU Penyiaran jika ditemukan unsur pelanggaran hukum misalnya pencemaran nama baik.
Pesantren bukan sekadar lembaga pengajaran agama, tetapi pusat pembentukan nilai, karakter, dan peradaban bangsa. Reputasi pesantren adalah marwah bersama yang harus dijaga. Sekali ia dicederai, maka seluruh komunitas turut menanggung dampaknya.
Hari Santri adalah milik kita semua. Maka, duka para santri, luka lembaga pesantren, dan martabat kiai serta ulama adalah tanggung jawab kita bersama. Peristiwa ini bukan hanya menjadi headline sesaat, tetapi menjadi panggilan nurani untuk bertindak bijak, adil, dan bertanggung jawab.
Kedua peristiwa ditersebut menandai peringatan Hari Santri 2025 dengan suasana yang jauh dari gegap gempita. Hari Santri harus dijadikan momentum evaluasi diri, bukan hanya menjadi seremoni tahunan. Sudah saatnya menjadikan Hari Santri bukan sekadar pengakuan simbolik, tetapi sebagai momentum nyata untuk memperbaiki proses pembelajaran yang adaptif kontekstual sesuai kebutuhan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai adab dan ahlaq. (*)
*M Fadeli adalah Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Fisip Ubhara Surabaya.