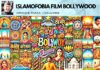Oleh: M. Shoim Anwar
Sejarah adalah lintasan peristiwa yang telah lampau. Sejarah berada dalam ketegangan karena keberadaannya dipengaruhi oleh kekuatan informasi yang beredar. Makin kuat informasi yang diedarkan, makin kuat pula sejarah dipengaruhi. Sejarah seharusnya adalah “kebenaran”, namun berbagai kepentingan yang didesakkan dapat pula membelokkan arah sejarah. Pihak penguasa beserta lingkarannya memiliki andil lebih besar untuk mengubah sejarah.
Sejarah bukan saja menyangkut peristiwa. Aktor sejarah, pribadi seseorang misalnya, menjadi subjek penting keberadaan sejarah. Dalam konteks inilah kita kembali mengingat Gus Dur (K.H. Abdul Rahman Wahid, Presiden ke-4 RI ) sebagai pribadi yang kompleks. Hampir selalu ada ruang untuk membicarakannya dari berbagai sisi yang kita pilih. Ibarat pohon yang tinggi, terpaan terhadap Gus Dur semasa hidup juga tidak kalah santer. Para pengikutnya, sering disebut “gusdurian”, dan para penentang sering bersitegang. Puncaknya, dia diturunkan oleh parlemen dari jabatan presiden sebelum masanya habis. Khas senimannya pun muncul, sebelum meninggalkan istana, Gus Dur menyapa para pendukungnya di depan istana sambil pakai kaos dan celana kolor.
Pamor Gus Dur ternyata tidak meredup. Di tengah kegalauan politik yang acap kali terjadi, tidak sedikit orang yang merindukan sosok seperti Gus Dur. Mungkin sebuah romantisme. Gus Dur berubah dari realita menjadi citra. Dalam kedudukannya sebagai citra, pandangan yang subjektif tentunya, Gus Dur ditempatkan sebagai sosok yang “sempurna”.
Makam Gus Dur di Tebu Ireng Jombang menjadi makin ramai oleh para penziarah. Menziarahi makam Gus Dur, terutama bagi para nahdliyin, menjadi rangkaian paket ziarah ke makam para wali lainnya. Di sekitar makamnya, Gur Dur “menghidupi” para santri, pedagang kaki lima, sopir, kernet, pemilik kereta kelinci, tukan parkir, dan ada juga pengemis. Mitos-mitos baru tentang Gus Dur juga bermunculan. Wacana bahwa Gus Dur adalah “wali kesepuluh” makin sering terdengar, meski kita juga tidak tahu siapa yang paling berhak memberi kriteria dan gelar tersebut.
Di dunia perpuisian Indonesia, representasi Gus Dur dihadirkan pula oleh para penyair melalui puisi. Di dunia seni lukis Gus Dur sering digambarkan sebagai Semar. Sedangkan dalam perpuisian yang muncul adalah puja sastra, yaitu karya sastra digunakan untuk memuja atau mengunggulkan sosok dan peran seseorang.
Dalam berbagai kesempatan untuk mengenang Gus Dur puja sastra pun dihadirkan. Tentu saja kita berharap begitulah kenyataannya. Puisi “Sueznya Abdurrahman Wahid” karya Mustofa Bisri mengisyaratkan adanya puja sastra secara tulus: “Kota Suez kota sepi / Kota Suez kota kering / Dengan angin suara kami beriring / Dendang membelah hati / Kau yang jauh dari kami / kota Suez beri gamitan padamu // Kami beri lagu untukmu / Lagu sunyi hati kami.” Puisi ini tentu terkait dengan pengalaman emosional penyair dengan Gus Dur. Ada ruang rindu karena jarak yang memisahkan mereka. Sebuah romantisme yang indah.
Terhadap kontroversi sepak terjang dan pernyataan yang membuat Gus Dur dijuluki “Pendekar Mabuk” dan dikritik secara keras, penyair D.Zawawi Imron pada puisi “Ode Buat Gus Dur” menulis:
Di antara kami ada yang mengenalmu
sebagai pemain akrobat yang piawai
sehingga kami kadang bersedih
dan yang lain tersenyum
Yang kadang terluput kulihat
adalah kelebat mutiara
yang membias sangat sebentar
Hanya gerimis dan sesekali hujan
yang menangisi momentum-momentum yang hilang
padahal kami tahu
momentum tak kan kembali
dan tidak akan pernah kembali
Kata “kami” pada kutipan puisi di atas adalah representasi publik terhadap Gus Dur. Penyair menjadi penyambung opini atas persepsi yang dibangun masyarakat, bahwa di satu sisi Gus Dur adalah “pemain akrobat yang piawai”. Citra positif dihadirkan oleh penyair karena menggunakan kata “piawai”. Pengakuan itu menjadi makin terbuka saat penyair menampilkan sikap si aku lirik pada kata “kulihat” yang mengakui bahwa pernyataan Gus Dur mengandung nilai keagungan sebagai, “kelebat mutiara yang membias sangat sebentar”.
Masih terkait dengan pernyataan-pernyataan Gus Dur yang kerap kontroversial, penyair Joko Pinurbo dalam puisi “Durrahman” mengisyaratkan bahwa Gus Dur adalah “pujangga”, kata yang sengaja dipilih untuk menyimbolkan keindahan, kedalaman makna, ketulusan, dan perilaku yang menentramkan. Pujangga mengabdikan dirinya untuk nilai-nilai yang dibalut dengan keindahan, bukan ambisi kekuasaan. Pujangga adalah level yang setara dengan “empu”. Karya pujangga yang agung tak akan lekang oleh zaman, inspiratif di segala masa.
Selamat jalan, Gus. Selamat jalan, Dur.
Dalam dirimu ada seorang pujangga yang tak binasa.
Hatimu suaka bagi segala umat yang ingin membangun kembali
puing-puing cinta, ibukota bagi kaum yang teraniaya.
Ketika kami semua ingin jadi presiden,
baju presidenmu sudah lebih dulu kautanggalkan
Gus Dur adalah pribadi yang kuat memegang prinsip yang penuh teka-teki. Jurus mabuknya yang sering memicu perdebatan tidak membuatnya mengendur. Mendengar pembicaraan Gus Dur kita harus siap menerima dua kemungkinan, yakni dihibur dengan kelucuannya dan dibuat kaget dengan pernyataannya seperti geluduk di siang bolong: “Dur…!” Hal demikianlah antara lain yang diungkap Agus Noor dalam narasi “Lelucon Menjelang Kematian”: “ Meski sering ditinggal sendirian, sampeyan juga tak pernah gentar, kalau yakin diri sampeyan benar, tetap tegar berdiri sendiri di depan, tak undur meski hanya selangkah, dengan tabah dan penuh keyakinan…
Sampeyan juga tak peduli ditelikung lawan dan kawan, tak ambil pusing dan dengan enteng sampeyan malah maju terus dan pasang badan, sambil sesekali berkata, gitu aja kok repot!”
Bulan Desember 2014 yang baru lalu, Lesbumi NU Jawa Timur menerbitkan kumpulan puisi berjudul Tasbih Hijau Bumi. Latar belakang kultural kumpulan puisi tersebut tentu sangat dekat dengan Gus Dur. Lesbumi adalah organisasi di bawah naungan NU. Mungkin tidak banyak puisi yang “nakal” secara literer di dalamnya. Patronisme memberi pengaruh sangat kuat pada produksi seni yang disirkulasikan di ruang publik. Identitas ke-NU-an menjadi jaring untuk menangkapnya dalam proses yang bisa dirunut ke belakang sebagai latar historis.
Sebagai efek patronisme, dalam buku di atas paling tidak terdapat empat puisi yang mengangkat Gus Dur sebagai citra. Puisi “Kuda-kuda Kayu” karya Achmad Fatoni mengaitkan peran Gus Dur dengan Hari Raya Imlek: “Rumah, mall, kantor, toko, dan juga rumah ibadah, telah / kami sediakan kayu-kayu untuk tumpuan kuda-kuda itu / berlati. Sebab rindu ini untukmu Gus.”
Puisi “Di Pusara Gus Dur” karya Anurah Lelono Broto mengungkap masa kanak-kanak Gus Dur di tempat yang kini jadi makamnya. Gus Dur di masa kecil dilukiskan suka bermain sepak bola, memanjat pagar pesantren untuk menonton wayang di pabrik gula, juga mencuri jambu atau mangga di masa anak-anak. Romantisme masa lalu menjadi catatan yang membangkitkan kecintaan. Bagi penyair, berada di makam Gus Dur mampu melahirkan renungan dan ketenangan: “Gusku yang tak suka repot meski tubuh reyot, / alangkah tenang tidurmu, alangkah teduh istirahatmu, / hingga meski tinggal nisan batu / kau masih mampu berbagi sesuatu / Hujan tidak juga datang namun kami merasa / sejuk di dekatmu, Gus.”
Di kalangan nahdliyin Gus Dur memang ditempatkan sebagai citra. Sepak terjang Gus Dur adalah anutan, bahkan yang tampak aneh sekalipun. Puisi “Wafatnya Pendekar Mabuk” karya Rosie Jibril juga mengamini jurus pendekar mabuk ala Gus Dur. Ruang pemaknaan terhadap ucapan Gus Dur telah dilandasi dengan berbaik sangka (khusnudlon). Pemikiran positif penyair telah mengukuhkan keberadaan nilai yang dilontarkan Gus Dur. Pemikiran positif itu mirip dengan sikap Bima dalam pewayangan ketika diminta Pendeta Durna untuk mencebur ke laut mencari air kehidupan. Bima melaksanakan dengan sepenuh hati perintah sang guru, padahal Pendeta Durna justru berniat mencelakakan Bima. Tentu kita tidak bermaksud menyamakan Gus Dur dengan Pendeta Durna, tapi menganalogikan sikap menerima secara positif sang pengikut terhadap ucapan sang guru. Berikut kutipan puisinya:
ketidakpercayaan
tentang sang pendekar yang akhirnya menguluk salam
terhadap perjuangan.
Rumput menunduk lesu laiknya ketika Abu Nuwas
meninggalkan sang khalifah
Dimana kata-kata ngawur penuh makna
Tiada lagi dapat dijumpai, entah sampai kapan.
Aku mencoba mengais remah sisa jurus-jurus mabukmu
Berharap mengalir deras di denyut jantungku
dan mengisi kekosongan otakku dari ilmu-ilmu kehidupan.
Meski, kusadari dengan hati, aku takkan mampu bisa
sepertimu.
Selamat jalan, Gus!
Semoga jalanmu dijejali jutaan orang yang mampu
menakar dengan hati
Bahwa berbeda adalah rahmat. Amin.
Sebagai presiden Gus Dur adalah seorang politikus. Perjalanan hidup yang dilakoni kerap bersentuhan dengan dimensi politik. Pada masa Orde Baru dia pernah dipinggirkan sebagai efek politik. Setelah dia dilengserkan oleh parlemen dan diganti oleh Megawati, Gus Dur juga dipinggirkan. Di televisi pernah kita lihat, dalam suatu acara yang dihadiri Presiden Megawati, Gus Dur didudukkan di kursi bersama para tamu lainnya.
Harapan bagi penggagas adalah agar Megawati rujuk dan bersalaman dengan Gus Dur. Tapi apa yang terjadi? Ketika sampai pada giliran bersalaman dengan Gus Dur, Megawati melewatinya dan tidak mau bersalaman dengan Gus Dur, padahal mereka yang duduk di sebelah kiri dan kanan Gus Dur disalami. Konon setelah itu ada yang “meminta” Megawati untuk menyalami Gus Dur. Gus Dur tampaknya tidak mempermasalahkan hal itu. Puisi “Sang Penegak Negeri”, yang diberi penjelas Obituari Gus Dur, karya Sabrot D. Malioboro memberi penguatan pentingnya menghargai perbedaan untuk tetap berlaku sebagai sahabat dan saling menolong: “Paculah laju kuda jantanmu / Kendati pun bukan jalang lapang / Mengerti berbeda dari mengetahui / Kita selama ini adalah sahabat / Jalinkan tangan saling menolong.”
Puisi adalah sarana untuk ekspresi diri dan sekaligus media komunikasi. Sebagai media ekspresi, puisi digunakan penyair untuk mengungkapkan tanggapan, pemikiran, ide, dan imajinasinya yang sangat personal. Pada konteks demikian puisi benar-benar menjadi hak penyair dengan licentia poetica alias kebebasan yang melekat padanya. Posisi si “aku” lirik, yang diidentikkan dengan diri penyair secara personal, menjadi sangat kuat dan harus diterima pembaca apa adanya. Penyair hadir dengan hak dan tanggung jawabnya sendiri. Dalam kaitannya dengan Gus Dur, penyair menyuarakan tanggapannya secara pribadi dalam bentuk puisi seperti tampak pada kutipan puisi “Wafatnya Pendekar Mabuk” di atas .
Sementara itu puisi sebagai media komunikasi adalah sarana bagi penyair untuk membangun hubungan dengan pembaca, memberi informasi, mengajak atau memengaruhi orang lain. Posisi si “aku” lirik dipersandingkan dengan “kami” atau “kita” sebagai model penjamakan. Kedudukan si aku lirik alias penyair sebagai personal tentu masih muncul, tapi perannya didistribusikan juga ke pihak lain untuk membangun kebersamaan. Pada konteks inilah penyair bertindak sebagai juru bicara dalam membangun komunikasi dengan publik. Puisi-puisi yang terkait dengan Gus Dur tentu banyak yang memakai model demikian. Penyair memberikan tanggapan terhadap Gus Dur, kemudian melibatkan pihak lain untuk membangun persepsi, penilaian, dan ajakan. Puisi “Tafakur Bagi Gus Dur” karya Adhi M. Massardi berikut layak untuk dicermati.
Pada Rabu terakhir di tahun yang ragu
Aku mendengar kabar dingin angin
Lalu orang-orang menyebut namamu
Dalam nyanyian yang tak mungkin
Tapi pada Kamis terakhir tahun yang penuh tangis
Seribu Malaikat berdzikir mengiringi langkahmu
Seribu Bidadari mengikatkan selendangnya pada teralis
Dan aku hanya bisa menggumam: “O, Guruku…”
Kebijakanmu adalah cermin kebajikanmu
Kebesaranmu adalah cermin kesabaranmu
Bahkan ketika angin tak lagi membawa pesan penyair
Kau tetap lebih suka menyapa orang-orang tersingkir
Bunga mekar di taman
Bunga gugur di taman
Engkau duduk di singgasana
Engkau pergi dari sana
O, alangkah lekasnya waktu
Tapi engkau pergi
Setelah meninggalkan api kecil di hati kami
Yang tak akan pernah mati
Dan kami akan terus melangkah
Mengikuti jejakmu
Agar Tanahair kami penuh berkah
Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Jasa dan budi baik seseorang akan selalu dikenang walau dia sudah tiada. Potensi ini tentu dimiliki oleh siapa pun, tergantung konteks dan ruang lingkup masing-masing. Sebagai figur publik, sekaligus ulama dan mantan presiden, Gus Dur memiliki potensi dikenang dalam rentang waktu yang panjang. Para penyair dengan puisinya adalah saksi sejarah dalam kehidupan Gus Dur. Gitu aja kok repot. (*)
M.Shoim Anwar: lahir di Jombang, Jawa Timur. Menyelesaikan pendidikan S3 (doktor) di Universitas Negeri Surabaya. Banyak menulis puisi, cerpen, novel, dan esai. Dia masuk dalam Angkatan 2000 dalam Sastra Indonesia. Karya-karyanya diterjemahkan dan terbit dalam bahasa Jawa, Indonesia, Inggris, dan Prancis. Buku kumpulan cerpennya antara lain Oknum, Musyawarah Para Bajingan, Pot dalam Otak Kepala Desa, Sebiji Pisang dalam Perut Jenazah, Asap Rokok di Jilbab Santi, Kutunggu di Jarwal, Tahi Lalat di Dada Istri Pak Lurah, serta Tikus Parlemen.