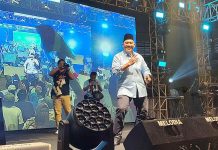“….’Politik Kiai’ lebih dominan pada politik etis, politik bermoral, politik bermartabat dan berakhlaq. Bukan politik menang-kalah yang senantiasa dibalut warna abu-abu. Menang tapi diperoleh dengan proses yang curang dan penuh tipuan, haruslah ditinggalkan…”
Oleh: Choirul Anam
TAHUKAH Anda, siapa sesungguhnya ulama atau kiai itu? Allah SWT berfirman dengan balik bertanya: ”Siapakah orang yang paling baik perkataannya dari orang yang mengajak berbuat baik (ke jalan Allah), dan ia pun melakukan perbuatan baik itu (beramal shalih)?”—Qaala Ta’ala: Waman ahsana qaulan mimman da’aa ila Allah wa ‘amala shaalihan?.
Allah kembali bertanya (dalam firman-NYa): “Katakanlah (hai Muhammad) apakah sama antara mereka yang berilmu pengetahuan dan mereka yang tidak berpengetahuan?”—Qul hal yastawiy al-ladziina ya’lamuuna wa al-ladziina laa ya’lamuuna? Tentu saja berbeda. Jadi, ulama atau kiai itu adalah orang yang berilmu, beramal, dan selalu konsisten antara perkataan dan perbuatannya. Satunya kata dengan perbuatan.
Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda: “Apabila tiba hari kiamat, Allah berfirman kepada orang-orang ahli ibadah (‘aabidiin) dan para pejuang (mujaahidiin): Masuklah kalian ke sorga! Saat itu para ulama/kiai langsung bersembah (mengusulkan): Ya Allah dengan berkat ilmu hambalah mereka bisa beribadah dan berjuang—bifadli ‘ilminaa ta’abbaduu wajaahaduu. Kemudian Allah berfirman (menjawab) usulan para ulama/kiai tadi itu: Kamu sekalian seperti setengah Malaikat-Ku—antum ‘indii kaba’dli malaa-ikatii, syafa’atilah mereka, syafa’atmu akan diterima! Maka, para ulama/kiai itu menyafa’ati mereka. Lalu kemudian mereka (para pejuang dan ahli ibadah) masuk sorga semuanya.”
Itulah yang namanya berkah atau barakah ulama/kiai yang sering kita sebut sehari-hari. Jadi, bukan hanya di dunia saja para ulma/kiai memberi berkah, melainkan juga di akhirat kelak, seperti yang terurai dalam hadis riwayat Ibnu Abbas tersebut.
Imam Hassan berkata: “Jikalau tidak ada ulama/kiai, niscaya keadaan kehidupan manusia seperti binatang—laulaa al-ulamaa-u lashaara al-naasu mitsla al-bahaa-imi.” Maksudnya memang, tugas keseharian ulama/kiai itu adalah memanusiakan manusia. Senantiasa menganjurkan dan mengajak kepada kebaikan (ke jalan Allah), mengajar dan mendidik manusia agar selalu berada di jalur kemanusiannya.
Tugas suci dan mulia itu (tentu) bukan berasal dari pemerinah atau dari anjuran MUI. Melainkan, tugas yang memang melekat pada diri keulamaan/kekiaian seseorang sebagaimana disebut (dalam hadis lain) sebagai “Pewaris tugas para Nabi—al-ulamaa-u waratsatul ambiya’.”
Dan bahkan Allah SWT telah menegaskan dalam firman-Nya): “Bahwa sesungguhnya yang takut kepada Allah dari segala hamba-Nya, hanyalah ulama/kiai—innamaa yakhsyaa Allaha min ‘ibaadihi al-ulama’.” Nah, jadi, selain berilmu, beramal saleh serta konsisten pada satunya kata dengan perbuatan, ulama/kiai itu adalah sosok manusia yang tiada takut kepada apa saja kecuali hanya kepada Allah SWT.
Dalam konteks politik, setelah kita tahu sedikit siapa sesungguhnya ulama/kiai itu, maka warna ‘Politik Kiai’ lebih dominan pada politik etis, politik bermoral, politik bermartabat dan berakhlaq. Bukan politik menang-kalah yang senantiasa dibalut warna abu-abu. Menang tapi diperoleh dengan proses yang curang dan penuh tipuan, haruslah ditinggalkan. Sebaliknya, kalah tapi dalam posisi benar dan jujur serta adil, harus dipertahankan. Inilah pinsip politik ulama/kiai—iqaamatul haqqi wal ‘adl—menegakkan kebenaran (juga kejujuran) dan keadilan.
Politik Kiai dengan demikian, bukanlah politik mencari kekuasaan sebesar-besarnya dan bukan pula politik merebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Melainkan, politik memperoleh dan atau mendapatkan kekuasaan dengan proses yang halal, demokratis, berpijak pada etika-moral, taat asas (hukum dan perundang-undangan) serta tetap berada dalam koridor konstitusi.
Inilah budaya politik yang ingin ditegakkan. Inilah pula kultur politik yang hendak dibangun oleh ulama atau kiai. Karena itu, dahulu, Rais ‘Am Syuriah PBNU, DR. KH. MA. Sahal Mahfudh, menegaskan: NU (Nahdlatul Ulama) tidak bergerak di kancah struktur politik, namun tetap berjuang membangun kultur politik yang sehat dan berakhlaq.
Penegasan yang sama juga disampaikan oleh Rais ‘Am Syuriah PBNU KH. Achmad Siddiq sebelumnya. Bahwa warga nahdliyin—terutama pengurus NU—harus bisa membedakan antara Budaya Politik dan Politik Praktis. Politik praktis adalah perbuatan politik yang berkait langsung dengan perebutan kekuasaan (jabatan eksekutif pemerintahan) maupun bagian kekuasaan melalui kursi-kursi di parlemen.
Dalam hal ini, NU secara tegas menyatakan: tidak ada urusan dan tidak turut campur. Sedangkan Budaya Politik, masih menurut Kiai Achmad Siddiq, adalah sikap dan tingkah laku yang sudah mapan dalam melakukan perbuatan politik. Cuma saja, harus diakui, budaya politik ini mungkin masih sangat rendah, kotor, curang serta penuh tipu-daya. Dan dengan tegas, NU berkomitmen untuk mewujudkan budaya politik yang sehat, bermartabat dan berakhlaq.
Pendek kata, dalam konteks Pilkada serentak saat ini, warga nahdliyin yang sudah semakin cerdas dan tergolong pemilih rasional (bukan tradisional apalagi emosional), diminta menjatuhkan pilihannya secara tepat dan benar guna mendukung terwujudnya budaya politik yang sehat dan berakhlaq. Jangan sampai terbius oleh bujuk rayu, harapan palsu dan janji-janji kosong serta pemberian sembako dll, yang sedang dimainkan calon pemimpin beserta kroni-kroninya.
Karenanya, jika ada edaran hasil istikharah jumhur ulama/kiai agar umat memilih si Badut misalnya, karena dalam istikharah dia terlihat jelas akan menjadi pemimpin yang amanah, maka edaran itu haruslah dimaknai sebagai suatu ikhtiar politik ulama/kiai guna mewujudkan budaya politik yang sehat dan berakhaq tadi.
Begitu pula, jika ada fatwa ‘wajib ain’ memilih Paslon (pasangan calon) pemimpi terbaik, karena jika kita tahu ada Paslon terbaik, tetapi tidak dipilih berarti berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka fatwa tersebut harus pula diartikan sebagai upaya politik ulama/kiai mendidik kedewasaan berpolitik warganya agar mampu menjatuhkan pilihannya secara tepat dan benar.
Lalu bagaimana umat bisa mengetahui Paslon itu baik dan terbaik? Tidak sulit! Karena, di zaman now ini, rekam jejak digital masing-masing Paslon dapat dilihat jelas dan dibaca secara kasat mata. Lihat dan baca misalnya, mana Paslon yang diusung pembesar partai dengan seruan: “Harus menang meskipun digugat lawan, dari pada kalah lalu menyerang.” Ini yang harus dijauhi dan tidak usah dipilih, karena seruan macam itu sama halnya membentuk perilaku politik machiavelistis—menghalalkan segala cara—termasuk kecurangan, penipuan, kepalsuan, kelicikan dan sebangsanya.
Dan biasanya, pembesar partai yang berseru seperti itu, tidak mengenal halal-haram dalam berpolitik. Dia hanya berpegang teguh pada nasehat Niccolo Machiavelli (filusuf politik Italia 1469-1527) yang membenarkan tindak kecurangan, penipuan, pemalsuan dan, jika perlu dengan kekerasan, dalam mempertahankan dan atau merebut kekuasaan.

Dan lihat, baca serta bandingkan dengan Paslon yang diusung pembesar partai dengan semboyan: “Manang secara terhormat dan bermartabat”. Semboyan macam ini akan membentuk perilaku politik yang jujur, adil, jauh dari kepalsuan dan selalu berpijak pada etika-moral. Dan biasanya, pembesar partai yang berslogan semacam itu, memang mengusung Paslon berkualitas tinggi, cerdas, jujur dan amanah, layak jual dan pantas untuk dipilih, lantaran juga sejalan dengan politik ulama/kiai yang hendak mewujudkan budaya politik yang sehat dan berakhlaq.
Nah, jadi, antara ‘politik kiai’ dan ‘kiai politik’ itu jauh berbeda. Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin, Rais ‘Am Syuriah PBNU dan Ketua Umum MUI, pernah menerangkan, bahwa ulama/kiai politik itu adalah ulama/kiai yang mengikuti arus politik kotor (politik machiavelistis). Kebanggaan ulama/kiai semacam itu jika berjumpa dan mendapat hadiah dari pejabat pemerintahan (presiden, menteri, gubernur, bupati/walikota dan para ajudannya)—wafakhruhu biliqaa-I amiirihi washilati sulthaanihi wathaa’ati al-qaadlii walwaziiri wal haabibi lahu.
Ulama/kiai model seperti ini, menurut Imam Ghazali adalah syiraarul ulamaa-i. Karena antara perkataan dan perbuatan, tidak pernah sama. Suka berubah-ubah, tidak istiqamah. Pagi kedele sore tempe, dan ilmunya dibarter dengan kemegahan duniawi. Adakah ulama/kiai yang disinyalir Imam Ghazali dalam Pilkada serentah dewasa ini? Wallahu’alam bisshawab! (*)