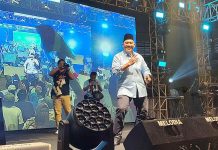Oleh: Suparto Wijoyo
Akademisi Fakultas Hukum, dan koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga
PILKADA membawa berkah. Begitu yang banyak diucap teman-teman pembaca Tajalli untuk menunjukkan bahwa demokrasi memang ngrejekeni. Percetakan baliho menggeliat dan para tenaga kerja pemasang gambar kian optimistis mengepulnya asap dapur yang telah lama dinanti. Pada saat kampanye ditunggu penuh nafsu karena roda ekonomi diyakini menggelinding lebih dari hari ini. Jual gorengan, bakso, soto, nasgor, es campur, dan aneka ragam kuliner diobsesi laris manis. Pokoknya, pilkada yang diagendakan sebagai wujud “rakyat berdaulat” di daerah dapat memompa semangat membuat pendapatan dikononkan akan berlipat. Belum lagi kalau masuk menjadi tim sukses yang biasanya kliwar-kliwer keliling kampung untuk memungut “serakan suara” yang masih tercecer.
Gairah semakin kentara yang dilakukan partai pengusung yang sedang merangkak memberikan sanjungan calon yang digadang-gadang untuk menang. Partai pengusung memberikan energinya sambil membawa-bawa poster yang memuat tanda gambar sekaligus petinggi idamannya. Sementara itu partai pendukung sekilas masih canggung karena dianggap pelengkap penderita yang “nunut” memeriahkan “akad nikah politik” paslon semata. Semaraknya tanda gambar diri yang terpotret semakin memadati ruang publik, dan pasti memberikan beban tersendiri di aspek ekologi. Berapa juta ton sampah yang diproduksi dari 171 daerah pemilihan yang sedang dihelat. Ini menjadi masalah lingkungan dalam lorong waktu lebih dari seabad. Kurun seratus tahun adalah batas masa yang diberikan oleh alam tentang luluhnya plastik-plastik pilkada dalam rengkuhan semesta.
Lebih dari itu, pilkada ini menarik dibincang karena memang menyangkut daya rangsang khalayak. Melalui rekomendasi partai berikut isu maharnya tidaklah menyentak pada helatan yang dipertontonkan. Tetapi tayangan alat peraga kampanye pastilah terus merangsek ke wajah kota, betapa hasrat berkuasa sedang dipanggungkan. Tataplah ke banyak sisi ruang kehidupan pembaca, gambar ditampilkan penuh aroma yang terkadang mengharumkan jalanan, meski tidak jarang membuat mual perut para “pengendara” yang semliwer untuk urusan hidupnya sendiri. Gambar dipajang dengan membawa-bawa leluhurnya agar orang tahu siapa dia sejatinya.
Mengapa untuk meraih suara dan menolehkan lirikan mata warga negara, paslon harus membopong trah keluarganya? Ada yang membusungkan diri dengan memberikan informasi bahwa dirinya adalah keturunan “nigrat negeri”. Bahkan dianggap pendiri sejati Republik ini. Meski sejarah tidak selalu menorehkan lakon yang seperhaluan, tetapi yakinlah kisah historianya masih banyak yang tersembunyi dengan cara membaca yang terkadang penuh elegi. Tokoh yang dikabarkan dan diketahui memang benar adanya sebagai “penuntun utama” munculnya NKRI dengan dasar negara Pancasila, ternyata di tengah-tengah panggung kuasanya telah pula “menggendong-gendong komunisme” yang jelas cetho welo-welo, laku itu ingkari Pancasila. Dalam pandangan yang diserempet-serempetkan dengan bahasa fiqih, kelindan historiografi ini diibaratkan bahwa sang tokoh telah “kentut sewaktu salat”. Semua orang akan menjawab batal salatnya, tetapi kekuasaan terkadang tidak mau mengerti tentang “fiqih kenegaraan” sebersit cerita ini. Aji mumpung kuasa kalau berkehendak dapat pula terjadi bahwa meski dia batal salatnya, tetap harus dianggap “sah sebagai romantika” yang menarik, sehingga hari ucapannya harus ditetapkan sebagai “milad peletak fondasi” rumah besar Indonesia.
Maka terhadap foto yang terpampang kadang-kadang orang lupa atau tegas bertanya-tanya, siapa dia? Untuk memberikan jawaban yang paling tegas adalah, dia itu merupakan “titah generasi pemilik NKRI” yang tanpa “moyangnya tidaklah ada ini negara”. Pokoknya jawaban harus maksimal dan dalam titik kendali yang paripurna, agar umat tidak bimbang guna mendapatkan tetenger yang pas. Walaupun pada saatnya, mengenai baliho paslon yang membawa-bawa leluhurnya mengingatkan saya pada sindiran yang terekam dalam cerpen-cerpen yang terhimpun dalam Jump and Other Stories karya Nadine Gordimer (2017), Pengarang Afrika Selatan, Peraih Hadiah Nobel Sastra tahun 1991: “Si anak mengingat-ingat dari foto, ia bilang, ia bukan ayahku. Aku sering ke sini dan duduk ketika ia masih di Pulau … dan aku menunggu. Menunggunya kembali … menunggu untuk pulang”.
Terhadap orang-orang yang selalu mengunggulkan keturunan tidaklah perlu ada reaksi massal, cukup jadi penyadaran saja bahwa manusia yang beriman niscaya bertauhid sebagai ciptaan Tuhan dengan moyang biologis nan teologis Nabi Adam as. Saya meneguhkan rasa percaya sebagai “generasi manusia yang berpuncak pada Adam as, bukan dari monyet seberang”. Dalam lingkup sekarang ini, ternyata masih sangat aktual tulisan Pemimpin Redaksi harian Duta Masyarakat tahun 1960-1970 Mahbub Djunaidi di kolom Asal Usul, koran Kompas, Minggu, 5 April 1987 yang berjudul Keturunan. Saya selalu terpikat tulisan-tulisan Mahbub Djunaidi yang senantiasa rileks dan aduhai mak nyessss sambil leyeh-leyeh “meneguk” opini humor nan satirenya.
Saya cuplikkan saja sebagai pengingat di era zaman now ini bagi pembaca Tajalli tentang ungkapan orang yang pernah duduk sebagai Pemimpin Redaksi Duta Masyarakat: “Pentingkah keturunan itu? Tentu penting, walau sama sekali tidak menentukan kualitas … Lewat kaca mata awam pun orang bisa maklum betapa keturunan itu bukanlah apa-apa dan tidak seratus persen dominan. Taruhlah Anda itu memang keturunan Gajah Mada yang hebat, tapi yang penting siapakah Anda sekarang ini? Antara kehebatan Gajah Mada dan Anda tidak ada hubungannya sama sekali. Anda tak lebih sekadar pendompleng kebesarannya, tak lebih, sementara Anda tetap bukan siapa-siapa. Anda adalah Anda, habis perkara. Anda tidak perlu macam-macam dengan dongeng keturunan itu. Anda musti bekerja keras untuk jadi semacam Gajah Mada. Kualitas tidak jatuh dari keturunan, dan tidak juga dari langit”. Bagaimana?