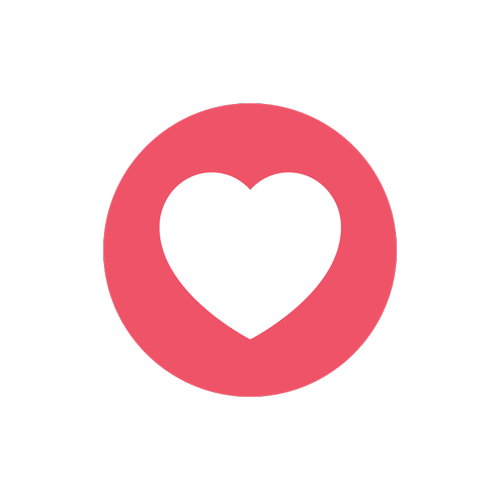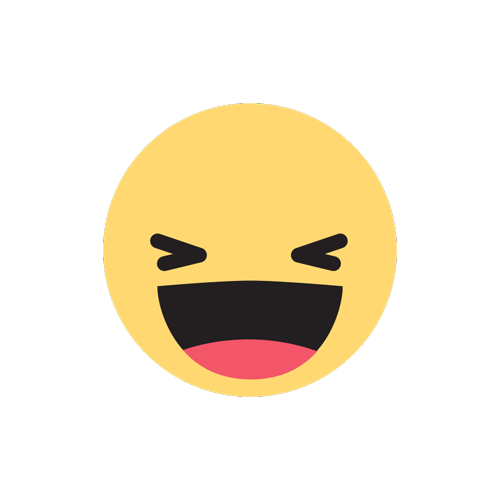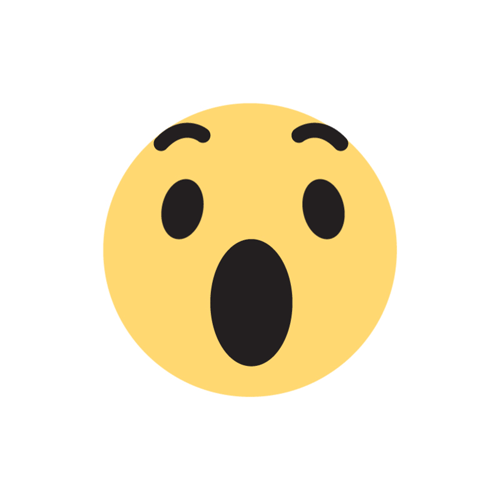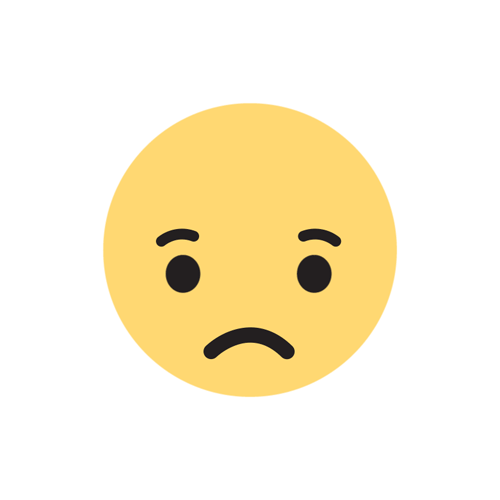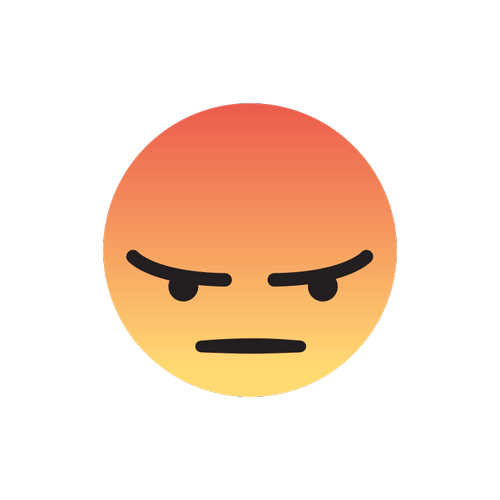Catatan Cak AT*
SAYA tahu, judul filmnya saja sudah bikin ngos-ngosan: One Battle After Another. Pertempuran demi pertempuran. Seakan hidup ini kurang drama sampai Paul Thomas Anderson turun tangan dengan menghadirkan film yang mewakili kisah perjuangan sebagian kita.
Dalam film ini, ia menyulap trauma keluarga jadi tontonan layar lebar yang lebih megah daripada sidang DPR soal RUU entah apa. Bedanya, kalau DPR bisa bikin kita ketiduran, Paul justru bikin kita melek nonton sampai kopi habis dua teko.
Film ini bukan parade pahlawan berseragam ketat yang sok menyelamatkan dunia dari alien plastik CGI. Tidak. Ini tentang bapak-bapak kesepian yang dulunya jago meledakkan gedung, kini kebingungan meledakkan telur ceplok buat anak gadisnya.
Leonardo DiCaprio, aktor yang sudah berkali-kali kehilangan Oscar sebelum akhirnya dapat lewat Revenant, di sini bermain sebagai Bob Ferguson —eks-revolusioner yang lebih paham merakit bom ketimbang mengepang rambut anaknya. Sungguh potret bapak-bapak sejati: pandai mengkritik negara, tapi gemetar di depan sisir.
Akankah film ini masuk nominasi Oscar? Ah, ini jelas kandidat kuat, bersama beberapa film pilihan. Clayton Davis dari _Variety_ sudah kasih skor tinggi, bahkan menaruh film ini di jajaran sepuluh nominasi terbanyak.
Paul konon “overdue narrative”, bahasa halusnya: juri Oscar sudah lama merasa bersalah belum kasih dia piala. Jadi, kalau pun filmnya cuma menampilkan Leo sedang bingung pilih sampo, kemungkinan tetap dibungkus emas di Dolby Theatre.
Tapi jujur saja, film ini memang punya bobot, bukan sekadar belas kasihan Akademi Oscar. Ia memadukan kamera 70mm dengan drama tujuh galon air mata. Hasilnya: sinema yang terasa intim sekaligus kolosal.
Nah, kalau mau ditarik garis cerita ringkasnya, One Battle After Another berpusat pada sosok Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio). Dia eks anggota kelompok revolusioner “French 75” yang dulunya hidupnya meledak-ledak —secara harfiah.
Setelah lahir anaknya, ia kabur dari dunia perlawanan. Bersama si bocah, ia berusaha hidup “normal” meski trauma menempel seperti noda kopi di meja kerja.
Namun, bertahun-tahun kemudian, masa lalunya menuntut balas: kawan lama, musuh lama, semua muncul, membuat ayah dan anak harus kabur lagi. Kali ini bukan demi revolusi, tapi demi mereka bisa bertahan hidup.
Diadaptasi dari novel aslinya, kisah ini dipilih karena menggambarkan ironi universal: seorang pejuang keras kepala yang ternyata paling rapuh saat harus menghadapi hal paling sederhana —menjadi ayah.
Novel itu serius, getir, penuh renungan. Anderson mengadaptasinya jadi lebih cair, menambahkan absurditas sehari-hari agar pesannya tidak berubah jadi khotbah kering.
Novel aslinya berjudul _Vineland_, ditulis Thomas Pynchon, seorang novelis Amerika. Adaptasi film One Battle After Another bukan terjemahan literal atau sangat setia terhadap novel tersebut. Film ini lebih bersifat _loosely inspired_ atau _modern update_ dari _Vineland_.
Pynchon sendiri dikenal sebagai penulis dengan gaya postmodern, satir, eksperimental, penuh simbolisme, ironi, dan sering bermain di antara realitas/paranoia/kritis terhadap kekuasaan. Adaptasi ke layar tentu menghadapi tantangan besar agar tidak kehilangan nuansa kompleks itu.
Di halaman-halaman novel, tokoh Bob ditulis sebagai sosok getir yang terjebak antara ideologi dan keluarga. Paul tentu menyulapnya jadi lebih pop: ada humor getir, ada momen “bapak nggak bisa nyisir rambut anaknya”, ada ledakan yang lebih mirip kembang api tahun baru ketimbang manifesto revolusioner.
Distorsi? Ya jelas ada. Novel ingin bicara serius soal trauma generasi dan harga pengkhianatan politik. Film justru menyeimbangkannya dengan adegan absurditas sehari-hari.
Tapi bukankah justru itu yang bikin pesan novel lebih mudah ditelan? Kadang kebenaran memang harus disajikan seperti obat anak: dikunyah bersama sirup rasa anggur.
Sekarang, pertanyaan penting: kenapa orang Indonesia perlu nonton? Jawabannya sederhana: supaya kita sadar bahwa drama keluarga revolusioner tak kalah pelik dari drama keluarga WhatsApp grup RT.
Bob Ferguson memang lari dari masa lalu politiknya, tapi bukankah kita juga sering begitu? Kita pura-pura lupa pernah ikut demo, sementara foto selfie masih beredar di Instagram dengan caption “perjuangan belum selesai”. Bob bersembunyi di padang pasir, kita bersembunyi di balik undangan arisan. Sama saja, kawan.
Dan inilah pesan yang menusuk, terutama bagi para bapak aktivis: jangan cuma piawai orasi di mimbar, menggebu soal keadilan sosial, lingkungan, atau bahkan agama, tapi begitu pulang ke rumah mendadak jadi “aktivis rebahan”.
Apa gunanya berapi-api membela rakyat miskin kalau lupa menimang anak sendiri? Apa faedahnya mengkritik kerusakan hutan kalau tak tahu cara memeluk istri dengan hangat? Bob Ferguson adalah karikatur tragis dari fenomena ini —pahlawan di jalanan, tapi sering gagal jadi pahlawan di ruang tamu.
Di Indonesia, menonton film ini bisa jadi cermin: bagaimana generasi bapak-ibu yang dulu “membakar” jalanan kini kikuk berhadapan dengan anak-anak Gen Z yang lebih fasih TikTok ketimbang revolusi.
Novel memberi peringatan tragis, film memberi kita peluang tertawa getir. Dan bukankah tertawa atas tragedi adalah skill bertahan hidup paling elegan?
Maka, jika Anda merasa hidup ini penuh pertarungan —utang cicilan, harga beras, sampai debat politik receh di medsos— film One Battle After Another bisa jadi hiburan sekaligus terapi.
Film ini menunjukkan bahwa satu-satunya pertempuran yang sungguh layak dimenangkan bukan melawan negara, bukan pula melawan masa lalu, melainkan melawan rasa kikuk kita sendiri saat mencoba menyisir rambut anak gadis.
Pada akhirnya, tragedi di layar berubah jadi komedi di kursi penonton. Distorsi pesan novel justru membuka pintu refleksi: mungkin semua pertempuran hanyalah alasan agar kita belajar kalah dengan elegan.
Dan kalaupun film ini nanti gagal menang Oscar, paling tidak kita sudah mendapat satu hal berharga —kesadaran bahwa hidup ini, memang, hanyalah one battle after another, satu perjuangan ke perjuangan lainnya.
Tapi tenang, kadang satu kekalahan bisa jadi kemenangan tersembunyi, sama seperti menemukan sisir patah yang ternyata bisa juga dipakai buat menata rambut.
*Cak AT adalah Ahmadie Thaha. Pengasuh
Ma’had Tadabbur al-Qur’an.