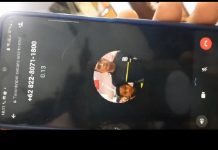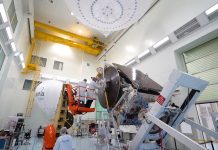“Berkali-kali saya melakukan “wisata religi” ke makam Gus Dur, kelebatan para peziarah itu acapkali melintas dengan senyum dan urai kepuasan batinnya. Damai ada dalam sebongkah makam. Kalaulah ini yang melintas di jiwa-jiwa anak bangsa, maka kelindan batin yang terekam adalah: Gus Dur dirindukan dengan beragam alasannya.”
Oleh: Suparto Wijoyo *
SOSOK ini sangat fenomenal dalam tumpukan kenangan yang selalu melintas dalam ruang hati saya. Tanggal 19-20 Oktober 1999 saat pemilihan dan pelantikan Presiden Republik Indonesia yang dipanggulnya, saya ikuti sambil menyimak siaran langsung TV dengan ketertegunan. KH Abdurahman Wahid bertahta di singgasana paling diperebutkan para politisi untuk menggapainya, Presiden RI. Nama dan kiprahnya merasuk dalam gelombang pikiran bangsa, dan saya baru menyinambungkan indra ketertarikan sejak bersekolah di Madrasah Aliyah, waktu Gus Dur didaulat menjadi Ketua Umum PBNU 1984 hasil Muktamar di Situbondo. Jargon yang mengekspresikan semangat pergerakan NU di bawah nahkodanya adalah “Kembali Ke Khittah”. Alun-Alun Lamongan menjadi saksi bersama 15.000 jamaah yang menghadiri tausiyahnya. Saya merekam dengan menggunakan tape recorder sebagai anak Madrasah Aliyah kelas satu.
Pidato di Alun-Alun Lamongan itu membekas dengan tema yang membincang politik nasional dalam genggam kuasa Presiden Soeharto. FORDEM muncul menjadi “institusi sosial” yang digawanginya, dan sangat menarik minat “diintai” para mahasiswa, termasuk saya. Forum Demokrasi gencar terberitakan dan mahasiswa asyik “menari bersama” gendangannya. Diskusi-diskusi demokrasi dan HAM marak di kampus dan mampu menggelorakan semangat juang dalam “rahim pembuaian jabang bayi” reformasi. Hentakan reformasi menggelembung di tahun 1998 pada saat saya memasuki babak menjadi PNS, menempuh jalan perdosenan.
Kesempatan belajar dan riset terbentang di era kepresidenan Gus Dur. Kiprah Gus Dur sebagai orang nomor satu di Indonesia saya persaksikan dengan melihat TV dan mendengarkan radio-radio dengan degub yang menghentak dan menumpahkan keterharuan. Situasi batin saya nyaris serupa dengan gerakan pemakzulan Gus Dur yang diusung MPR. Antara tanggal 1-23 Juli 2001 itu teramat dramatik kisahnya untuk dilintasi bangsa ini dengan hasil akhirnya: Gus Dur benar-benar dilengserkan, 23 Juli 2001. Kejatuhan dari kursi presiden pastilah tidak dirasakan oleh Gus Dur, karena tidak kemaruk jabatan. Tetapi rasa tersayat menggerus dada menghadirkan guncangan batin yang menumpahkan air mata. Saya menyaksikan peristiwa itu saat melakukan penelitian disertasi di Eropa. Perjalanan dari Belanda melintas Jerman, Prancis sampai ke Austria dengan mengistirahatkan badan di Swiss.
Berbagai kolega menatap dan saya ceritakan bahwa di Indonesia sedang terjadi pemberhentian Presiden Gus Dur. Presiden yang sewaktu hadir di Prancis memukau banyak tokoh Paris itu kini lengser. Belum lekang ingatan itu, saya sungguh menarik nafas panjang atas apa yang menimpa Gus Dur sambil menyaksikan diri sang pemakzul, tokoh penggedog pelengseran, yang juga bertandang ke Belanda. Pemakzulan yang kontroversial sampai hari ini dengan bukti-bukti yang sumir. Buloggate dan Bruneigate lambat laun ternarasikan hanyalah imaji tanpa bukti yuridis yang memenuhi syarat bagi kepentingan pemberhentian Presiden.
Sejatinya, gonjang-ganjing kenegaraan yang terhelat di Jakarta sewaktu Gus Dur mengganti menteri ataupun mengatasi “pembangkangan” mereka yang silih berganti, tidaklah menimbulkan keganjilan di masyarakat desa. Masyarakat di kampung-kampung, apalagi Lamongan, kepemimpinan Gus Dur dianggap mbarokahi. Orang tua, sanak saudara dan handai taulan pada tahun 1999-2001 itu sangat mensyukuri geliat ekonomi yang terus membubung tinggi. Ini bukan soal angka statistik versi negara melainkan ekonomi roso yang menghampiri petani dan petambak. Sawah dan tambak udang saya sendiri membuncahkan kenikmatan yang tidak terperi. Tahun-tahun yang membahagiakan dengan udang windu seharga Rp125 ribu per kilogram. Suatu harga yang sangat fantastis yang kemudian turun melorot sampai ke tingkatan Rp17.000-Rp19.000 seiring momen Gus Dur “dipelorot” dengan mekanisme politik pelengseran. Nilai harga udang windu itu sampai saat ini belum mampu merangkak naik setinggi “barokahe” kebijakan ekonomi Gus Dur.
Panen raya tambak diikuti dengan meningkatnya jumlah orang naik haji. Naik haji adalah “cita-cita tertinggi” yang ada di benak para petambak udang dan petani pada umumnya. Haji adalah simbol kemakmuran dan di zaman Gus Dur dengan udang yang berharga tinggi menjadikan lembaran yang sesuatu banget di hati emak, kakak, dan kerabat. Keterpentalan Gus Dur dari Istana Negara dengan sambutan gempita di lapangan untuk terbang ke USA, adalah wujud pengaliran hati agar memiliki kelembutan. Kini orang bisa memahami pilihan “celana kolor” Gus Dur di panggung Istana yang sangat “mengena di pelupuk jiwa”. Kepasrahan itu melintas dengan kelapangan ruhani dalam menampung gelombang massa.
Usai lengser, Gus Dur bertandang pulang kampung ke Jombang dan mengumpulkan teman-teman kecilnya di Cukir Gang III saat itu, dan saya turut menghantar orang tua, kakak, dan adik-adik dalam bincangan yang sangat sederhana. Saya menepi menyaksikan orang-orang kampung di Cukir bercengkerama bersama “kekasihnya”. Gus Dur “ndeprok” duduk di lantai beralas tikar pandan, sambil menikmati rebusan singkong, kacang, dan ubi jalar. Kematangan batin terpancar dan kehendak Tuhan menuntun langkah selanjutnya, Gus Dur hadir ke rumah orang tua saya di Lamongan sewaktu hajatan ponakan menikah. Di acara inilah Gus Dur meresmikan bangunan kecil yang diniatkan menjadi pesantren kelas dusun yang dipangku oleh kakak KH Abdul Halim Affandie. Sebuah peristiwa yang diterima sebagai berkah. Saya hanya tertegun dan bersimpuh dengan tetap berada pada pusaran luar untuk menangkap bayang “kerinduan” agar tetap pada posisi tanpa kepentingan apa pun.
Hari-hari di bulan Desember 2009 beredar banyak kabar tentang kesehatan Gus Dur. Tanggal 30 Desember 2009 seputaran magrib berkelebat kabar dari Jakarta, Gus Dur diperjalankan Allah SWT menempuh rute akhir batas dunianya. Kewafatannya menyentak sesi kehidupan yang paling inti dari bangsa Indonesia. Gelombang rakyat di Jakarta dan Jawa Timur membanjiri jalanan sampai di halaman Ponpes Tebuireng Jombang, 31 Desember 2009. Presiden SBY hadir memimpin pemakaman Bapak Pluralisme dalam persemayaman agung nan hikmat di Ponpes Tebuireng. Lantun doa dan simpuh peziarah memadati lokasi makamnya sampai saat ini dan esok hari. Waktu minggu pertama Januari 2010 saya beserta rombongan pengabdi lingkungan menjelajah dari Blitar, balik ke Surabaya dengan kesadaran penuh melewati Ponpes Tebuireng. Pukul 19.00 saat itu hujan sedang “mengerem kecepatannya” sehingga tampil rintik-rintik. Jalanan mulai dari arah Kediri sudah melambat dan macet di Kandangan. Kendaraan berjalan seperti berhenti bergerak dalam ramainya kerumun peziarah.
Saya menyaksikan serombongan nenek-nenek menuntun cucunya, sambil kehujanan dan menapak jalanan yang becek serta sesaknya ransekan orang. Sang nenek mengajak keluarganya dan cucu-cicitnya duduk nglesot di jalan depan Ponpes Tebuireng. Nenek itu duduk tafakur sambil merendahkan tubuhnya sekaligus mengusap wajahnya dengan gambaran yang khusuk. Ribuan orang melakukan hal yang sama. Hujan yang mengguyur dan beceknya jalanan bukanlah halangan untuk meneduhkan diri di pusaran makam Gus Dur. Saya bertanya dalam ketersendirian, apa yang mereka cari dengan “ritual iman” ini? Apa yang menyebabkan mereka rela menapak kaki, melangkahkan diri, membungkukkan jasad dan mengiriskan cintanya untuk Gus Dur seperti ini?
Pasti ada yang mereka “temukan” meski saya tidak meminta jawaban kepada para peziarah. Berkali-kali saya melakukan “wisata religi” ke makam Gus Dur, kelebatan para peziarah itu acapkali melintas dengan senyum dan urai kepuasan batinnya. Damai ada dalam sebongkah makam. Kalaulah ini yang melintas di jiwa-jiwa anak bangsa, maka kelindan batin yang terekam adalah: Gus Dur dirindukan dengan beragam alasannya. Biarlah semua alasan itu menjadi tenunan kebangsaan yang indah bagi Indonesia yang tengah sewindu “ditemani” Gus Dur dari alam sana. Alfatihah.
* Esais, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga