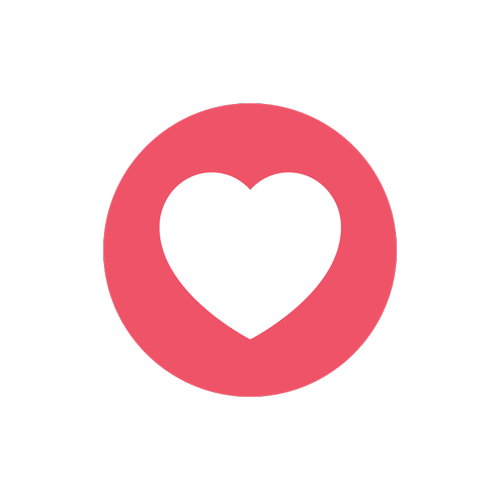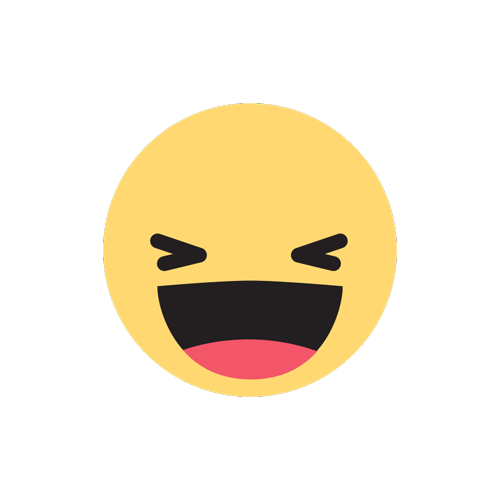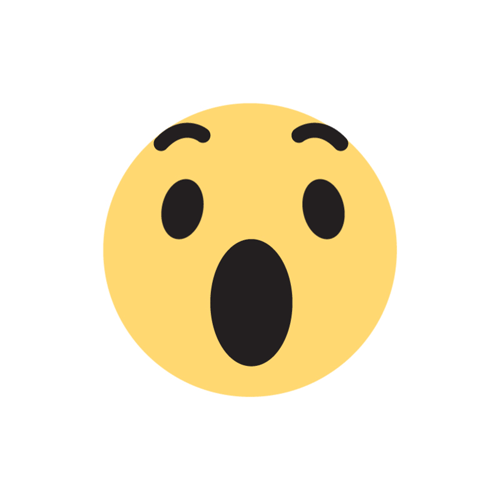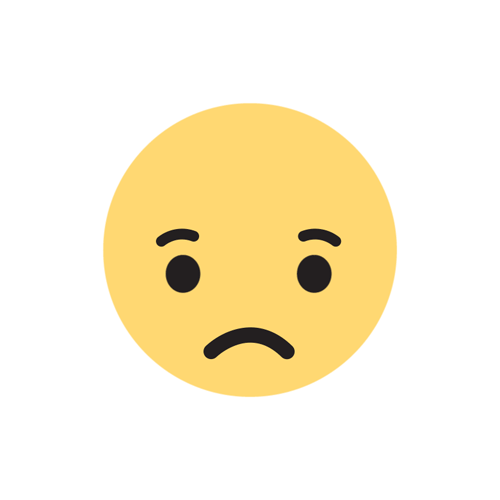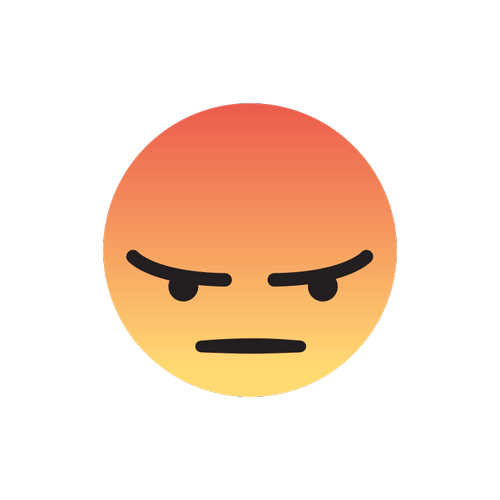“Dari ketiga titik awal ini, sosok Mbah Canthing pegang peran penting dalam periode awal pendirian Desa Mlorah. Bahkan Mbah Canthing dianggap sebagai lurah pertama di desa ini.”
Oleh Mukani*
BANGSA Belanda memiliki hasrat kerakusan dalam memonopoli dunia perdagangan di kepulauan Nusantara. Mereka kemudian mendirikan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada tanggal 20 Maret 1602. Kongsi dagang multinasional pertama di dunia ini, menurut Hamka (2016: 610), berdiri atas usulan Johan van Oldenbarneveld.
Perkembangan VOC memiliki kekuasaan politik cukup besar di Nusantara. Meski periode awalnya dibentuk sebagai organisasi perdagangan. Bahkan menurut Nugroho Notosusanto (2008:227), VOC layaknya sebuah pemerintahan suatu negara. Era baru Indonesia kemudian berada di bawah kolonial Belanda dengan “nama baru” yang disebut sebagai Hindia Belanda.
Perlawanan Gigih
Berbagai perlawanan sudah dilakukan rakyat Indonesia kepada kolonial Belanda. Dari berbagai perlawanan itu, muncul nama-nama pahlawan Islam di Indonesia, seperti Sultan Agung Mataram, Sultan Hasanuddin Makasar, Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Sultan Iskandar Muda, Cut Nyak Dien, Tengku Cik di Tiro, Tuangku Imam Bonjol, Trunojoyo, Untung Suropati dan lain sebagainya.
Namun semua perlawanan itu masih bisa dipatahkan oleh kolonial. Hal ini lebih dikarenakan sifat perlawanan yang masih kedaerahan. Mulai dari daerah Aceh, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sumatera, Kalimantan, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur dan daerah lainnya.
Salah satu pemberontakan pribumi kepada Belanda adalah yang dipimpin Pangeran Diponegoro. Perang yang berlangsung selama 1825-1830 ini lebih dikenal sebagai Perang Jawa. Di beberapa referensi, menyebut Perang Jawa sebagai sebuah perang sabil. Artinya, juga terdapat motivasi agama dalam melawan bangsa Belanda.
Perang Jawa disebut sebagai peristiwa perlawanan terbesar masyarakat Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro terhadap penguasa kolonial. Api semangat Islam di Indonesia, menurut Nugroho Notosusanto (2008: 229), akhirnya tidak dipandang sebelah mata lagi oleh Belanda.
Pangeran Diponegoro menggunakan dukungan dari rakyat yang tinggal di berbagai pelosok desa. Perang Jawa juga didukung berbagai elemen masyarakat Islam, terutama santri dan kiai. Tidak mengherankan jika selama lima tahun itu Belanda dibuat repot oleh laskar Diponegoro.
Belanda sudah mengerahkan pasukan sebanyak 8.000 serdadu Eropa dan 7.000 prajurit pribumi. Itu ditambah dua per tiga dari 3.145 tentara bantuan yang didatangkan langsung dari Belanda. Tentu mobilisasi pasukan sebanyak itu membutuhkan biaya besar. Meminjam istilah MC Ricklefs (1993: 123), dana itu hanya bisa ditutupi melalui sistem tanam paksa Van de Bosch.
Perang ini, sebagaimana dikutip dari Peter BR Carey, diikuti sebanyak 108 kiai, 31 haji, 15 syaikh, 12 penghulu Yogyakarta dan 4 kiai guru yang ikut ke dalam laskar Pangeran Diponegoro. Siasat licik yang digagas Letjen de Kock melalui “perundingan damai” sebagai upaya tipu daya (overriding) di Magelang berhasil menangkap Pangeran Diponegoro.
Setelah Pangeran Diponegoro diasingkan ke Sulawesi tahun 1830, anggota laskar ini menyebar dan mendirikan basis-basis perlawanan dengan mendirikan masjid dan pesantren yang jauh dari pusat-pusat tangsi Belanda. Mereka berpencar ke penjuru mata angin dengan mengubah strategi perlawanannya untuk menyebar dan berdiaspora dalam meneruskan kaderisasi, melakukan perlawanan kultural seperti gerakan literasi dan memperkuat pemahaman keagamaan terhadap masyarakat.
Strategi perjuangan baru ini, diakui Zainul Milal Bizawie dalam buku Jejaring Ulama Diponegoro (2019: 283) akan memakan waktu lama. Hasilnya akan dipetik oleh para generasi penerus setelahnya. Perubahan ini sebagai suatu kewajaran, terlebih mayoritas sebagian besar pengikut dan pendukung Pangeran Diponegoro adalah kaum santri dan kiai.
Para sisa pasukan laskar Pangeran Diponegoro banyak yang melarikan diri ke daerah Jawa Tengah yang disebut sebagai Pinggiran Nagari. Mereka yang hijrah ke arah barat disebut sebagai Mancanegara Kulon. Namun mayoritas mereka hijrah ke daerah Jawa Timur sebagai Mancanegara Wetan.
Mereka hijrah secara berkelompok. Pada beberapa lokasi singgah, terkadang salah satu anggota rombongan memilih untuk tetap tinggal dengan tujuan membuka lahan yang baru dalam berdakwah (Jawa: babat alas). Sedangkan rombongan lainnya meneruskan perjalanan.
Hal ini bisa dijumpai di beberapa daerah Jawa Timur. Khusus di Nganjuk, jejaring laskar Diponegoro ada Mbah Karimun di Desa Petak Bagor dan di Pesantren Miftahul Ula Nglawak Kertosono dengan sosok KH Abdul Fattah Jalalain. Termasuk Mbah Canthing yang kemudian tinggal dan wafat di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Nganjuk.
Peran Penting
Sesepuh Desa Mlorah, Parjimun (2011), menegaskan bahwa desanya memiliki cikal bakal dari tiga titik awal. Pertama adalah sumber mata air semacam petirtan di sisi selatan desa, yang sekarang dikenal dengan daerah Janeng. Kedua adalah makam Mbah Jantho yang berada di selatan balai desa. Ketiga adalah keberadaan Mbah Canthing di pojok’an desa.
Dari ketiga titik awal ini, sosok Mbah Canthing memegang peran penting dalam periode awal pendirian Desa Mlorah. Bahkan Mbah Canthing dianggap sebagai lurah pertama di desa ini. Inilah yang mendorong warga Mlorah menghormati keberadaan makam Mbah Canthing hingga sekarang.
Hal senada diungkapkan Murhardi/Partoko (2011). Dia adalah mantan kepala desa Mlorah selama dua periode. Pria yang juga pensiunan guru PNS ini meyakini sosok Mbah Canthing sebagai sosok yang tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan cikal bakal pendirian Desa Mlorah.
Tidak heran jika warganya menganggap Mbah Canthing sebagai “punden” desa. Keberadaan Mbah Canthing diidentifikasi dan diyakini sebagai orang pertama yang tinggal di Desa Mlorah. Menurut Imam Hartoyo (2019), ketua MWC NU Rejoso yang juga warga asli Desa Mlorah, sebenarnya sudah mulai ada titik terang terkait sejarah awal mula Mlorah dan memang desa ini memiliki sejarah panjang.
Hal ini bahkan sudah pernah dijelaskan KH. Abu Hakim Abdurrahman (almarhum), pengasuh Pesantren Sekapurtih Nganjuk. Pada suatu kesempatan, kiai kharismatik itu menjelaskan secara detail kronologi sejarah Desa Mlorah dan nama-nama para tokohnya serta tahun ringkasan kisah munculnya nama Mlorah. Termasuk sosok yang disebut wong ning pojok’e deso.
Pilihan Mbah Canthing untuk bergabung dengan laskar Pangeran Diponegoro menjadi catatan penting perjalanan sejarah. Dengan meninggalkan jabatan di kerajaan Mataram Islam, dia lebih memilih menghadapi kekejaman Belanda demi memerdekakan bangsanya. Spirit inilah yang harus terus dilestarikan dalam memajukan masyarakat pada masa sekarang.(*)
*Mukani adalah Dosen STAI Darussalam Krempyang Nganjuk, Anggota LTNU PWNU Jatim.