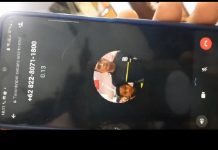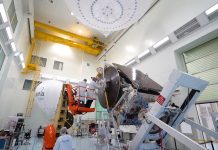Oleh: Suparto Wijoyo*
TANGGAL 2 Mei selalu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, tak terkecuali 2 Mei 2019. Sebuah momentum untuk membangun sekaligus merenungi tingkat peradaban bangsa dari dunia pendidikan. Situasi politik hari-hari ini menjadikan pustaka pendidikan sedang dipertanyakan. Ke mana kalangan terdidik sekarang ini?
Suara-suara pemanggul kekuatan moral dan intelektual dalam sebuah tatanan waktu satu “periode ini” tampak membenarkan saja atas apa yang terjadi. Terhadap kecurangan dan kejahatan demokrasi yang mencuri suara-suara rakyat melalui modus salah input belum menyentuh titik kesadaran para intelektual. Mereka seperti sedang asyik dengan dunianya melakukan rapat-rapat di kampus, sibuk penelitian rutin yang tidak kerap terpanen manfaatnya, pengabdian-pengabdian masyarakat yang digelar seperti “proyek musiman”.
Intinya ada yang aneh dengan dunia pendidikan terutama pendidikan tinggi yang cenderung menjadi hulubalang kekuasaan. Mereka ada yang membuat surat edaran pencoblosan dan membuat grup-grup tertentu yang mengarahkan kepada pilihan-pilihan tertentu yang tidak sesuai dengan nalar akademiknya.
Begitulah kritik keras yang disampaikan oleh sahabat spesial saya yang bernama Mispon. Memang Cak Mispon kerap hadir dengan analisis-analisis yang tepat meski kadang-kadang saya jengah. Saya selalu tekankan bahwa saya tidak seperti yang direkam oleh umum bahwa kampus sudah tersembelih idealitanya. Sebab, saya sendiri merasa tetap menjaga nalar kampus sebagai lembaga yang berkarakter kebenaran dan kejujuran.
Terhadap hal itu, Cak Mispon memahaminya dan memberikan kembali renungan atas Hari Pendidikan yang diperingati ternyata tetap saja semakin tidak melahirkan generasi milenial yang “berpihak kepada yang hak”. Menurutnya sekarang ini banyak ditemukan generasi lalat yang jelas-jelas sudah diberi keterangan bahwa madu itu lebih enak tetapi lalat terus saja suka-suka ke comberan. Jelas bahwa bunga itu harum semerbak, tetap saja lalat lebih suka hinggap di sampah.
Begitulah kalau mengajari lalat, mendidik kaum lalat tentang “wewangian” karena “kapasitas hidupnya” memang suka sampah, bukan madu atau bunga. Begitulah Mispon memberikan ilustrasi atas realitas sekarang yang menampilkan kaum terdidik berperilaku sekadar membela kebohongan. Kecurangan tidak diprotes tetapi diberi alibi. Perampasan suara rakyat sekadar dibilang salah input yang persentasenya kecil saja. Jadi kebenaran menurutnya hanya dilihat “besar gedenya” bukan soal “derajat kesalahannya”.
Maka “mencuri satu suara rakyat” itu dianggap lumrah dan tidak dianggap sebagai bentuk tindakan kriminal dari berjuta suara. Artinya membunuh seorang tidaklah apa di tengah berjuta-juta orang terselamatkan. Bukankah nalar hukum mengatakan bahwa “pembunuhan tetaplah pembunuhan meski hanya seorang”. Paham ya Cak Parto?
Mispon benar-benar menampar kepala saya, bukan sekarang muka dengan ungkapan tersebut, apalagi atas fakta yang disodorkan tentang pemilu yang “mencekam dalam koridor HAM” warga negara. Daripada sibuk itu tumben Mispon lantas menarik kertas catatan agar saya memberikan pemahaman tentang “pendidikan itu dirancang sejatinya demi kemuliaan manusia, bukan sekadar berkuasanya manusia”.
Dalam lingkup ini saya beri tahu, Cak Mispon pahamilah bahwa Hardiknas merupakan ladang penting untuk bercermin diri dengan menggali kembali dasar falsafati pendidikan. Apa yang telah diraih oleh kita semua dalam menyelenggarakan pendidikan di negeri ini? Apakah anak-anak didik telah menjadi insan yang semakin mulia akhlaknya, ataukah sekadar kerumunan manusia yang cerdas tetapi culas? Hal ini dapat dipotret secara faktual dari laku siapa saja, mulai sosok kepala negara sampai dengan tabiat kepala keluarga.
Tuhan telah memberikan garis pergerakan menurunkan agama seperti Islam melalui manusia agung yang bernama Nabi Muhammad saw? Apa target utamanya? Ternyata kehadiran Nabi Muhammad saw ini diorientasikan sebagai teladan, “Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak”.
Dengan manusia yang berakhlak mulia, niscaya terbangun masyarakat dan negara yang berkarakter mulia. Sudahkah pendidikan yang digelar selama ini telah menggapai secara tepat pesan tertinggi dari kehadiran sosok paling mulia tersebut? Sudahkah kita selama ini terpanggil untuk membangun manusia-manusia Indonesia yang berakhlak mulia.
Para pendidik mestinya sudah paham tentang risalah ini, meski terkesan diabaikan dengan ungkapan politik yang gagap nalar dengan menyatakan agama tidak hadir dalam urusan negara. Ingatlah bahwa setiap pejabat ataupun guru, dosen, widyaiswara, sampai kepala desa atau kelurahan, sewaktu memulai kariernya senantiasa disumpah dengan menyebat “Nama Allah”. Bukan menyebut nama undang-undang, bukan menyebut nama negara, bukan menyebut nama jabatan, tetapi “dengan menyebut nama Allah, saya bersumpah” (sebagai guru). Kalaulah demikian berarti seluruh piranti keagamaan, termasuk pesan mengonstruksi penyempurnaan akhlak adalah titian spektakuler yang semestinya diemban oleh para pendidik.
Kenapa di Unas ada kecurangan, kenapa di Pilpres ini banyak kejadian nista berupa “pembegalan suara”. Ini secara umum dalam konteks Hardiknas merupakan produk dari pendidikan yang selama ini hanya menjadikan anak didik seperti mesin pembelajaran. Sibuk dengan kurikulum yang mengunggulkan kepintaran tanpa kemantapan iman. Proses pendidikan yang kering dari makna tauhid. Pelajaran agama bahkan disendirikan sebagai mata pelajaran, bukan sebagai mata pendidikan yang semua mata pelajaran bersendikan agama. Akibatnya tauhid umat rapuh.
Adakah anak-anak semakin santun berperilaku? Kita lupa tentang pendidikan tetapi fasih pengajaran. Adakah laku Ki Hajar Dewantara dengan motto pendidikan yang luas: “Ing ngarso sung tulodo (menjadi teladan), ing madyo mangun karso (menjadi penuntun), dan tut wuri handayani (menjadi fasilitor) telah diejawantah? Pendidikan itu harus menghadirkan kesejatian diri. Narasi ini mengantarkan rute perjalanan bangsa untuk mengingat terus-menerus sumber otoritasnya yang tetap dialirkan pada cawan pendidikan tunas bangsa.
Ada syair yang sering dikutip Bung Karno untuk menjadi peneguh: De toorts/Ontstoken in de Nacht/Reiken wij Voorts/Aan het Nageslacht. Artinya: Obor yang kita nyalakan/Dalam malam gulita/Kita terus serahkan/Kepada Tunas Bangsa. Sebagai permenungan untuk membuka lembaran historis pendidikan bangsa ini ke depan, saya teringat ucap Jose M.A. Capdevilla yang disitir Mochtar Lubis: Aqui tengo una voz enardecida/Aqui tengo una vida combatida …/Aqui tengo un rumor, aqui tengo una vida …/Ini suaraku yang meradang/Ini hidupku penuh perjuangan …./Ini pesanku, ini hidupku. Mari menyambut pendidikan baru dengan manusia berakhlak mulia, bukan “manusia-manusia lalat”.
* Koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga