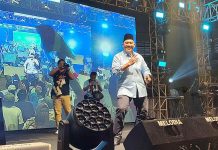Oleh: Suparto Wijoyo*
PADA mulanya saya hendak menuliskan tentang krisis ekologis yang menyertai gerbang musim penghujan yang mengiringkan awan maupun petir yang menyambar. Tetapi ada kehendak politik yang jauh lebih perlu mendapatkan sedikit seputaran mendung Ibu Kota yang “menggeledekkan” jagad pemilu atas nama HAM yang berpulang kepada Putusan MK. Orang-orang gila pun manusia yang memiliki HAM untuk turut mencoblos dalam gelanggang pileg dan pilpres 17 April 2019. Alasan itu sangat wajar dan mudah dinalar sebagaimana KPU mendemonstrasikan argumentasinya sambil menetapkannya dalam DPT. Lantas persyaratan teknis disorongkan agar orang gila boleh memberikan suaranya, mereka harus membawa serta surat “keterangan sehat” yang menandakan dirinya sudah waras, tidak hilang ingatan, berakal budi yang berhak menikmati demokrasi.
Kalaulah begitu kenapa TNI dan Polri tidak sekalian diberi hak mencoblos asal dengan syarat bahwa selama di luar areal pemilu tetap tidak ikut-ikutan berpihak. Anggota TNI-Polri paham jua bahwa di bilik suara semua menjadi sangat rahasia, sehingga semua WNI berkompeten menentukan pilihan. TNI-Polri yang netral itu diatributi alasan hukum di luar TPS, kalau sudah masuk ke dalam tenda dan mencoblos di bantalan suara, hanya dirinya sama Tuhan yang mengetahuinya. Bukankah ini juga menghargai peran TNI-Polri yang jelas-jelas sehat, bila perlu diberi pengantar oleh komandannya masing-masing bahwa anggota TNI-Polri ini waktu datang ke TPS berstatus netral melalui surat keterangan netral dari satuannya. Selanjutnya soal nyoblos kan rahasia. Anggota TNI-Polri itu terang dijamin tidak gila, pasti waras, kenapa tidak ikut mencoblos? Netralitas itu dalam tugas negara, sementara dia juga mendapatkan mandat demokrasi untuk memilih. Pilihan yang rahasia.
Pemilu 2019 memang unik dan terkesan paling sesuai dengan “jiwa demokrasi” bahwa setiap jiwa adalah angka-angka yang bisa distatistikkan menjadi kekuatan kekuasaan. Hari-hari ini niscaya berkelindan persekutuan orang gila untuk membentuk order “kedaulatan rakyat gila”. Dengan ikut pemilu, orang-orang gila itu memiliki kesadaran tinggi karena bereaksi setelah mengerti atas hak konstitusionalnya. Sebuah realitas yang tidak hanya fenomenologis tetapi sangat sistemis dengan kecenderungan tertentu: ke mana mereka hendak digiringnya.
Inilah pemilu yang mewadahi orang-orang gila yang berkesadaran politik. Ingatan saya langsung menelusuri rekaman cerita beberapa waktu lalu, ada orgil yang mampu menyasar ulama, bukan yang lain, semisal kuli bangunan atau pedagang sayur. Orgil ini mampu bertindak selektif dan juga pandai bermain peran dengan tampilan meyakinkan. Panggung sosial saat itu mempertontonkan kehebatan betapa orgil mampu bertindak tepat sasaran. Saya menjadi sangat terkesima dengan aktor orgil dalam menyikapi posisi kiai, dengan aparatur hukum yang dituntut menimang penuh pertimbangan mengingat orgil dianggap tidak elok diminta pertanggungjawaban.
Tampilan orgil kisahnya semakin ganjil: pembunuhan ulama di Jawa Barat yang juga pernah menimpa keluarga kiai di Jombang di era lama serta menyeruak di kasus “kolor ijo” maupun “Ninja Banyuwangi” tahun 1998. Konteksnya nyaris serupa dalam genderang politik nasional yang menghangat. Merujuk Laporan Tim Pencari Fakta dari KISDI amatlah terang “cerita” pembantaian ulama di Banyuwangi yang “dilakukan orang-orang gila” yang mampu bertindak “sangat presisi”.
Atmosfirnya selaksa lazuardi yang mempertontonkan “parade kecerdasaan” dengan menuang “genderang kegilaan”. Adakah hadirnya orang-orang gila dalam pentas pemilu perebutan jabatan pemerintahan itu pada dasarnya diawali oleh “pemain-pemain waras”? Orang-orang waras yang tidak tahan menghadapi realitas menjadi sangat tertekan jiwanya, karena khawatir tidak dapat menggapai “mimpi berkuasa” yang sangat emosional. Situasinya persis seperti yang dianalisis oleh Jean-Paul Sartre dalam karyanya Theory of The Emotions (1962).
Emosi orang-orang itu merefleksikan sebuah keadaan yang terjadi berulang-ulang dalam situasi yang sulit dan hal ini bukanlah soal karakter, melainkan soal perasaan yang fluktuatif. Berarti “kegilaan orang-orang” pembunuh ulama atau peserta pemilu memenuhi kategori model “perasaan yang fluktuatif” yang tidak mampu bertanding dengan ksatria. Munculnya orang-orang gila yang pandai memilih untuk membangun kerumunannya itu menjadikan saya semakin tertarik membaca ulang Kitab Kebijaksanaan Orang-orang Gila (‘Uqala’ al-Majanin) yang ditulis Abu Al-Qasim An-Naisaburi yang terbit pertama kali 1987.
Buku ini memuat 500 kisah muslim genius yang dianggap gila dalam sejarah Islam, ditulis 1.000 tahun lalu. Terdapat mutiara hikmah yang banyak dari pustaka ini: Wahai Sa’dun, mengapa engkau tidak bergaul dengan masyarakat? Sa’dun bersyair: Menjaulah dari orang-orang supaya mereka menyangkamu takut. Tak perlu kau menginginkan saudara, teman, dan sahabat. Pandanglah manusia dari mana pun kau suka. Maka yang akan kau lihat hanyalah kalajengking.
Sengatan kalajengking itu memang mengenang dan soal urusan orgil terus meretas bercampur aduk dengan adegan yang mendentum di cakrawala nusantara. Dalam konteks yang agak berbeda menjadikan saya mencermati juga buku La Nuit karya Elie Wiesel yang mengungkapkan kisah anak Yahudi yang mengalami penderitaan di Kamp Nazi Jerman. Kekejaman yang diderita berujung pada kosa kata hanya mukjizat yang diharapkan mampu mengatasinya. Buku yang amat bersahaja dalam menampilkan lakon keberadaan manusia di tengah segala kemelut yang dapat memusnahkan manusia (dalam kasus ini hanya sekadar meraih kuasa), ialah agar manusia dapat berkembang menjadi manusia yang lebih manusiawi, yang mempunyai landasan kasih.
Ya … orang-orang gila itu memang membutuhkan kasih, termasuk kasih KPU. Pesan Elie Wiesel amatlah dalam dan itu tampak tidak mampu dimainkan dalam gelora pemilu. Kondisinya sungguh telah menambah kelambu publik semakin tampak kisut. Tapi biarlah. Tidakkah kita dapat bersuara bahwa akan datang kekuatan baru dalam pemilu, yaitu sepasukan orang-orang yang semula gila tetapi kini memiliki kewarasan baru menyambut hadirnya pemimpin baru. Begitukah?
* Kolomnis, akademisi Fakultas Hukum, dan koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga