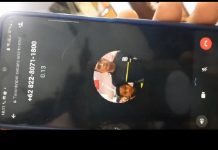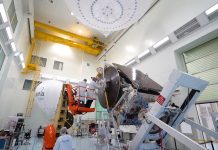Oleh: Suparto Wijoyo*
KATA Pilpres, Pileg, dan Ppemilu hari-hari ini kian menyeruak sebagai a global buzz-word, kata yang menggelora atas nama demokrasi. Kata itu menarik perhatian semua lapisan masyarakat. Para selebriti sampai kalangan ulama dan akademisi memberikan atensi atas apa yang memukau dari istilah yang berisikan ajakan untuk “menjadi mekanisme pergantian kepemimpinan secara sah”. Itulah yang diajarkan di bangku-bangku kuliah sejak zaman kolonial. Pemilihan pastilah menghendaki ada yang dipilih. Dalam bahasa tertentu Pemilu itu harus “nyetrum banget”. Semua warga sebaiknya terhanyut dalam arus suara yang muncul sebagai ekspresi peradaban celoteh bernegara. Ini sejatinya adalah wujud paling hiperbolik di mana terminologi Pemilu lahir dan kemudian hadir ke ruang global sampai jengkalan lokal. Bahkan pada ujung deret waktu ada bincangan tentang muslim peduli Pemilu.
Dalam rentang kosmologi inilah, saya harus menghadirkan diri pada acara yang dihelat oleh Radio Suara Muslim pada Rabu, 20 Februari 2019. Sebagai orang yang telah mendapatkan pembelajaran tiada jeda tentang demokrasi, maka Pemilu itu langkah prosedural untuk mengkristalisasi kehendak rakyat sebagai material. Dalam Pemilu akan tertuangkan kedaulatan rakyat agar tersalurkan dengan satu kehendak bahwa Pemilu itu pasti ada yang dipilih. Dalam Pemilu ada pilihan-pilihan yang harus diberikan dan ada yang memilih. Pemilu bukan soal netral karena dalam pemilu diajangkan dengan memanggungkan yang dipilih dan pemilih. Namanya saja pemilihan pastilah ada yang dipilih. Pemilu bukan undian dan bukan pula soal netral-netral. Kalau ditanya apakah dalam Pemilu ini Anda akan netral berarti Anda berada dalam posisi tidak memilih atau memilih semuanya. Apabila langkah ini yang diberikan niscaya pilihanmu tidak sah dan berarti ini bukan Pemilu tetapi netralu, alias netral umum.
Apakah kemudian tidak usah ada pemilihan apabila semua harus dalam posisi netral? Nah netral pada tingkatan siapa? Tentu hanya ada dalam tingkatan penyelenggara dan aparatur negara yang melayani penyelenggaraan Pemilu. PNS-ASN harus netral. Ok. Tapi mereka netral dalam pengertian yang sangat formalistik, sebab netralitas PNS bukan menafikan hak suaranya. Mereka tetap mempunyai hak untuk memilih sehingga tidaklah ada PNS-ASN netral dalam soal pilihannya. Netralitasnya PNS yang formalitas itu bukan berarti pura-pura melainkan taat aturan dalam penyelenggaraan Pemilu. Tegasnya ya netral di luar berpihak di dalam, dalam bilik pencoblosan.
Dengan demikian saya adalah orang yang netral selaku pihak yang berada dalam status PNS tetapi saya tetap punya pilihan dalam kerangka berdemokrasi. Untuk menghadapi kelindan netralitas yang formalitas itulah tidak serta-merta setiap ekspresi PNS dipersekusi atau dibatasi, apalagi dikriminalisasi. Pembatasan ekspresi mulai dari warna busana sampai pada peragaan jemari tangan sebelah menandakan bahwa penyelenggara negara tidak paham dengan fungsi persepsional tupoksi ASN dalam konsepsi Pemilu.
Maka dalam acara tersebut saya memberikan contoh-contoh ekspresi yang agar tidak dipersalahkan, saya cenderung menggunakan kata tanya, aksentuasi, dan aksi mohon penjelasan. Inilah yang saya namakan mengambil posisi berjarak dalam ruang yang sempit. Sama, anak-anak juga akan memiliki ruang rengekan sebagai bagian dari langkah-langkah diplomatiknya untuk menyampaikan kehendaknya kepada orang tua. Setiap kesempatan harus diamanfaatkan untuk menyedot perhatian orang tua. Dan Pemilu sejatinya soal kegembiraan rakyat dalam merayakan kedaulatannya yang disediakan orang tua (negara).
Penyelenggara Pemilu hanya menjaga agar kegembiraan itu tidak usahlah membaur-baurkan diri menjadi ledakan tetapi biarlah terzonasi demi kenyamanan ekspresi. Untuk itulah tidak boleh ada berbedaan warna dan pilihan serta ekspresi jari olok-olok atau diintimidasi. Inilah ajaran demokrasi yang bermuatan perbedaan sebagai hal yang lumrah, natural dan oleh karena itu sangatlah legal. Begitulah mestinya hukum Pemilu diperlakukan.
Memang sekarang ini dunia hukum mengalami problema yang nyaris sama. Apa yang diungkapkan umum tentang peradilan ada juga peradilan sesat. Ini adalah dentuman besar yang semestinya menggedor langit hukum nasional. Ada yang cetho welo-welo tidak terjamah oleh hukum, sementara yang benderang maupun remang tidak “melanggar banget” dipersekongkolkan dalam koalisi yang mengerikan. Atmosfer penegakan hukum semakin disilang-sengkuratkan. Hukum yang mestinya menjamin ketertiban dan kepastian dengan jiwa keadilannya, tampak menumpahkan dendam. Law enforcement dipertontonkan penuh onak dan ontran-ontran sambil menunjukkan “akulah yang kuasa”.
Pendidikan hukum sebagai “endapan pikir” seharusnya menjelajahi wilayah-wilayah ilmu hukum dan non hukum secara interaktif. Gagasan UUD 1945 yang mempermaklumatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (“rechtsstaat”) bisa tergugat manfaatnya. Kenyataan konstitusional ini merupakan indikator mengenai kesahihan profesi hukum dalam koridor UUD 1945. Para juristenrecht atau lawyer’s law alias “pengembang ilmu hukum” wajib berkontribusi mengembangkan dan meneguhkan hukum yang bersemayam “di ketiak kekuasaan” agar tidak disumpahserapahi.
Pembelajaran hukum tidak boleh berotasi linier tanpa sedia berdialog dengan pemanggul tradisi kritis. Hukum jangan dikerangkeng dalam space ketersendiriannya yang tersorot penguasa semata. Hukum bukan menara gading dan mercusuar purba. Hukum yang terbidik sebagai hukum –“rule of law” (bukan “rule of man”) yang mengabaikan kepatutan sosialnya (“social reasonableness”) dan rasa keadilan pada ritme tertentu akan kehilangan orientasinya sebagai bagian hakiki kemanusiaan (humanistic studies).
Ke depan meski sedikit spekulatif, kita memiliki impian agar hukum selalu dirindu rasa adilnya. Bagaimana rakyat merasa nyaman diayomi oleh hukum dengan aparaturnya yang membopong rakyat, bukan menjadikan hukum sebagai alat penindasan bagi yang lemah atau untuk dilemahkan atau pemilu justru hendak menyeragamkan pilihan. Dalam pemilu ini saya teringat Jula-Juli Zaman Edan di buku Air Kata-kata tulisan Sindhunata: Bale bunder gawange bolong/Rakyate mblenger janji sing kosong.
*Esais, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga