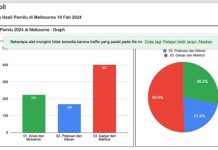“Ini mestinya dijauhi oleh NU. Meminjam istilah Kiai Sahal Mahfud, NU harus berada di politik tingkat tinggi. Politik tingkat tinggi itu politik kenegaraan, bukan politik praktis atau politik rendahan.”
Oleh: Mukhlas Syarkun*
TULISAN saudara Ainur Rafiq Al Amin di harian Kompas, 13 Februari 2019), judul “NU dalam Pusaran Pilpres 2019” , intinya keterlibatan NU dalam pilpres adalah sesuatu yang menuntut agar NU cancut taliwondo dan dapat dirumuskan sebagai berikut:
Pertama, meyakini langkah ini tidak melanggar Khitthah dan AD/ART, sebab Kiai Ma’ruf Amin sudah mengundurkan diri. Sementara Cak Anam juga merujuk AD/ART menegaskan keputusan itu melanggar, bahkan menyalahi prinsip-prinsip dasar musyawarah, qanun asasi.
Pendapat Cak Anam diperkuat KH Tholchah Hasan yang menilai, ini telah melakukan desakralisasi Rais Aam, demikian juga Gus Solah (KH Salahuddin Wahid), beliau menilai bahwa ini telah melakukan degradasi Rais Aam.
Dampaknya NU akan menjadi bulan-bulan dan NU sudah kehilangan legitimasi bicara moral, karena posisi yang sakral (Rais Aam) sebagai simbol kekuatan moral dalam menentukan arah kebijakan organisasi dicampakkan begitu saja.
Kedua, bahwa keterlibatan NU dalam Pilpres 2019 dan selanjutnya menjatuhkan pilihannya pada petahana, yang konon (katanya) dalam rangka menjaga NKRI, memposisikan NU sebagai penyangga negara. Niatan itu telah bertolak belakang (ternodai) oleh keinginan Kiai Miftakhul Akhyar (yang dinobatkan sebagai Rais Aam) dan Kiai Said Aqil Siroj Ketua Umum PBNU. Di mana keduanya menyatakan bahwa NU akan memasuki era baru dari (ashabul haq ke ashabul qarar), artinya NU akan masuk dalam politik praktis perebutan kekuasaan.
Padahal, ini mestinya dijauhi oleh NU. Meminjam istilah Kiai Sahal Mahfud, NU harus berada di politik tingkat tinggi. Politik tingkat tinggi itu politik kenegaraan, bukan politik praktis atau politik rendahan.
Karena itu dapat disimpulkan arah PBNU sekarang meninggalkan high politics (politik tingkat tinggi) menuju ke level politik rendahan (politik praktis), yang syarat dengan kepentingan. Dengan begitu, maka, secara otomatis peran penyangga negara menjadi hilang seketika.
Inilah yang kemudian oleh Gus Solah dalam wawancara dengan TvOne, diluruskan (keinginan
ashabul qarar). Itu adalah tidak benar. NU harus tetap dalam posisi sebagai kekuatan masyarakat sipil (high politics) sejajar dengan masyarakat politik, supaya tetap berfungsi sebagai penyangga negara.
Harus Terpisah Ulama dengan Umara
Begitu juga ketika merujuk hadits nabi yang popular, bahwa bangunan negara akan kokoh jika ditopang oleh oleh empat penyangga yaitu (bi-’ilmi ulama, bi-’adlil umaro, bi-sakhowati aghniya’, bi-du’ai fuqara).
Oleh karena itu, ulama dan kaum intelektual (sebagai ashabul haq) harus terpisah dengan umara (sebagai ashabul qarar) untuk saling menopang supaya negara tetap tegak dan kuat.
Ketiga, keterlibatan NU dalam Pilpres 2019 konon (katanya) dalam rangka menghadang laju gerakan radikal dan menuding kelompok radikal sudah ada di pasangan 02. Isu ini tentu paradoks dengan cara pandang warga NU sendiri yang lebih melihat Pilpres pada visi missi secara subtansi yaitu kemaslahatan.
Apalagi isu radikal (wahabi-HTI) adalah pengulangan seperti ini pernah dihembuskan di pilkada DKI. Katanya jika Ahok kalah, maulid nabi akan dilarang, kenyataannya justru sebaliknya, sebab Anis Baswedan justru melakukan maulid nabi bersama Habib Luthfi di Monas yang dulu tempat itu dilarang Ahok untuk dibuat acara maulid.
Jika radikal merujuk adanya gerakan HTI, maka itu sebuah kemunduran, sebab gagasan khilafah HTI ilusi belaka. Mulai kapan NU takut dengan ilusi, padahal dengan PKI saja saja tidak takut apalagi dengan HTI.
Keempat, pilihan struktur NU pada petahana ini juga katanya telah didukung oleh kiai sepuh (nama nama kiai sepuh dimaksud sama sebagaimana di pilkada Jatim yang mendukung Gus Ipul), ini juga paradoks dengan hasil pertemuan kiai sepuh yang tergabung dalam ‘Forum masyayikh , habaib dan kiai’ yang melakukan musyawarah di Sidogiri dan menilai potret kebijakan rezim petahana dianggap tidak mampu mewujudkan maslahah, sebab rezim petahana tidak mampu menjaga hal-hal yang fundamental.
Rezim ini dinilai gagal dalam hifdhu ad-din (tidak mampu menjaga agama, kerena umat terbelah secara tajam) tidak mampu hifdhu an-nafes (karena penegakkan hukum yang tajam kebawah tumpul keatas) tidak mampu hifdhul mal (tidak mampu menjaga kekayaan, kenyataannya utang tambah banyak ).
Selain itu dalam rekomendasi di Sidogiri, menegaskan bahwa membanjirnya TKA adalah madharrat yang nyata, begitu juga impor pangan –garam telah memukul perekonomia warga NU itu sendiri (yang mayoritas petani dan petambak garam), maka berlaku kaidah “darul mafasid muqaddamu ‘ala jalbil masalih” (menghindari madharrat harus didahulukan sebelum menggapai maslahah).
Oleh karena itu, wajar kemudian keputusan (“Forum masyayikh , habaib dan Kiyai” ) di Sidogiri adalah ganti rezim dan bahkan dengan terang-terang mendeklarasikan mendukung pasangan Prabowo-Sandi.
Nah, jika terjadi paradoks yang demikian ini — antara elit struktur dan kultur NU — maka hasilnya bisa diprediksi seperti Pilkada DKI dan Pilkada Jatim. Akankah terulang? Wallahu ‘alam.
Jakarta
13, Februari 2019
Mukhlas Syarkun (Ketua PKB Cabang Istimewa Malaysia tahun 1999)