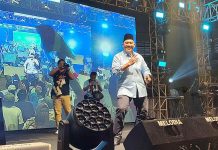“…kecintaan terhadap tanah air atau nasionalisme tidak seharusnya dikontrakdisikan dengan kecintaan terhadap agama. Masing-masing memiliki wilayahnya.”
Oleh: Achmad Murtafi Haris
SUATU ketika ada seorang netizen memasang status di akun FB yang berbunyi: Nasionalisme dan agama adalah dua kutub yang tidak bertentangan (KH Hasyim Asy’ari). Status ini mendapat komen positif dari banyak teman dan ada juga yang megkritiknya. Kritik tersebut mengatakan bahwa Agama harus didahulukan dan bukan tanah air.
Tanggapan senada mengutip sebuah dalil bahwa siapa yang mati demi sebuah fanatisme, maka dia mati jahiliyyah. Terkandung arti di sini bahwa mereka yang mati demi selain Islam, seperti demi membela negara adalah mati Jahiliyyah.
Menjadi tanda tanya besar di sini akan nasib para pejuang dan pahlawan yang mati membela negara, apakah tergolong yang demikian, mati Jahiliyyah?
Menjawab pertanyaan di atas yang intinya menyoal legalitas nasionalisme dalam perspektif hukum Islam atau fiqih, adalah sesuatu yang fundamental. Mengingat bahwa semua umat Islam di dunia saat ini hidup dalam sistem negara bangsa yang mendengungkan cinta tanah air dan bela negara. Nampak pula di sini bahwa konsep Nation State bagi sebagian muslim masih dipersoalkan.
Terkait hal ini, baik Nahdlatul Ulama mau pun Muhammadiyah, telah sepakat bahwa Negara Bangsa secara fiqih dibenarkan. Hal ini muncul dalam hasil Muktamar NU ke-11 di Banjarmasin (1936) yang menyatakan bahwa wilayah Nusantara adalah Darul Islam atau wilayah umat Islam yang harus dibela.
Pembelaan terhadap wilayah ini adalah fardlu ‘ain bagi segenap muslim Indonesia. Selain keputusan ini masih ada lagi yang lain yang menunjukkan dukungan Nahdlatul Ulama terhadap nasionalisme.
Muhammadiyah pun demikian halnya, selain menelorkan tokoh yang kelak dikokohkan sebagai pahlawan nasional seperti Kasman Singodimejo, yang paling mutakhir pada Muktamar Makassar 2015, Muhammadiyah menyebutkan bahwa negara Pancasila adalah Darul ‘Ahd wa Syahadah (DAWS). Yang mengandung makna bahwa Indonesia adalah buah kesepakatan luhur para pendiri bangsa yang harus dipertahankan. Sekaligus mengandung makna kewajiban bagi Muhammadiyah dan umat Islam Indonesia untuk membuktikan sumbangsihnya kepada negara.
Selain pernyataan dukungan terhadap Nation State atau Negara Bangsa yang keluar dari ormas terbesar Indonesia, dalam banyak karya tafsir klasik terdapat kandungan ajaran nasionalisme.
Seperti dalam menafsirkan al-Qashash: 85: “Sesungguhnya (Allah) yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al-Qur’an benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali”, Al-Razy dalam Mafatih al-Ghayb mengatakan bahwa ‘tempat kembali’ itu adalah Makkah tanah yang paling dicintai Rasulullah. Dalam tafsir Ruhul Bayan, Ismail Haqqi al-Hanafi mengutip sebuah hadits bahwa Rasulullah SAW (dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah) banyak sekali menyebut kata; “tanah air, tanah air” (al-Watan), kemudian Allah SWT mewujudkan permohonannya (dengan kembali ke Makkah).
Sahabat Umar RA berkata; “Jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek (gersang), maka sebab cinta tanah air lah, dibangunlah negeri-negeri”. Dari sini jelas bahwa cinta tanah air atau nasionalisme adalah fitrah yang mendapat legitimasi Quran dan hadits.
Sedangkan makna Ashabiyyah yang dilarang dalam Islam menurut Sheikh Abdul Aziz al-Najjar ulama al-Azhar mengatakan bahwa ia terkait dengan fanatisme kesukuan, golongan, ras, faham dan feodalisme yang menjadikan seseorang merasa bangga dan lebih mulia dari yang lain.
Munculnya ketidaksetaraan dan diskriminasi sosial adalah akibat dari fanatisme semacam. Suatu hal yang tumbuh subur dan menjadi sistem sosial di zaman Jahiliyyah yang kemudian dihancurkan oleh Islam. Islam mengusung egalitarianisme dan menjadikan ukuran kemuliaan pada kualitas individu dan ketakwaan kepada Allah SWT.
Bilal b. Rabbah yang berkulit hitam dan bekas budak diangkat derajatnya dan Abu Lahab yang ningrat direndahkan karena tingkat ketakwaan. Pertikaian kerap terjadi pada zaman pra-Islam karena fanatisme ini dan hal ini pula yang sering memicu pertikaian di pelbagai belahan dunia hingga saat ini khususnya di negara miskin.
Di sisi lain, kecintaan terhadap tanah air atau nasionalisme tidak seharusnya dikontrakdisikan dengan kecintaan terhadap agama. Masing-masing memiliki wilayahnya. Kecintaan terhadap anak dan isteri tidak perlu dikontradiksikan dengan kecintaan kepada ibu. Demikian juga dengan kecintaan kepada ulama tidak perlu dikontradiksikan kepada Nabi. Masing-masing ada tingkatannya dan tiap tingkatan ada yang dicintainya.
Mengatakan cinta kepada isteri tidak berarti tidak cinta kepada ibu. Mencintai pasantren tempat dia mengaji bukan berarti tidak mencintai kampus tempat dia kuliah. Mencintai negara pun tidak berarti menomorduakan Islam agama yang dipeluknya. Masing-masing berhak mencintai banyak figur bahkan untuk tingkat yang sama dan tidak harus dikontradiksikan satu dengan yang lain.
Dalan sebuah hadits disebutkan: dari Anas b. Malik Rasulullah bersabda “Tidak beriman salah satu di antara kamu hingga aku (Rasulullah) lebih dicintai daripada anak dan orang tua dan sekalian manusia”. (HR. Bukhari). Sementara di sana ada hadits: “Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua”. (HR. Ibn Hibban dan jama’ah). Hadits ini seolah berlawanan dengan hadits sebelumnya. Yang pertama mengunggulkan Nabi sedangkan yang kedua mengunggulkan orang tua.
Yang tepat dalam menyikapinya adalah tidak mengkontrakdisikan antara keduanya. Apalagi yang menyatakan keunggulan orang tua adalah nabi sendiri.
Dalam hadits yang dari Abu Hurairah juga disebutkan bahwa Rasulullah ditanya oleh seseorang tentang siapakah yang paling utama untuk ditemani? Rasulullah menjawab: Ibumu, kemudian Ibumu, kemudian Ibumum baru yang keempat Bapakmu. (Muttafaq Alaihi).
Apakah kemudian Rasulullah tidak utama untuk ditemani, sebab Rasulullah tidak tersebut di situ. Tentu tidak demikian. Masing-masing memiliki konteks dan sekupnya.
Andaikan hanya berpegang pada hadits yang pertama, yang menjadikan kecintaan kepada Rasulullah melebihi segalanya sebagai syarat keimanan, dalam prakteknya pun tidak boleh hingga menelantarkan anak-istri dan kepentingan banyak.
Mengapa? Karena Rasulullah melarang hal itu. Dari sini kemampuan memahami ajaran agama secara holistik, berimbang, proporsional sesuai konteks dan tatarannya masing-masing adalah kunci pengamalan ajaran agama yang baik dan benar. Ini bukanlah perkara mudah. Ia adalah proses tiada henti dari pangkuan ibu hingga ke liang lahat. (end)
*Achmad Murtafi Haris adalah dosen UIN Sunan Ampel Surabaya.