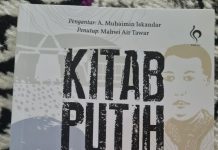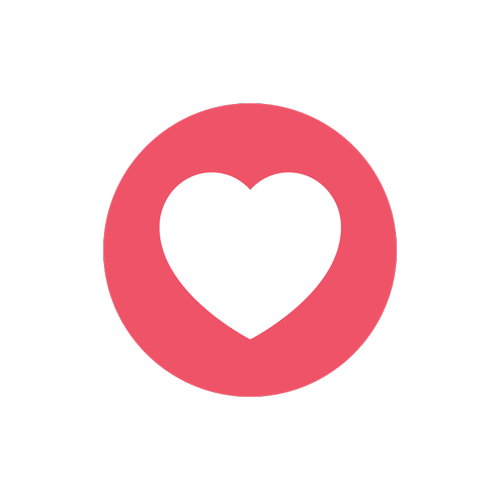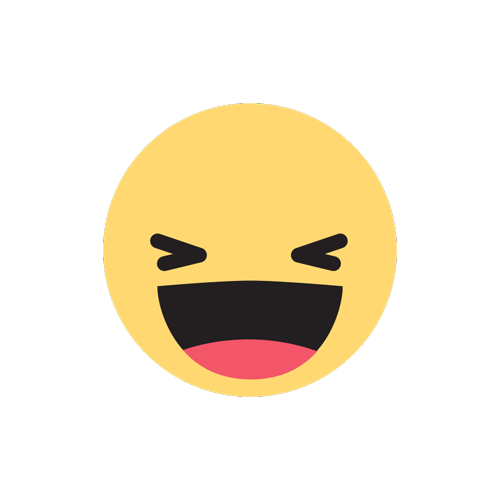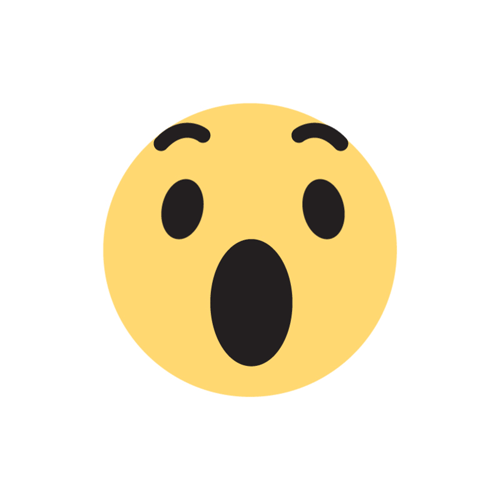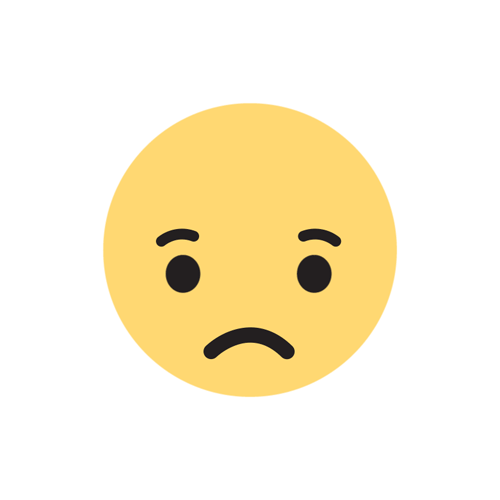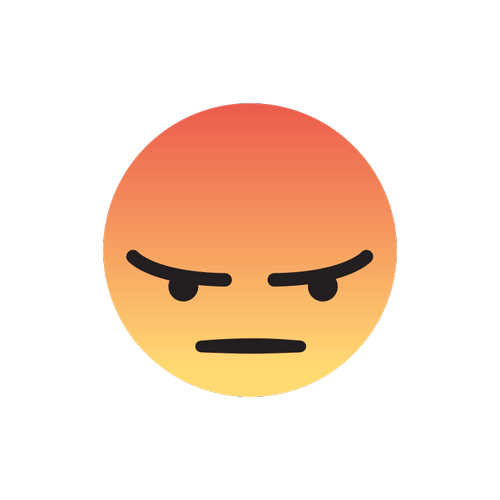“Setiap santri dituntut menunjukkan kebarakahan ilmu pengetahuan yang dipelajari melalui proyek perubahan sosial di masyarakat. Maka setiap santri wajib memiliki inisiatif yang tinggi, bersikap kreatif, dan mengamalkan ilmu pengetahuan secara progresif.”

Oleh Ahmad Muttaqin
PERKEMBANGAN pesantren saat ini dengan berbagai spesialisasi dan variasinya, tidak terbayang sebelumnya. Layaknya lembaga pendidikan modern, pesantren berkembang menuju spesialisasi kejuruan seperti Al-Qur’an, bahasa, wirausaha, dan kajian spesifik lainnya. Gejala ini muncul dalam 10 tahun terakhir bersamaan dengan spesialisasi pendidikan modern yang dimobilisasi secara massif melalui sekolah-sekolah kejuruan. Kondisi ini sangat berbeda dengan zaman klasik di mana para ulama mendirikan pesantren lebih pada upaya meningkatkan kompetensi santri, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan membangun masyarakat yang berakhlak mulia (Dhofier, 2019).
Pertimbangan yang sama dilakukan Hadratussyaikh KH M Hasyim Asy’ari pada saat mendirikan pesantren Tebuireng 125 tahun lalu, yaitu pertama kualitas masyarakat yang mengalami degradasi akibat kolonialisme dalam waktu yang panjang (Fijriah dan Ellisa, 2022). Degradasi ini terutama terjadi karena masyarakat tidak dapat mengakses pendidikan secara berkualitas, bahkan diperlakukan diskriminatif. Pendidikan merupakan hal mewah yang hanya bisa diakses oleh kelompok elit yang terdiri dari kalangan kulit putih (kolonial), ningrat, dan pembesar pemerintah lainnya.
Kedua, pengembangan ilmu pengetahuan yang hanya mungkin dilakukan melalui proses belajar-mengajar. Pendidikan formal hanya bisa diselenggarakan oleh pemerintah dan diikuti oleh siswa secara terbatas. Oleh karena itu, para ulama termasuk Hadratus Syaikh KH M Hasyim Asy’ari memilih membentuk lembaga pendidikan mandiri dan mengembangkan materi dan pendekatan pembelajaran yang khas dan dapat diikuti oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Pesantren dengan pembelajaran keagamaan Islam kemudian menjadi lembaga pendidikan alternatif yang kemudian mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat. Pesantren dengan aktivitas utama pembelajaran mendorong bertumbuhnya kegiatan ilmiah pengembangan ilmu pengetahuan.
Ketiga, rendahnya pendidikan masyarakat berimplikasi langsung terhadap perilaku sosial yang jauh dari peradaban luhur. Kriminalitas, kemaksiatan, dan perilaku anomali lainnya menjadi hal yang lazim terjadi setiap saat (Mahfudz, 2024). Kondisi ini menjadi keprihatinan Hadratus Syaikh KH M Hasyim Asy’ari yang kemudian mendorongnya lebih kuat untuk melakukan perubahan.
Agensi-Struktur Pesantren
Dalam sejarahnya, pesantren memerankan fungsi agensi dan struktur sekaligus. Kiai dan pesantren menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mendorong perubahan sosial, politik, dan kebudayaan di masyarakat. Bourdieu (1990) mengkonsepsikan bahwa perilaku sosial bukan hanya diproduksi oleh determinasi struktur obyektif atau eksistensi subyektif, tetapi keduanya secara interaktif. Pesantren sebagai struktur obyektif didefinisikan oleh Kiai sebagai lembaga pendidikan Islam yang berorientasi terhadap ilmu pengetahuan dan peradaban. Sebaliknya, Kiai dikonstruksi oleh pesantren sebagai figur sentral yang memiliki mandat untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan mentransformasi masyarakat menuju peradaban yang lebih baik.
Kiai-pesantren membentuk habitus religiusitas yang ditawarkan kepada masyarakat sebagai pengganti tradisi sebelumnya yang dinilai kurang beradab. Identitas pesantren yang mengambil nama desa/dusun dimaknai sebagai strategi Kiai mempromosikan sekaligus memaksa lingkungan sosial di dalamnya mengikuti tradisi dan kebiasaan baru yang berbeda dengan sebelumnya. Proses yang berlangsung intensif dan terus-menerus kemudian mengubah perilaku dan tradisi masyarakat tanpa disadari. Hal inilah yang sesungguhnya dilakukan oleh Kiai dengan pesantrennya, mengubah masyarakat secara ideologis sehingga tidak menimbulkan konflik dan menilainya sebagai kelaziman. Hadratus Syaikh KH M Hasyim Asy’ari membentuk habitus Tebuireng untuk mengubah masyarakat yang sebelumnya sarat dengan perilaku-perilaku anomalis.
Selain mengubah secara ideologis kepada masyarakat internal, pembangunan habitus religius diarahkan untuk membentuk identitas sebagai basis pengembangan interaksi eksternal. Habitus ini menjadi modal sosial (social capital) yang dimanfaatkan untuk membangun interaksi dalam panggung kontestasi yang diikuti oleh berbagai entitas sosial. Hadratus Syaikh KH M Hasyim Asy’ari aktif mementaskan Tebuireng dalam berbagai panggung sosial, politik, dan budaya. Melalui kontestasi ini, panggung sosial tidak dikuasai oleh kelompok dominan dari kalangan kulit putih (kolonial) dan elit-elit yang berafiliasi dengan kekuasaan. Pesantren dan Kiai hadir dengan identitas baru yang berbeda dengan mainstream dan merepresentasikan cara hidup orang pribumi yang lebih egaliter, beradab, dan kohesif.
Santri sebagai Agen Perubahan
Santri merupakan agensi kedua pesantren dan menjadi bagian integral dari eksistensi Kiai. Meskipun secara struktural santri merupakan seseorang yang belajar dan menimba ilmu kepada Kiai, tetapi posisi fungsionalnya kurang lebih sama dengannya. Santri menjadi representasi Kiai dan pesantren di masyarakat. Pembelajaran yang mengintegrasikan antara guru dengan murid sebagaimana Kiai-santri di pesantren tidak ditemukan di lembaga-lembaga modern. Hal ini terjadi karena metode pembelajaran di pesantren bukan hanya diarahkan untuk mentransfer ilmu pengatahuan dan keterampilan tetapi juga moral dan etik. Kiai bukan hanya sebagai guru, tetapi juga pendidik yang dituntut menjadi role model dan teladan bagi para santrinya.
Hadratus Syaikh KH M Hasyim Asy’ari sebelum mendirikan pesantren Tebuireng adalah pribadi yang komplet. Selain sebagai ulama dengan penguasaan ilmu yang memadai, Hadratus Syaikh KH M Hasyim Asy’ari adalah pengusaha (saudagar) yang terbilang mapan. Dengan demikian, pilihannya mendirikan pesantren jauh dari tujuan-tujuan bisnis atau memperbanyak keuntungan kapital. Saifuddin Zuhri (2001) menceritakan orang-orang pesantren tidak memiliki motif selain ilmu pengetahuan dan pendampingan masyarakat mewujudkan kesejahteraan sosial. Sebelum mendirikan pesantren, umumnya para Kiai telah memiliki cukup modal kapital untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan tidak membebani para santrinya.
Kondisi di atas menunjukkan bahwa pesantren sejak awal didesain oleh Kiai pendirinya sebagai media pengembangan ilmu pengetahuan, penguatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan, dan transformasi sosial. Spirit yang dikembangkan pesantren adalah perubahan sosial berbasis pada ilmu pengetahuan dan berorientasi pada peradaban luhur (akhlaqul karimah). Proses pembelajaran pesantren seperti ini dalam istilah Habermas (1988) disebut dengan praksis. Ilmu pengetahuan tidak bebas nilai, tetapi membawa nilai dan kepentingan untuk meningkatkan emansiapsi manusia melalui proses sosial, politik, dan kebudayaan.
Kesadaran emasipatif santri ditekankan selama proses pembelajaran di pesantren. Konsep “barakah” bukan hanya dimaknai secara transendental, tetapi lebih operasional dalam wujud kemanfaatan ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Setiap santri dituntut untuk menunjukkan kebarakahan ilmu pengetahuan yang dipelajari melalui proyek perubahan sosial di masyarakat. Dengan tuntutan ini maka setiap santri wajib memiliki inisiatif yang tinggi, bersikap kreatif, dan mengamalkan ilmu pengetahuan secara progresif. Upaya transformasi sosial terus-menerus inilah yang sesungguhnya menjadi peran dan kontribusi santri sebagaimana didesain oleh para Kiai.
*Ahmad Muttaqin adalah Alumni Pesantren Tebuireng tahun 1997 Dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto