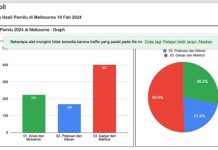Oleh: Suparto Wijoyo*
MUSIM telah menjadi terdakwa sebagai penyebab banjir. Seluruh warga di sepanjang bantaran Bengawan Solo maupun DAS diminta waspada. Apa yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia diminta waspada. Pun yang tinggal di Bojonegoro, Lamongan, dan Gresik yang areal hidupnya tergenang air seolah melengkapi “pesta air” di Jombang, Pasuruan, bahkan Brebes. Banyak kolega dari Jakarta, Semarang, Purwokerto, Palembang, dan Medan ketika di Surabaya sontak mendapatkan pemahaman kolektifnya bahwa inilah prestasi abadi yang terus dibopong penuh bangga. Titik-titik geografis Surabaya pusat, selatan, dan barat sering berubah menjadi sungai dadakan di kala hujan.
Berbagai media massa mewartakan jua tragedi banjir yang mengancam puluhan provinsi di Indonesia. Dalam skala yang lebih kolosal, banjir telah menyebar di areal 103 wilayah, dan 274 kabupaten/kota berpeluang menyelenggarakan “panen banjir”. Inilah fenomena yang acapkali terjadi setiap musim penghujan. Banjir menjadi tradisi tahunan yang dimaklumi dengan kerugian ekonomi, sosial dan lingkungan melebihi dari yang dapat bayangkan. Moda transportasi yang mengusung laju barang, orang dan jasa tersumbat dengan konsekuensi logis terganggunya sirkulasi kehidupan publik dalam memenuhi kebutuhannya.
Terhadap rendaman air yang disebut banjir itu, banyak pihak menyuarakan dengan nada dasar yang sama: bahwa “tingginya intensitas hujan” dianggap sebagai penyebab utama. Air hujan menjadi sang “pelaku “yang menyebabkan banjir dengan segala penderitaan yang ditimbulkannya. Luapan sungai, kali atau bengawan di seluruh koordinat NKRI diberi label sebagai “pemegang saham” terjadinya banjir yang melanda daratan.
Mengapa air hujan yang sejak penciptaannya dengan gerak hukum-hukum alamiahnya dan dimaknai secara teologis sebagai nikmat, berubah menjadi laknat? Mangapa hujan yang diharap sebagai berkah tumpah menjadi prahara? Mengapa sungai, kali atau bengawan bisa meluap dan muntah yang membanjiri sawah ladang serta rumah? Adakah penisbatan hujan sebagai penyebab tunggal terjadinya banjir itu suatu kebenaran?
Hujan bukan penyebab banjir, sehingga banjir bukanlah soal menjemput takdir. Banjir itu soal pengelolaan sumber daya alam, tata kota, tata pemerintahan, manajemen lingkungan, yang pada akhirnya adalah tata laku publiknya. Banjir pada ujungnya bermula dan berakhir pada konsepsi pembangunan yang dianut serta diimplementasikan oleh penyelenggara negara. Hal ini berarti masalah banjir adalah urusan bernegara yang berkaitan dengan public policy yang diformulasi oleh negara. Dengan demikian orientasi memilih jalan pembangunan sangat menentukan ke mana pergerakan banjir diarahkan.
Air hujan tidak akan melaju menerjang desa ke kota, kalau di setiap wilayah tersedia bank air yang menampung. Bank air itu dapat berupa kawasan konservasi, hutan kota, hutan desa, dan telaga-telaga yang sejak era abad IV dikembangkan nenek moyang dan mencapai tingkat kemajuan di abad keemasan Majapahit (XIII-XVI). Satu thani, kabuyutan –padukuhan– memiliki telaga dengan pepohonan yang memadai disertai lumbung pangan. Konstruksi ini berorientasi tentang suasana bernegara yang rakyatnya menikmati irigasi pertaniannya, sanitasi perkotaannya, dan sandang-pangan-papan yang berkecukupan.
Sejatinya abad generasi millenial ini tidak untuk menghindari tradisi itu tetapi mengembangkannya dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Pembangunan mall, supermarket, property, dan gedung-gedung tinggi dapat diimbangi dengan membangun embung-embung yang representatif secara planologis dengan balutan ruang terbuka hijau sebagai areal konservasinya. Dengan pola ini air hujan dapat bercengkerama secara ekologis dengan pepohonan, bercerita dengan hutan rakyat, hutan kota, hutan konservasi serta taman-taman rumah. Air hujan menjadi kerasan bersamanya tanpa perlu lari kencang guna bersimpuh di perut sungai, kali ataupun bengawan, apalagi dengan membawa potongan kayu yang ditinggal pencurinya. Bagaimana sungai tidak meluap, di kala perutnya tidak lagi menampung luberan, bukan karena dia tidak sayang air hujan, tetapi pendangkalan yang dialami akibat erosi, itulah yang ditangisi sungai dengan konsekuensi kesejahteraan rakyat yang terabaikan.
Terhadap hal ini kita ingat tulisan lama James Goldsmit, The Trap waktu jadi Capres tahun 1994 yang disampaikan di hadapan 2000 orang di Grand Amphitheatre Universitas Sorbonne, Paris bahwa: setiap masyarakat di dunia modern sedang menghadapi problem rumit dan tidak ada solusi yang sederhana dan universal. Tetapi banyak di antara problem ini memiliki akar yang sama. Ilmu, teknologi, dan ekonomi telah diperlakukan oleh masyarakat modern ini sebagai tujuan itu sendiri, bukannya sebagai sarana penting untuk meningkatkan kesejahteraan.
Meningkatnya kemerosotan lingkungan telah pula sampai pada tataran merenungkan kembali keberadaan negara kesejahteraan. Peran negara dan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat harus ditata kembali kalau banjir tetap menjadi tradisi. Peran negara dengan pemerintah pada kahirnya sampai pada perbincangan yang bersentuhan dengan economic performance global, regional maupun nasional. Pembangunan berkelanjutan menyorongkan pelaksanaan pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa menggerus kepentingan generasi mendatang dengan memadukan pilar ekonomi, sosial dan ekologi secara integral.
Dengan konsepsi fundamental demikian, ternyata tetap saja dipersepsi bahwa yang berkelanjutan adalah pembangunannya dengan dampak ikutan kehancuran lingkungan maupun kerapuhan sosial yang berupa kemiskinan, termasuk akibat banjir. Ini menandakan di ranah pembangunan berkelanjutan terdapat fakta yang senantiasa muncul dalam bentuk disparitas, ketimpangan sosial sekaligus penggadaian kekayaan alam yang dalam bahasa tertentu dinyatakan terjadinya kapitalisasi ekologi yang telah melampaui batas-batas yang bisa ditoleransi.
Kondisi ini pasti mengguncang tatanan sosial, ekonomi dan ekologi secara paralel. Penguasa mesti menyadari tentang kekeliruannya dalam membiarkan penyalahgunaan ruang dan pada akhirnya harus bersedia kembali ke ajaran leluhur: satu kampung satu embung, satu gayung, satu lumbung, satu saung. Mengikuti kata-kata Anthony Giddens, ini adalah bagian dari “kesadaran diri dan perjumpaan sosial”.
*Esais, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga