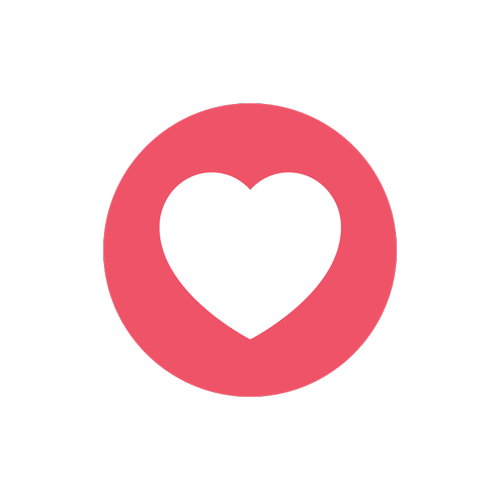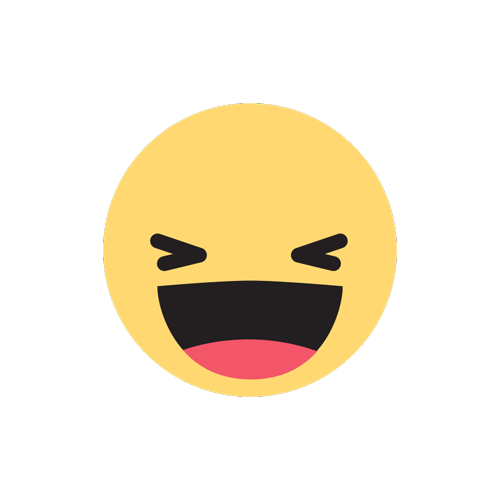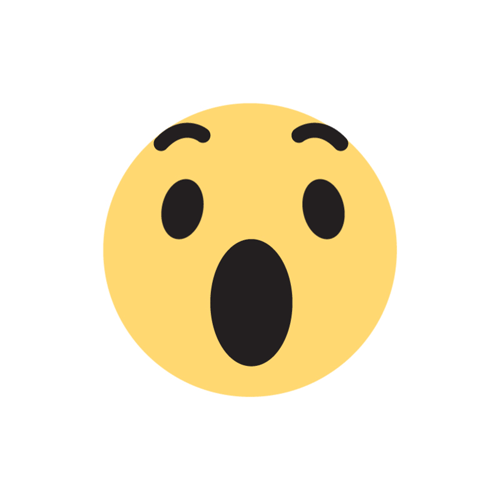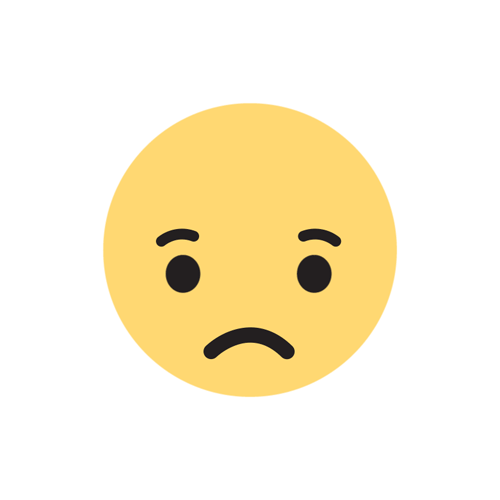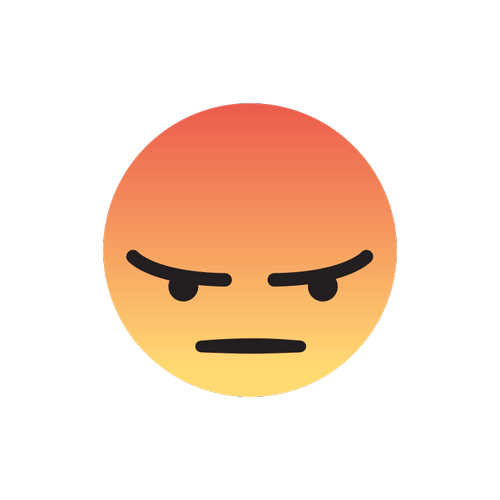Ketika nilai luar dijadikan tolok ukur universal, perbedaan budaya kehilangan konteks; kemanusiaan pun berubah menjadi ruang penghakiman.
Publik baru-baru ini dihebohkan oleh tayangan salah satu program di Trans7 yang menyorot kehidupan di pesantren dengan nada miring. Dalam segmen tersebut, tradisi santri yang ngabdi kepada kiai disebut-sebut sebagai bentuk “perbudakan modern.” Klaim ini kontan menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama dari lingkungan pesantren dan pemerhati budaya Nusantara.
Padahal, menilai sebuah tradisi dengan kacamata budaya lain adalah bentuk penghakiman kultural yang keliru. Dalam khazanah pesantren, praktik khidmah bukan sekadar “bekerja tanpa upah,” melainkan bagian dari pendidikan spiritual yang menanamkan nilai keikhlasan, kesabaran, dan tanggung jawab. Di sinilah sering kali terjadi kesalahpahaman: budaya yang lahir dari spiritualitas dimaknai dengan logika ekonomi semata.
Benturan Nilai dan Kekeliruan Perspektif
Apa yang terjadi sejatinya bukan sekadar perdebatan moral, melainkan benturan nilai antara dua sistem budaya. Ketika satu budaya menilai budaya lain dengan ukuran dirinya, yang muncul bukan dialog peradaban, melainkan judgement penghakiman yang kehilangan konteks.
Masalahnya, penghakiman semacam itu tidak bisa dilakukan apple to apple. Setiap peradaban memiliki sejarah, fondasi nilai, dan pandangan dunianya sendiri. Peradaban Tiongkok tak bisa diukur dengan standar India; India tak dapat disamakan dengan Arab; demikian pula Nusantara dengan Barat semuanya memiliki logika kebudayaan yang unik dan tak dapat diseragamkan.
Namun dalam percakapan global modern, nilai-nilai Barat dengan jargon “kesetaraan mutlak” dan “kebebasan absolut” sering dijadikan tolok ukur universal. Padahal, nilai-nilai tersebut lahir dari pengalaman sosial dan sejarah Barat yang berbeda jauh dengan konteks peradaban Timur, yang lebih menekankan harmoni, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial.
Islam dan Etika Menghormati Perbedaan
Islam memandang keberagaman sebagai bagian dari sunnatullah. Dalam Al-Qur’an ditegaskan: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa serta bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa.” (QS. Al-Hujurat: 13)
Ayat ini menegaskan bahwa manusia memang diciptakan berbeda baik suku, bangsa, maupun tradisinya bukan untuk diseragamkan, melainkan untuk saling mengenal (lita‘aarafuu). Maka, ketika satu budaya memaksakan ukuran tunggal atas budaya lain, sejatinya ia sedang menolak kehendak Tuhan atas keberagaman itu sendiri.
Karena itu, penghakiman terhadap tradisi pesantren dengan logika Barat bukan hanya kesalahan ilmiah, tetapi juga pelanggaran etika keberagaman. Peradaban yang matang justru lahir dari kesediaan untuk memahami, bukan dari keinginan untuk mengadili.
Tradisi Pondok Pesantren
Tradisi yang hidup di pesantren tidak lahir dari ruang hampa, tetapi berakar dari nilai-nilai syariah Islam. Penghormatan kepada ahli ilmu adalah perintah agama itu sendiri. Model penghormatan bisa bermacam-macam sesuai adat budaya masing-masing. Sepanjang adat itu tidak bertentangan dengan syariat, maka ia sah dan bahkan bisa menjadi bagian dari nilai syariah. Kaidah fikih menegaskan, al-‘adah muhakkamah adat dapat menjadi dasar hukum.
Sebagai contoh, kebiasaan mencium tangan guru, menata sandal orang tua, atau membantu kiai adalah bagian dari nilai luhur pesantren yang berakar pada ajaran Islam.
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, beliau pernah memegangkan tali kendali unta Sahabat Zaid bin Tsabit RA saat Zaid hendak keluar dari pertemuan. Melihat hal itu, Zaid berkata, “Biarkan, wahai Ibnu Abbas”. Namun Ibnu Abbas menjawab, “Demikian kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW memperlakukan ulama kami”. Mendengar itu, Zaid turun dari untanya, lalu berkata, “Berikan tanganmu, wahai Ibnu Abbas.” Setelah tangan itu diberikan, Zaid menciumnya seraya berkata, “Dan demikian kami diperintahkan memperlakukan keluarga Nabi Muhammad SAW”.
Kolonialisme Nilai Baru
Dunia hari ini tengah menghadapi bentuk baru dari kolonialisme: penjajahan makna. Nilai-nilai yang diklaim “universal” sering kali membawa misi ideologis tertentu. Dalam wacana global yang tampak modern, terselip upaya dominasi kultural yang perlahan menghapus identitas lokal dan spiritualitas yang menjadi fondasi moral masyarakat Timur.
Ketika Barat menjadikan dirinya ukuran tunggal bagi kemanusiaan, dunia kehilangan harmoni; manusia berhenti memahami, dan hanya sibuk menilai. Inilah krisis etika global: keberagaman yang seharusnya menjadi sumber hikmah justru berubah menjadi alat penghakiman.
Menutup dengan Kesadaran Peradaban
Peradaban yang benar-benar beradab bukanlah yang paling seragam, melainkan yang paling mampu menghormati perbedaan. Selama manusia masih mau mengenal sebelum menilai, memahami sebelum menghakimi, dunia akan tetap memiliki harapan untuk hidup damai di bawah payung kemanusiaan yang sejati.
Karena itu, menghormati perbedaan bukan sekadar sopan santun budaya, melainkan bentuk tertinggi dari kecerdasan spiritual.
Penulis: Gus Abdul Latif Malik, pengasuh Ponpes Asrama Ar’Rohmah Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang