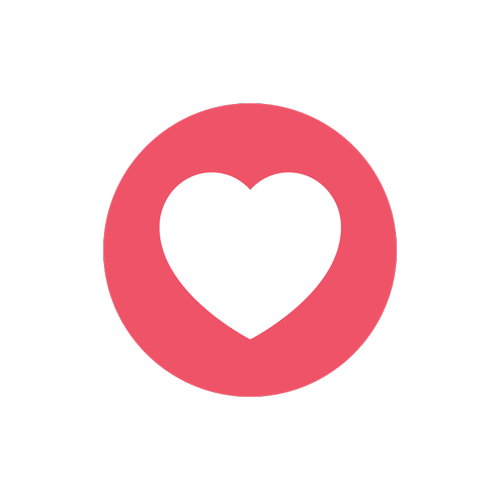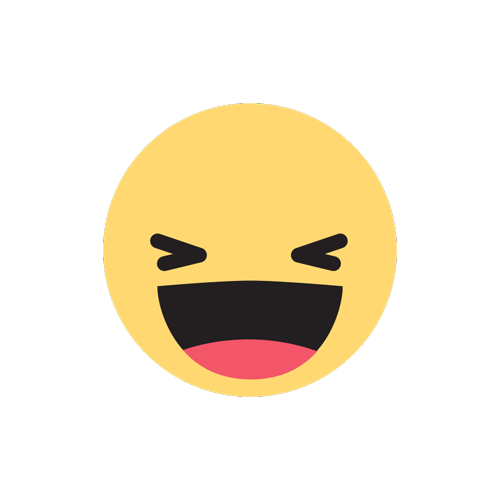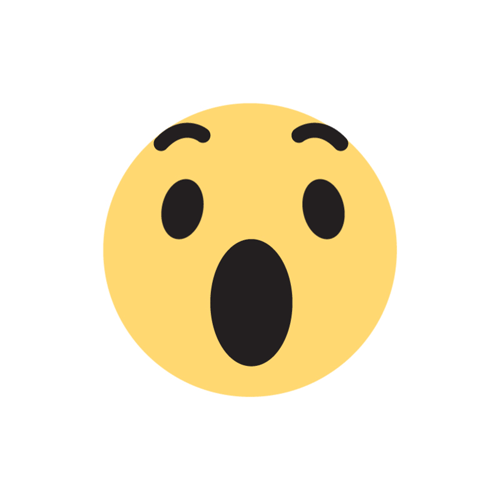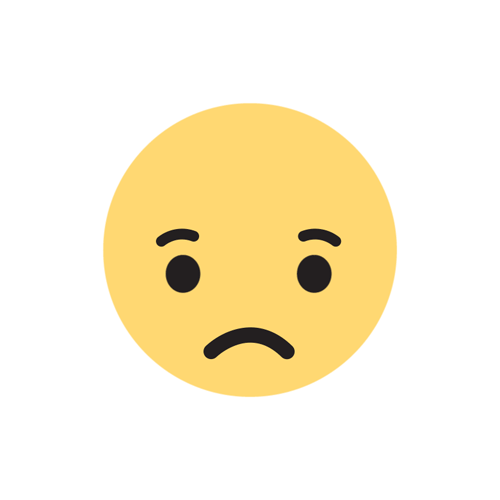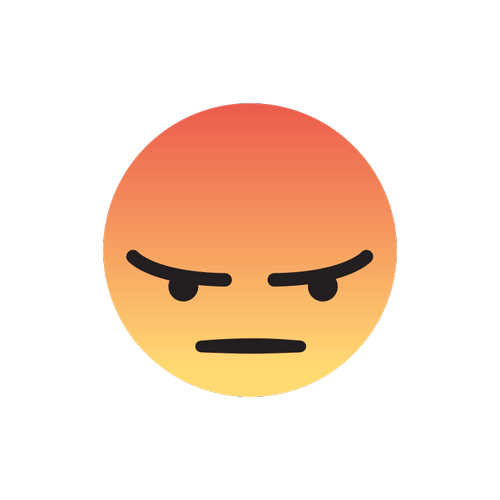“Di balik derap laju modernisasi dan hiruk-pikuk regulasi pendidikan tinggi, sebuah entitas keilmuan tumbuh dalam keheningan pesantren—Ma’had Aly. Negara memang mengakui keberadaannya, namun belum sepenuh hati. Pertanyaannya: apakah Ma’had Aly akan terus menjadi permata terpendam?”

Oleh: Dr H ROMADLON, MM, Pengurus LPPD Provinsi Jatim
SUATU siang yang teduh di sebuah pesantren di Yogyakarta, para pengasuh Ma’had Aly dari seluruh Indonesia berkumpul dalam forum bertajuk Intisyar Dusturi. Forum ini bukan sekadar ajang diskusi regulasi, tetapi sebuah muara dialektika antara tradisi dan modernitas. Di tengah lantunan ayat suci dan aroma kitab kuning yang menguar dari lembaran-lembaran tua, mereka membincang masa depan pendidikan tinggi Islam dengan penuh kehati-hatian, seolah menjaga nyala lentera warisan ulama agar tak padam tertiup angin zaman.
Ma’had Aly, sejak disahkan dalam regulasi negara sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi Islam, membawa harapan besar: mencetak ulama yang bukan hanya menguasai teks, tetapi juga konteks. Dengan pendekatan metodologis khas pesantren seperti tahqīq, taʿlīq, syarḥ, hingga ḥāsyiyah, Ma’had Aly menawarkan alternatif epistemologi yang kokoh, yang tak dapat diakomodasi oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) biasa.
Namun sayangnya, pengakuan yang telah diberikan negara melalui Kementerian Agama (Kemenag) belum sepenuhnya menjelma dalam praktik nyata. Ijazah Ma’had Aly masih dipertanyakan legalitasnya di banyak sektor. Ini bukan sekadar soal administratif, melainkan menyangkut martabat kelembagaan, dan lebih dari itu: menyangkut keberlangsungan tradisi keilmuan Islam di Indonesia.
Pengakuan Separuh Hati Itu
Pengakuan formal terhadap Ma’had Aly dimulai sejak KMA No. 407 Tahun 2015, yang kemudian diperkuat dengan KMA No. 941 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Pendidikan Ma’had Aly dan KMA No. 128 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu. Dalam dua dekade terakhir, negara melalui Kementerian Agama mulai membuka ruang formal bagi entitas ini agar bisa tumbuh sejajar dengan perguruan tinggi lainnya.
Namun, pengakuan ini masih menyisakan paradoks. Dalam wawancara dengan Mahrus, Kasubdit Pendidikan Ma’had Aly, ia mengakui bahwa hingga saat ini, ijazah Ma’had Aly belum sepenuhnya diterima sebagai dokumen resmi setara dengan ijazah universitas. “Kita sudah memiliki regulasi. Tapi implementasi di lapangan belum seragam. Banyak instansi yang belum memahami apa itu Ma’had Aly,” ujarnya.
Menurut Prof. Nur Ichwan, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, ini bukan semata soal birokrasi, tetapi lebih pada soal keberanian negara untuk menegaskan posisi Ma’had Aly dalam sistem pendidikan nasional. “Ma’had Aly adalah lembaga kaderisasi ulama, bukan sekadar tempat belajar agama. Negara seharusnya memberikan perlakuan afirmatif, bukan malah setengah hati,” tegasnya.
Distingsi Akademik dan Spiritualitas
Apa yang membuat Ma’had Aly berbeda? Jawabannya terletak pada pendekatan metodologisnya. Di saat PTKI sibuk mengejar akreditasi dan publikasi jurnal internasional, Ma’had Aly justru kembali ke akar: pendalaman makna teks, pemurnian logika berpikir, dan pelestarian khazanah turats.
Metode tahqīq (penyuntingan kritis naskah klasik), taʿlīq (catatan kontekstual), syarḥ (penjabaran atas teks), dan ḥāsyiyah (komentar tingkat lanjut) bukan sekadar cara baca, tapi juga cara hidup. Metodologi ini menjadikan setiap mahasantri tidak hanya cendekia, tapi juga memiliki adab keilmuan—sesuatu yang kerap hilang dalam pendidikan modern.
Seperti dijelaskan oleh KH Afifuddin Muhajir, Rais Syuriah PBNU dan anggota Majelis Masyayikh, “Ma’had Aly itu tempat pembentukan ulama, bukan hanya dosen. Ulama itu bukan orang yang sekadar tahu, tapi yang tahu bagaimana menanggung beban umat.”
Intisyar Dusturi: Tafsir Baru atas Regulasi
Intisyar Dusturi bukan sekadar forum sosialisasi, tetapi semacam deklarasi sunyi: bahwa mutu tak boleh menghapus tradisi, dan standarisasi tak semestinya mengebiri orisinalitas epistemik pesantren. Di forum yang digelar secara bergilir dari satu ma’had ke ma’had lainnya ini, para musyrif, musyrifah, dan pengasuh Ma’had Aly sepakat—regulasi negara harus diterima, tapi dengan tafsir yang tetap memberi ruang bagi jiwa pesantren.
Salah satu hasil penting dari forum tersebut adalah penegasan muatan lokal turats sebagai pilar kurikulum yang tak bisa ditawar. Dalam diskusi panjang, para peserta menolak penyeragaman yang menjauhkan Ma’had Aly dari khazanah keilmuan Islam klasik. Di sinilah, muncul istilah baru: “standarisasi bercita rasa pesantren”—yakni upaya menyeimbangkan antara tuntutan administratif negara dengan ruh keilmuan khas pesantren.
Kiai Mahbub, pengasuh Ma’had Aly di Jawa Tengah, menyampaikan dengan lirih namun tegas, “Kalau negara mengatur Ma’had Aly seperti mengatur kampus, lalu di mana tempatnya ngaji pasaran, halaqah subuh, dan sorogan? Ini bukan nostalgia, tapi pertarungan eksistensial.”
Jalan Panjang Menuju Kemandirian
Salah satu tantangan besar Ma’had Aly adalah keberlanjutan. Dengan anggaran yang minim, ketergantungan pada pesantren induk, dan keterbatasan akses terhadap fasilitas riset serta publikasi, banyak Ma’had Aly yang bertahan lebih karena semangat pengasuhnya ketimbang dukungan struktural.
Beberapa ma’had telah mencoba mendobrak keterbatasan ini. Di Jawa Timur, misalnya, sebuah Ma’had Aly mendirikan markaz tahqīq naskah yang bekerja sama dengan lembaga internasional untuk menyunting dan menerbitkan manuskrip langka. Di tempat lain, beberapa mahasantri aktif menulis di jurnal-jurnal bereputasi, tanpa kehilangan ruh taʿlīq mereka.
Namun semua ini belum cukup. Yang dibutuhkan adalah keberpihakan. Negara harus hadir, bukan sekadar sebagai regulator, tapi juga fasilitator dan advokat. Tanpa ini, Ma’had Aly akan tetap berada di pinggiran, menjadi lembaga yang diakui di atas kertas, tapi diabaikan dalam praktik kebijakan.
Membayangkan Masa Depan Keislaman Indonesia
Sebagian pihak bertanya: Apakah Ma’had Aly relevan di era digital? Pertanyaan itu barangkali keliru arah. Sebab bukan Ma’had Aly yang harus mengejar zaman, tetapi zaman yang harus memahami kembali apa yang disebut hikmah.
Bayangkan jika Ma’had Aly diberi ruang berkembang seperti Universitas Al-Azhar di Kairo atau Qom di Iran—bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga center of excellence untuk pemikiran Islam kontemporer berbasis turats. Indonesia, yang sejak lama dikenal sebagai tanah moderat dan toleran, justru bisa memiliki pilar keilmuan yang berakar dan berdialog aktif dengan zaman.
Sudah saatnya negara menjadikan Ma’had Aly sebagai investasi strategis—bukan sekadar simbol warisan budaya, tetapi sebagai jawaban atas kebutuhan zaman: ulama yang otoritatif, berpijak pada nash, dan peka terhadap realitas.
Penutup
Ma’had Aly adalah oase keilmuan di tengah gurun industrialisasi pendidikan. Ia bukan hanya ruang belajar, tetapi ruang peradaban. Jika negara sungguh-sungguh ingin membangun masa depan Islam yang tercerahkan, maka pengakuan terhadap Ma’had Aly harus menjadi pengakuan yang utuh—tidak hanya administratif, tapi juga epistemik, spiritual, dan politik.
Karena sesungguhnya, di balik ijazah yang tak diakui, tersembunyi cahaya ilmu yang tak lekang oleh zaman. Bukankah begitu, waallahu’alam. (*)