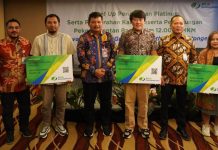Oleh: Suparto Wijoyo*
KUDETA menjadi kata yang ramai di pekan ini. Militer Myanmar melakukan itu dengan penuh selubung. Demokrasi dikebiri dan pemilu dianulir. Persis kisahknya di Mesir dan banyak negara yang menirunya. Tetapi lebih dari itu, serunya adalah dugaan adanya gerakan terencana, soal pengambilalihan kekuasaan secara tidak terhormat dalam tubuh partai politik. Demokrat menjadi “berang” dan kata Cak Mispon memberikan reaksi atas pengakuan kadernya mengenai suatu realitas kehendak. Kehendak untuk memimpin Demokrat. Hal ini semakin ramai karena ada “saur manuk” untuk saling menuding.
Hal itu biarlah menjadi bincangan warung kopi atau jagongan santai di kala pandemi. Intinya, kudeta itu menyangkut “rebutan kekuasaan” tetapi mekso. Dan pahamlah bahwa tidak ada pemain peran yang memiliki keluasan panggung bermain sandiwara melebihi dari mereka yang berebut. Semua perangkat kelembagaan maupun kemasyarakatan memasrahkan diri dalam sandaran kursi kuasa. Setiap jengkal ruang khalayak menyediakan diri penuh penghambaan sambil mempersilahkan agar “yang dipertuan” mengagung-agungkan diri. Sak karepmu.
Soal kekuasaan bukan saja mengenai protokolnya melainkan juga tentang keagungan atau berdrama ria. Boleh memelaskan diri dengan membuang uniform baju kebesaran, sepatu, perahu, bahkan lencana dipilih yang sebagaimana umumnya, guna berperan menjadi pengelana tanpa prasangka. Silahkan dipotret dan diviralkan untuk konsumsi media massa yang mampu mengunggahkan simpati bolo dewo. Laku ini dapat diberi dalil yang diimajinasikan kepada tindakan Nabi Musa As (1527-1407 SM), yang sebelum memangku mandat lanjutan dari Tuhan, harus menapaki bentang Gurun Sinai dengan “saling menawar”, karena “penyerahan firman” itu berlangsung di areal yang suci sehingga harus polos tanpa atribut apapun.
Soal kudeta, ada kisah yang malah menyerahkan kuasanya. Kisah yang disulam seperlakuan dengan Sang Raja Balkh, pemangku kekuasaan paling terhormat di teritorialnya yang beristana megah tanpa dapat dilukiskan. Nyaris kanfas para pelukis terkorek lusuh di kala menatap keanggunan Istana Raja Balkh, Ibrahim bin Adham. Namun Ibrahim bin Adham yang wafat tahun 782 M ini memiliki keterpanggilan batin untuk berkelana dengan melapas alas kakinya untuk menepi menjadi manusia biasa yang nyiwak (menyingkirkan) sahwat kekuasaan. Dia lempar kemegahan kerajaan dengan mengenakan jubah robek penuh tambalan. Pilihan hidup “Pangeran Balkh” ini sangat menakjubkan. Air, pohon dan ikan berebut menyodorkan baktinya.
Ngladeni orang alim, wali Allah seperti Ibrahim bin Adham tidak terbatas pada orang-perorang tetapi angin, awan-tanah dan hujan berebut membaktikan dirinya. Para pecinta kisah-kisah sufi tentu sangat mafhum bagaimana Ibrahim bin Adham sewaktu hendak menambal jubahnya yang terobek di tepian sungai Tigris, tiba-tiba jarumnya terjatuh ke sungai yang mengalir deras. Orang yang menyaksikan terus bergumam merasa sedih dan membatin: nasib apa yang dialami oleh Ibrahim bin Adham, dari penguasa nomor satu dalam imperium besarnya, kini terlunta dalam perjalanan dengan busana jubah penuh tambalan, dan jarumnya pun tidak sudi bersahabat dengannya. Tuhan benar-benar mencabut semua nikmatnya. Begitu pikir awam yang melihat dengan kasat mata jasadnya, tetapi “kelam ruhaninya”. Simaklah apa yang kemudian terjadi. Ibrahim bin Adham cukup mengucap lirih dengan penuh iman, “kembalikan jarumku”. Sontak berpuluh-puluh ikan datang menyodorkan jarum emas untuk dipersembahkan kepada sang maulana yang suci ini. Dia mengulang ungkapannya, kembalikan jarumku: seekor ikan anakan melompat mendekat sambil menyerahkan jarum milik “pangeran pengelana tanpa alas kaki” ini. Subhanallah.
Ibrahim bin Adham mencapai puncak kewalian ini dengan kesungguhan tanpa perlu “membawa-bawa media” agar tindakannya menarik perhatian. Bandingkan dengan video penguasa yang marah-marah di kantor pemerintahan kelas atas maupun level kecamatan yang “dipasarkan” dan saya paham: pemilih macam apa yang “memborongnya”. Era abad ke-8 saat itu, medsos bukan tidak ada, tetapi tidak digunakan, dan pastinya ditampik oleh Sang Sufi untuk meraih posisi kembali ke Istana. Sementara itu di abad milenial ini terjadi sebaliknya. Kekuasaan digondeli untuk diperebutkan dengan mekanisme pemilu yang digelar tanpa jemu.
Pilkada-pilpres dijadikan ajang untuk pamer cara-cara memperebutkan kekuasaan, bukan untuk menggembalakan rakyat dalam rezim kepemimpinan. Semua yang dipertontonkan adalah gelegak berkuasa, bukan gairah untuk memimpin: yang diselenggarakan kemudian adalah pentas sosok penguasa-penguasa, bukan pemimpin-pemimpin, yang ada adalah kasir-kasir, bukan bendahara-bendahara, yang tampak adalah kepala rumah tangga, bukan kepala keluarga. Negara pun dianggap sekadar urusan perkasiran, bukan perbendaharaan, sekadar urusan “transaksi-transaksi, investasi-investasi untuk dijual-jual kembali, dilego-lego lagi, urusan penanamam modal sampai modol-modol (terburai), utang terus ditumpuk agar kekuasaannya tidak tergerus .
Masa Pilpres masih 2024 dijadwalkan. Namun yang mengincarnya sudah bikin janji-janji yang membanjiri setiap “lorong gang-gang”, sesempit apa pun. Mulut mereka terbuka menganga menjulurkan lidah memuntahkan “air liur yang mendatangkan gempita”. Inilah visi-misi yang dinormakan oleh hukum pemilu untuk mengentas nasib rakyat agar munggah drajat. Kaos oblong, baju bercorak, mau ambil alih ketua Parpol, sampai mobil listrik disemat dengan retorika: tanpa utang, no impor, semua barang harganya murah, listrik, air dan BBM diomongkan “terjangkau” sampeyan semuanya.
Sadarilah bahwa seluruh calon penguasa itu sejatinya sang “peminta” karena dia meminta-minta suara. Bagaimana dia mengentas kemiskinan, sementara dia sendiri berjiwa sangat miskin. Meminta dukungan suara untuk dipintal dengan tebusan karung goni janji kekuasaan dan uang. Dalam situasi demikian, rakyat tentu menyaringkan hati, mengendapkan pikir, siapa yang bermain-main, bukan sekadar penguasa yang lihai bertelenovela. Dengan segala sumber daya kekuasaan yang ada di tangannya, kepalannya saja bisa diunggah tanda “dia sangat perkasa”, hingga mampu bermain sandiwara, jadi tokoh apa saja. Kini saya teringat buku Clifford Geertz, Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali (1980/2017). Ya … Negara Teater. Hanya saja siapa yang bermain dalam meraih kuasa itu? Bacalah sendiri buku ini.
* Wakil Direktur III Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga