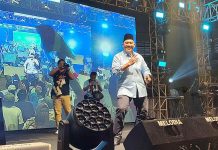Oleh : Zulfikar Ardiwardana Wanda, SH, MH.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali mengeluarkan putusan yang mengundang kontroversi di lintas kalangan. Kontroversi ini menjadi keniscayaan pasca MK menjatuhkan putusannya nomor 46/PUU-XIV/2017 pada 14 Desember 2017 yang menolak permohonan pengujian undang-undang (judicial review) yang dimohonkan oleh Guru Besar IPB, Prof Euis Sunarti dan kesebelas pemohon lainnya terkait norma hukum perzinahan, pemerkosaan dan homoseks/lesbian yang terkandung dalam ketentuan Pasal 284, 285 dan 292 KUHP warisan kolonial Hindia-Belanda.
MK berdalih menolak permohonan tersebut karena tidak berwenang dalam kapasitasnya sebagai pembatal undang-undang (negative legislator) melainkan hal itu merupakan ranah Pemerintah dan DPR selaku pembuat undang-undang (positive legislator).
Putusan ini diwarnai oleh empat pendapat Hakim Konstitusi yang berbeda (dissenting opinion) dari sembilan jumlah Hakim Konstitusi antara lain Arief Hidayat, Anwar Usman, Wahiduddin Adams dan Aswanto. Dalam kesempatan ini, penulis hanya membatasi kajian kritikal-analitik terhadap Pasal 284 dan 292 KUHP.
Jika ditelisik secara filosofis-historis, ketentuan Pasal 284 Wetbook van Strafrecht (WvS) –istilah/nama asli dari KUHP pasca diberlakukannya asas konkordansi (pemberlakuan hukum negeri kolonial ke wilayah koloni/jajahan) tahun 1918- mengatur tentang penalisasi perbuatan zina (overspel) antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan yang salah satu pelakunya masih dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain, pada hakikatnya sangat dipengaruhi mindset sekuleristik di daratan negara-negara Eropa pada waktu itu.
Paradigma semacam itu sangat berbeda dengan kondisi sosio-antropologis masyarakat Indonesia apabila di-flashback secara historis sebelum datangnya para negeri penjajah dan paradigma tersebut masih tetap lestari sebagai nilai-nilai hukum dan jiwa bangsa Indonesia hingga dewasa ini. Apabila dicermati rumusan konsep Pasal 284 KUHP di atas, pasal tersebut hanya membatasi pemidanaan/penalisasi terhadap perbuatan zina yang dianggap kejahatan terhadap kesetiaan perkawinan sehingga perbuatan tersebut dipandang menodai kesucian lembaga perkawinan.
Dengan demikian, dapat dipahami falsafah norma yang terkandung dalam Pasal 284 KUHP tentang zina telah melimitasi dan bertentangan dengan konsep zina menurut optik nilai-nilai ajaran agama (values of religion) dan hukum yang hidup serta berkembang dalam masyarakat (living law). Dalam optik values of religion dan living law bangsa Indonesia, konsep zina dipandang lebih luas, meliputi persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang terikat oleh perkawinan (adultery) maupun yang tidak terikat perkawinan (fornication). Konsep ini misalnya bisa ditemukan dalam kitab Agama Islam yang memuat norma larangan dalam QS. Al Isra: 32 “… dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” dan di dalam Agama Kristen bisa ditemukan pula dalam Surat Matius 5: 27 yang berbunyi “Kamu telah mendengar firman: Jangan berzinah”.
Pada perkembangannya, ketentuan Pasal 284 KUHP yang baru diundangkan tidak lama setelah Indonesia merdeka, dalam praktiknya telah mengalami perluasan norma oleh puncak lembaga peradilan tertinggi negara. Ketentuan ayat-ayat kitab suci di atas semakin mendapat legitimasi hukum yang kuat dan dipertegas lagi secara yuridis-normatif dengan lahirnya Putusan MA No. 93/K/Kr/1976 tentang perkara “tindak pidana zina” di Banda Aceh yang dalam pertimbangan hukumnya (ratio decidendi) memandang bahwa zina merupakan perbuatan terlarang mengenai hubungan kelamin pria dan wanita, terlepas dari persyaratan apakah salah satu pihak terikat perkawinan atau tidak sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 284 KUHP.
Pada prinsipnya konsep zina yang mengandung adultery dan fornication sebagaimana dipaparkan di atas merupakan perbuatan yang dianggap tercela dan terlarang dengan sendirinya (mala in se) yang bersumber dari nilai-nilai agama dan jiwa hukum yang berkembang dalam masyarakat, bukan perbuatan yang baru bersifat melawan hukum dan tercela karena diatur dalam undang-undang (mala in prohibita) sebagai doktrin dalam disiplin hukum pidana.
Beralih pada ketentuan Pasal 292 KUHP yang turut dimohonkan kepada MK, mengatur penalisasi pencabulan terhadap orang dewasa (laki-laki dan perempuan) yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis yang patut diketahui/diduga belum dewasa. Dengan rumusan yang demikian dapat dikatakan bahwa perbuatan homoseks atau lesbian yang sudah sama-sama dewasa tidak dipidana. Agar dapat dijerat pasal ini, orang dewasa tersebut harus tahu atau setidaknya menduga bahwa lawan yang akan dicabuli itu belum dewasa menurut undang-undang. Pasal ini memiliki persamaan dengan Pasal 284 KUHP dimana minimal ada dua orang yang melakukan. Sedangkan perbedaannya jenis kelamin yang melakukan dan zina mempersyarakatkan harus ada persetubuhan badan yang berbeda konsep dengan delik pencabulan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 292 KUHP.
Secara historis, terjadi pergulatan politik hukum yang saling bersaingan dalam perumusan Pasal 292 WvS (KUHP sekarang) antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Tweede Kamer (Parlemen Belanda) yang pada akhirnya dimenangkan oleh kaum homoseksual yang mayoritas duduk di Tweede kamer. Berdasarkan asas konkordansi, kemudian pasal ini yang termuat dalam WvS diterapkan ke dalam wilayah koloni Hindia Belanda dan semakin mendapat kedudukan hukum yang kuat pasca ditetapkankannya UUD 1945 oleh PPKI yang tetap memberlakukan WvS sebagai hukum negara Indonesia berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD sebelum amandemen agar tidak terjadi kekosongan hukum (rechtsvacuum) untuk sementara waktu. Setahun pasca kemerdekan, WvS diundangkan secara resmi oleh Pemerintah melalui UU No. 1 Tahun 1946 (berlaku untuk Jawa dan Madura) dan UU No. 73 Tahun 1958 (berlaku secara nasional) dengan istilah resmi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih tetap berlaku hingga sekarang.
Di tengah merebaknya gagasan dan penyebaran HAM pasca Perang Dunia ke-II maka semakin berkembanglah negara-negara yang mengusung HAM sebagai identitas negara modern. Euforia terhadap HAM mengalir deras tanpa batas di era globalisasi ini sehingga kaum Lesbian, Gay dan Biseks dan Transgender (LGBT) pun juga memanfaatkannya untuk pengakuan dan perlindungan eksistensinya.
Baru-baru ini pada 26 Juni 2015, Supreme Court (MA) Amerika Serikat melegalkan pernikahan sesama jenis di 50 negara bagian yang sebelumnya hanya diperbolehkan di 36 negara bagian. Melalui putusan tersebut, Supreme Court AS resmi mencabut larangan pernikahan sesama jenis yang diberlakukan di 14 negara bagian.
Namun Permasalahannya, Pasal 292 KUHP yang diuraikan di atas merupakan hukum kompromistis yang dibuat oleh Belanda dan serta merta diterapkan di Hindia Belanda, sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama, moralitas dan hukum adat masyarakat Indonesia ketika itu. Pasca kemerdekaan, melalui muatan isi Pancasila dan UUD 1945 pun, perilaku seksual menyimpang ini juga tidak mendapat tempat dan bertentangan dengan nilai ketuhanan dan nilai moralitas yang terkandung dalam sila pertama dan Pasal 28 J UUD 1945.
Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa seyogyanya MK dapat mengabulkan secara bersyarat apa yang dimohonkan oleh pemohon dalam amar putusannya. Pada perkembangannya dalam praktik, jenis amar putusan MK mengalami kreasi di luar jenis amar putusan yang ditentukan secara limitatif di dalam UU MK yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan dan permohonan ditolak.
Menurut mantan Hakim Konstitusi Harjono di dalam bukunya yang bejudul “Konstitusi sebagai Rumah Bangsa”, apabila hanya berdasarkan pada ketiga jenis putusan tersebut akan sukar untuk me-judicial review dimana sebuah undang-undang seringkali mempunyai sifat yang dirumuskan secara umum, padahal dalam rumusan yang umum itu belum diketahui apakah dalam penerapannya akan bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Maka dari itu, timbullah 2 bentuk kreasi amar putusan MK yaitu konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) dan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional).
Dalam kaitannya dengan pasal-pasal yang dimohonkan di atas, menurut pendapat penulis MK dapat menjatuhkan putusan inkonstitusional bersyarat sepanjang untuk Pasal 284 KUHP tidak dimaknai persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan oleh pihak yang terikat oleh perkawinan (adultery), tidak mencakup atau meliputi juga persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang tidak terikat perkawinan (fornication) serta sepanjang untuk Pasal 292 KUHP tidak dimaknai pemidanaan pencabulan terhadap orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis yang patut diketahui/diduga belum dewasa menurut undang-undang tidak mencakup atau meliputi juga “yang sudah dewasa menurut undang-undang”. Dalam sejarahnya, putusan inkonstitusional bersyarat pertama kali dijatuhkan pada maret tahun 2009 ketika MK me-judicial review UU Pemerintahan Daerah.
Dengan demikian, menurut pandangan penulis tidaklah tepat MK menolak permohonan pemohon dengan dalih tidak berwenang karena perannya bukanlah sebagai positive legislator. Sepanjang MK menerapkan dua bentuk kreasi putusan yaitu conditionally constitutional dan conditionally unconstitutional sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka tidak dapat dihindari MK menjalankan fungsinya sebagai positive legislator sebab norma yang ditafsirkan oleh MK tersebut menjadi sebuah norma baru yang berbeda dengan norma sebelumnya. Dalam konteks pemidanaan terkait pasal yang dimohonkan di atas yang secara tegas tercantum dalam rumusan tindak pidana, penulis tidak sependapat dengan 4 (empat) Hakim Konstitusi yang menyatakan dissenting opinion bahwa MK seyogianya harus mengambil sikap membatasi diri (judicial restraint) untuk tidak menjadi positive legislator. Menurut pandangan penulis sepanjang hal itu dibutuhkan untuk mencairkan kebekuan pasal dalam undang-undang maka sah sah saja MK melakukan penafsiran dalam rangka melakukan terobosan hukum yang progresif dan keadilan substantif.
Namun penulis sependapat dengan dissenting opinion yang lain dari 4 Hakim Konstitusi apabila norma dalam undang-undang tersebut secara nyata bertentangan dengan nilai-nilai agama, Pancasila dan living law yang dijamin oleh konstitusi namun terganjal oleh aturan formal-legalistik maka MK perlu ber-ijtihad dengan menggunakan konstitusional moralitas (moral reading of the Constitution). Dan tambahan dari penulis yang perlu menjadi catatan pertimbangan bagi MK dalam menjatuhkan putusan perkara ini bahwa apabila berdalih bahwa pasal-pasal yang dimohonkan sedang atau telah tercantum Rancangan KUHP (RKUHP) nasional, masih belum jelas kapan akan diberlakukan. Perlu disimak bahwa RKUHP Nasional sudah mulai digodok awal tahun 1960an hingga sekarang pun tak kunjung rampung. Akan menunggu sampai kapan? Maka inilah momentum MK untuk melakukan terobosan hukum guna menegakkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.
*Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik dan Pengurus Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Jawa Timur