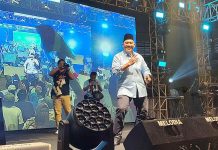Sebenarnya, jika ditelusur secara historis, orang-orang yang menjadi pejabat dan duduk di kursi kekuasaan, mula-mula baik.
Oleh Anas Ahmadi*
FIKSI adalah hasil kreasi sang pengarang. Fiksi diracik dari idea dan realita sehingga menghasilkan bahasa estetis. Salah satu hal yang kini menghangat di tanah air adalah korupsifilia (dalam konteks psikologi dimaknai sebagai penyuka korupsi [masih dalam tahapan filia; suka]) lebih tinggi lagi korupsimania (sangat suka/berlebih untuk korupsi). Tipikal koruptif tersebut masuk kategori nekrofilia sebab merusak, menggerogoti, dan mencuri dianggap sebagai sesuatu yang menyenangkan.
Fiksi dan Korupsi
Dalam konteks fiksi, misal novel, Purple Hibiscus (2003) karya Chimimanda Ngozi Adichie berbicara tentang korupsi dalam konteks agama. Novel Indonesia, misal Laskar Pelangi (2005) karya Andrea Hirata yang sempat menyinggung masalah korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang terdapat di daerah pertambangan. Dalam konteks film, misalnya Backstabbing for Beginners (2018) sebagai sebuah fiksi juga tidak lepas dari dunia fakta. Film tersebut menggambarkan kejahatan korupsi korporasi tingkat transnasional, yakni Program Minyak untuk Pangan di Irak yang terjadi 2005. Dalam dunia realitas, fakta kejahatan korupsi tingkat transnasional tersebut memang benar-benar terjadi, 2005, skandal korupsi Program Minyak untuk Pangan di Irak tersebut melibatkan PBB. Kisah korupsi dalam fiksi, baik sastra ataupun film, sebenarnya tidak lepas dari fakta yang terdapat dalam dunia realitas. Hanya saja, pengarang membalutnya dengan bahasa yang estetis dan filosofis sehingga fiksi yang mengangkat korupsi dari dunia realita tidak terkesan ‘kaku’ dan ‘kering’.
Fakta dan Korupsi
Masih hangat dibenak kita, fakta rentetan pejabat negara yang tertangkap karena korupsi. Simak saja, 41 dari 45 anggota DPRD di kota Malang yang menjadi tersangka korupsi. Sebelumnya, mantan menteri juga menjadi tersangka korupsi. Jauh sebelumnya juga, anggota DPR juga ditangkap gara-gara kasus korupsi yang kategori megakorupsi (kelak bisa jadi diganti dengan gigakorupsi sebab lebih besar).
Sebenarnya, jika ditelusur secara historis, orang-orang yang menjadi pejabat dan duduk di kursi kekuasaan, mula-mula baik. Namun, lama-kelamaan mereka mengalami pergeseran atau bahkan perubahan paradigma berpikir. Dari idealisme menuju oportunisme. Dari katakan tidak pada korupsi menjadi katakan ya pada korupsi. Perubahan tersebut jika dihubungkaitkan dengan pandangan Zimbardo (2007) disebut dengan Lucifer Effect. Intinya, orang yang baik-baik kemudian ditempatkan dengan orang yang jahat, kecenderungan akan berubah menjadi jahat. Apakah para pejabat yang duduk di kursi kekuasaan semuanya jahat. Ah, tentu tidak, saya juga tak mau gebyah uyah bahwa semua pejabat adalah penjahat. Bukan. Sebab banyak juga penjahat yang bukan pejabat. Namun, kita juga tidak boleh lupa bahwa “Penjahat Menafsirkan Kebenaran, sedangkan Pejabat Menciptakan Kebenaran.” Kembali ke bincangan semula, korupsi adalah masalah mentalitas. Jika seseorang bertipikal koruptif, semakin lama cenderung melanggengkan korupsinya. Bukankah “duwek iku legi” (uang itu manis) kata orang Jawa. Siapa yang gak suka manis. Jarang kita dengar pejabat negara ataupun penguasa yang phobia uang (takut dengan uang) atau dalam istilah psikologinya Chrometophobia (juga disebut Chrematophobia).
Berdasarkan statistik KPK, “Per 31 Mei 2018, di tahun 2018 KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 76 perkara, penyidikan 85 perkara, penuntutan 50 perkara, inkracht 47 perkara, dan eksekusi 48 perkara.” (https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan). Dengan demikian, fakta korupsi di Indonesia bisa dikategorikan dalam kategori korupsifilia sebab banyak yang suka korupsi. Kelak, kita tinggal menunggu, Indonesia bebas korupsi ataukah korupsi bebas. Semuanya tinggal menunggu waktu!
Penulis adalah dosen Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Surabaya