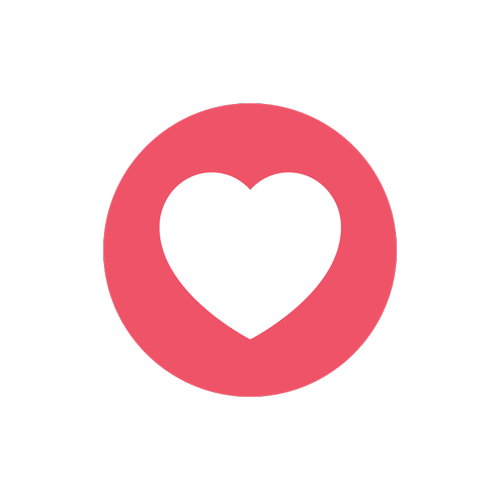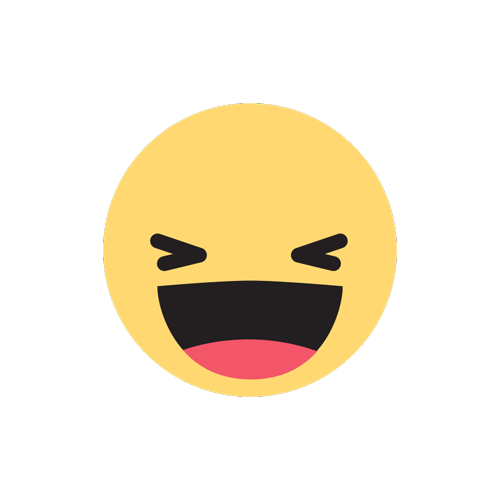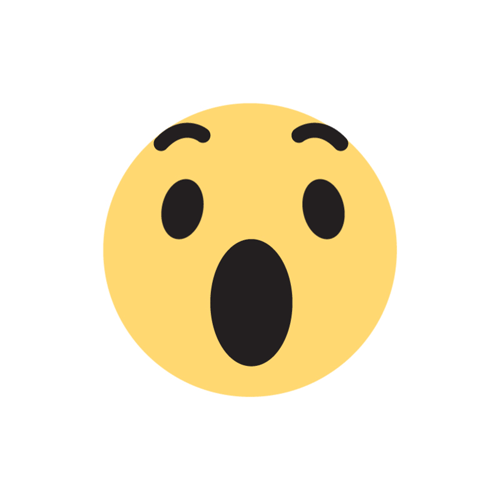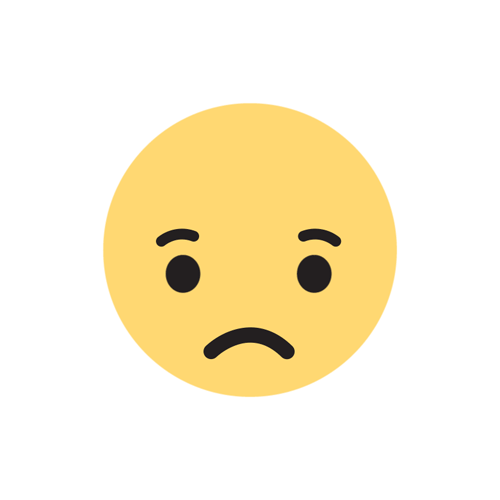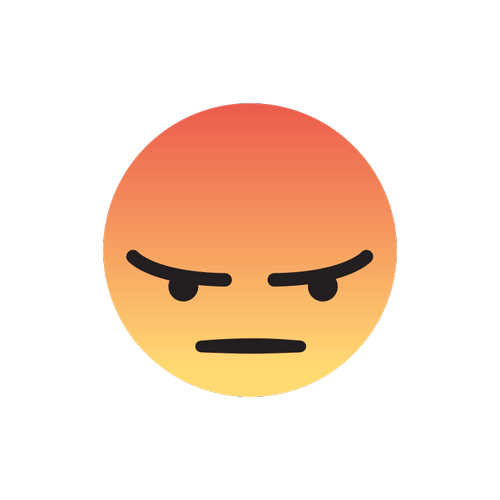“Jika negara ingin menjadikan pesantren sebagai pilar pendidikan nasional yang berkualitas dan bermartabat, maka kebijakan akreditasi tidak boleh hanya menjadi alat ukur teknokratis.”
Oleh: Moch. Fauzie Said*
ALAT penting untuk memastikan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia adalah akreditasi program studi. Sejak dibentuknya Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sebagai badan akreditasi untuk bidang keilmuan—yang mengambil alih sebagian besar peran Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)—muncul masalah baru, terutama bagi kelompok kecil dan non-elit seperti Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) dan kampus berbasis pesantren.
Pertanyaan kritis yang mengemuka adalah: Bagaimana kebijakan pembiayaan akreditasi program studi di LAM ini dapat mengintegrasikan prinsip keadilan dalam ketimpangan biaya akreditasi perguruan tinggi non-elit?
LAM didirikan dengan semangat profesionalisasi dan spesialisasi akreditasi berbasis keilmuan. Namun, salah satu kelemahan mendasar dari LAM adalah kesulitannya menetapkan biaya layanan akreditasi secara adil dan proporsional.
Besaran biaya akreditasi program studi yang ditetapkan oleh berbagai LAM. beberapa contoh biaya akreditasi prodi di berbagai LAM, seperti: LAM INFOKOM: Rp 53.000.000,00, LAMSAMA: Rp 57.500.000,00, LAM-PTKes: Rp 65.500.000,00 (untuk program studi vokasi, akademik, dan spesialis), Rp 80.000.000,00 (untuk program studi profesi), dan LAMSPAK Rp 50.000.000,00. Variasi ini tergantung pada jenjang dan kompleksitas program studi. Realitas tersebut memberi tekanan serius bagi perguruan tinggi dengan anggaran terbatas, yang pada akhirnya justru berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas antar lembaga pendidikan.
Biaya akreditasi yang tinggi berdampak ganda: tidak hanya menghambat upaya peningkatan mutu pendidikan, tetapi juga mengganggu keberlangsungan program studi itu sendiri.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020, program studi yang belum terakreditasi akan mengalami kesulitan dalam menjalankan operasional akademik, seperti penerimaan mahasiswa baru dan pengakuan ijazah lulusan. Dengan demikian, akreditasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sangat menentukan keberlangsungan lembaga pendidikan tinggi.
Menurut data Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kementerian Agama RI, lebih dari 60% PTKIS menghadapi kendala dalam pembiayaan akreditasi, terutama sejak transisi akreditasi dari BAN-PT ke LAM (Diktis, 2023). Akibatnya, banyak program studi menunda pengajuan atau perpanjangan akreditasi. Implikasinya cukup serius: menurunnya daya saing, tertutupnya kesempatan penerimaan mahasiswa baru, dan terkendalanya status legal lembaga. Menurut data dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023, jumlah total PTKIS adalah 844 dan dari keseluruhan PTKIS tersebut belum ada yang meraih akreditasi institusi unggul.
Mari kita lihat potret akreditasi dari beberapa negara, seperti Malaysia, pemerintah menanggung 100% biaya akreditasi untuk kampus Islam melalui Malaysian Qualification Agency (MQA), dimana dalam hal ini Universiti Islam Antarbangsa Malaysia (UIAM) meraih akreditas A tanpa beban finansial. Selanjutnya di Amerika Serikat, kampus kecil , Zaytuna College mendapat hibah akreditasi dari filantropi Islam (ISNA Islamic Foundation), sehingga menjadi perguruan tinggi Islam pertama di Amerika Serikat yang menerima akreditasi akademis formal.
Sejumlah pakar pendidikan dalam forum akademik mengkritik pendekatan LAM yang dinilai terlalu transaksional. “Kita tidak dapat membicarakan kualitas tanpa memprioritaskan akses. Pembiayaan akreditasi harus memiliki semangat dukungan bagi kampus-kampus kecil,” tegas Dr. Nur Kholis Setiawan, mantan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, dalam sebuah forum daring pada Maret 2022. Pernyataan ini menegaskan bahwa prinsip keadilan harus menjadi fokus utama dalam kebijakan akreditasi. Bukan hanya hasil akhir berupa nilai akreditasi yang penting, tetapi juga proses dan akses menuju penilaian tersebut harus adil.
Dalam konteks ini, pendekatan teori kebijakan deliberatif menjadi relevan sebagai kerangka analisis. Menurut Jürgen Habermas (1996), deliberasi publik merupakan cara ideal dalam merumuskan kebijakan yang adil, yakni melalui partisipasi inklusif dan pertimbangan rasional yang memperhatikan suara semua pihak. Habermas menekankan bahwa legitimasi suatu kebijakan tidak hanya terletak pada hasilnya, tetapi pada proses dialogis yang menjamin representasi semua aktor, termasuk pihak yang terpinggirkan seperti PTKIS dan kampus berbasis pesantren. Dalam bukunya Between Facts and Norms, Habermas menjelaskan bahwa “only those norms can claim to be valid that meet (or could meet) with the approval of all affected in their capacity as participants in a practical discourse” (Habermas, 1996).
Sayangnya, dalam praktik kebijakan akreditasi LAM, semangat deliberatif ini masih belum terlihat. Proses perumusan kebijakan pembiayaan tidak sepenuhnya melibatkan kampus-kampus kecil dalam diskusi atau konsultasi publik. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip deliberatif yang seharusnya menjamin keterlibatan semua pemangku kepentingan secara sejajar. Pemerintah, melalui Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi, memang telah menyatakan komitmennya terhadap peningkatan mutu pendidikan tinggi. Namun, implementasi kebijakan pembiayaan masih menunjukkan pola eksklusif, yang tidak ramah bagi institusi pendidikan non-elit.
Masalah makin kompleks ketika negara tidak menyediakan pola subsidi atau skema bantuan khusus yang berkelanjutan bagi perguruan tinggi dengan keterbatasan anggaran. Bantuan akreditasi atau hibah mutu memang tersedia, tetapi jumlahnya sangat terbatas dan proses seleksinya sangat kompetitif. Pada tahun 2023, hanya sekitar 115 program studi yang menerima bantuan dari total lebih dari 3.000 yang mengajukan permohonan (Kementerian Agama, 2023). Angka ini menunjukkan ketimpangan serius yang perlu ditinjau ulang secara sistemik.
Kritik juga datang dari para pimpinan perguruan tinggi. Seorang rektor PTKIS di Jawa Tengah mengungkapkan bahwa biaya akreditasi yang tinggi tidak diimbangi dengan layanan pendampingan dari LAM. “Kami merasa seolah-olah membayar sejumlah besar uang untuk dievaluasi, tetapi kami tidak mendapatkan diskusi atau bantuan yang proporsional,” ujarnya.
Sebagai upaya perbaikan, muncul sejumlah saran kebijakan yang dapat diadopsi. Pertama, pemerintah perlu menetapkan batas atas (ceiling) biaya akreditasi berdasarkan klasifikasi institusi. Kedua, LAM harus memiliki skema subsidi silang untuk membantu program studi dari institusi yang kurang mampu. Ketiga, perlu dibangun mekanisme pengawasan terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana LAM.
Keempat, proses perumusan kebijakan pembiayaan harus melibatkan lembaga pendidikan kecil dalam forum deliberatif, sehingga kebijakan yang dihasilkan bersifat representatif dan adil secara sosial.
Dalam perspektif teori kebijakan deliberatif, hal ini penting agar akreditasi benar-benar menjadi alat pemberdayaan, bukan alat diskriminasi. Seperti ditegaskan oleh Prof. Azyumardi Azra, “Jika pendidikan tinggi dibiarkan sepenuhnya dikendalikan oleh logika pasar, maka kita akan kehilangan pilar keadilan sosial dalam pembangunan nasional.” Pernyataan ini selaras dengan prinsip dasar deliberasi: bahwa keadilan tidak boleh dikorbankan atas nama efisiensi atau kompetisi bebas.
Akhirnya, jika negara sungguh-sungguh ingin menjadikan pesantren sebagai pilar pendidikan nasional yang berkualitas dan bermartabat, maka kebijakan akreditasi tidak boleh hanya menjadi alat ukur teknokratis. Ia harus menjadi jembatan yang menghubungkan semangat pemberdayaan, keadilan, dan kolaborasi. Seperti yang diungkapkan Gus Dur, “Pesantren adalah laboratorium manusia yang tidak boleh ditinggalkan oleh negara, maka, saatnya negara hadir bukan hanya dengan retorika, tetapi dengan regulasi yang adil dan dukungan fiskal yang nyata.”
*MOCH FAUZIE SAID adalah Asesor BAN-PT dan LAMSPAK, Dosen Magister Ilmu Politik-UB, Alumni PP Bahrul Ulum Tambakberas Jombang dan PP Miftahul Huda Gading Malang).
Referensi:
1. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis). (2023). Laporan Tahunan Direktorat PTKIS.
2. Forum Akademik Pendidikan Tinggi Islam. (2022). Diskusi Daring Nasional: Keadilan dalam Pembiayaan Akreditasi.
3. Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. MIT Press.
4. Kementerian Agama RI. (2023). Data Bantuan Akreditasi dan Hibah Mutu PTKIS.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.