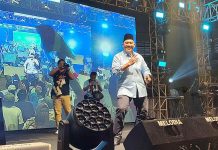Tetapi, jika Islam Nusantara ini diusung dan didakwahkan oleh tokoh-tokoh nyleneh, liberal yang sering menggembar-gemborkan ide sekularisme, maka hal ini akan menjadi pintu gerbang potensial merusak tatanan akidah dan syari’at Islam. Setuju!
Oleh: Mokhammad Kaiyis*
DUNIA umat (beragama) Islam sedang memasuki ‘lorong gelap’. Ini membuat satu sama lain sensitif, curiga dan takut. Jangankan suara keras atau gerakan kuat, bayangan sendiri kadang, membuat kita terkaget. Bagi orang latah, komentarnya bisa macam-macam, tentu, sesuai dengan kebiasaannya. Itulah (barangkali) yang kita saksikan saat muncul istilah Islam Nusantara.
Padahal, apa yang disebut dengan Islam Nusantara adalah diri kita sendiri. Islam Indonesia, Islam kita. Takut dengan Islam Nusantara, sama hal-nya takut dengan bayangan diri sendiri. Ketika kita takut dengan bayangan, maka, tidak ada yang bisa ‘menyelamatkan’ kecuali ‘menyinarinya’ dengan benar.
Islam Nusantara tidak butuh pengakuan, tetapi butuh pemahaman. Banyak orang mengira bahwa Islam Nusantara itu, me-Nusantara-kan Islam, sehingga berbeda dengan Islam Arab atau Islam Kanjeng Nabi Muhammad saw. Ada juga yang kelewat suudhon dengan menyebut Islam Nusantara itu Syi’ah, Liberal. Lebih dari itu, ada yang memberikan stigma, sesat. Tetapi, semua itu, harap maklum, karena kita berada dalam ‘lorong gelap’, butuh ‘penyinaran’ agar kita tidak lagi ketakutan dengan bayangan sendiri.
Intinya, Islam Nusantara itu hanya menjelaskan proses dan praktik keislaman kita, praktik beragama masyarakat nusantara yang tercermin dalam perilaku sosial budaya. Kita, muslim Indonesia, yang mayoritas nahdliyin, mengikuti alur moderat (tawassuth), menjaga keseimbangan (tawazun), toleran (tasamuh). Dengan demikian, Islam Nusantara itu bukan agama baru, bukan aliran baru, bukan kelompok anti Arab. Tetapi, Islam Indonesia yang memiliki ciri khas tersendiri. Bisa jadi, ciri itu, tidak terdapat di Arab Saudi.
Nah, ciri khas ini menjadi terang benderang, pembeda, ketika berhadapan dengan radikalisme agama-agama yang sangat menyedihkan. Itulah yang terjadi akhir-akhir ini. Radikalisme agama sudah melahirkan kecurigaan yang dalam, sedikit-sedikit bid’ah, musyrik, kafir, sehingga terjadilah benturan keras dengan budaya Islam Kita, Islam Nusantara, Islam Indonesia yang moderat.
Hari ini (Jumat 29/6/2018), masih viral di media sosial catatan keras KH Najih Maemoen (Gus Najih), putra KH Maemoen Zubair yang bertajuk ‘Islam Nusantara dan Konspirasi Liberal’. Intinya ada kekhawatiran dari beliau, jangan-jangan Islam Nusantara ini sengaja hadir untuk mensinkronkan Islam dengan budaya dan atau kultur Indonesia yang sangat mungkin sekali bertolak belakang dengan syariat Islam. Atau dengan bahasa lain, Islam harus patuh dan tunduk terhadap budaya Nusantara. Ujungnya umat Islam Indonesia menjadi ramah terhadap kultur yang bertentangan dengan agama, tidak lagi fanatik dengan ke-Islamannya, luntur ghiroh islamiyahnya.
Apa yang disampaikan Gus Najih ini, tidaklah salah, bahkan penting. Karena tidak sedikit budaya nusantara yang bertentangan dengan akidah maupun syariat Islam. Tetapi, tidak sedikit pula, kultur kita yang bisa berubah wajah menjadi Islami, tidak merusak akidah maupun syariat, bahkan sebaliknya justru memperkuat keimanan.
Maka, benar, apa yang disampaikan Gus Najih, jika yang mengawal Islam Nusantara adalah para ulama pesantren yang istiqamah mengajar kitab salaf, membela-memperjuangkan ajaran dan membentengi akidahnya, maka Islam Nusantara bisa menjadi estafet ajaran Islam yang benar dan lurus serta dakwah Islam yang tegas namun tetap santun dan merakyat sesuai warisan ulama-ulama Nusantara pendahulu atau wali songo.
Tetapi, jika Islam Nusantara ini diusung dan didakwahkan oleh tokoh-tokoh nyleneh, liberal yang sering menggembar-gemborkan ide sekularisme, pluralisme, maka hal ini akan menjadi pintu gerbang potensial merusak tatanan akidah dan syari’at Islam. Setuju!
Karena kenyataannya banyak orang Islam yang bicara tentang pentingnya pluralisme, toleransi, tetapi, faktanya dia sendiri tidak pernah salat, abai syariat. Walau pun ibadah salat itu berbentuk mahdhoh dan masuk wilayah privat, tetapi, ketika dia berperan sebagai pengusung Islam Nusantara, maka, hal tersebut bisa mendistorsi makna Islam Nusantara itu sendiri. Ini sisi negatifnya.
***
Mari kita simak beberapa episode bid’ah yang sering diperdebatkan. Dan masalah ini lebih diperankan oleh kelompok yang dekat dengan paham wahabi (kini masih dominan di Arab Saudi).
Pertama, ‘debat panas’ yang sudah viral di youtube tentang bid’ah antara Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) vs Khalid Basalamah. Video yang diupload Aswaja Nusantara itu sudah ditonton ratusan ribu orang, disukai seribu orang lebih.
Dalam video itu, Khalid Basalamah menegaskan, bahwa, bid’ah itu lawan sunnah. Meski amalan (bid’ah) itu baik (hasanah), tetapi kalau tidak pernah dicontohkan Nabi Muhammad, adalah terlaknat. Khalid menyebut kiai-kiai, ustadz atau siapalah namanya, yang mengerjakan pekerjaan baru yang tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad, adalah neraka.
“Nabi tidak pernah nyontohin, sahabat tidak pernah nyontohin. Ketika ditanya adakah contohnya? Mereka sendiri mengatakan tidak ada, tetapi mereka selalu alasan itu baik, kan bagus, syiar. Banyak alasan, seribu alasan. Ketika ditanya adakah perintah Alquran, adakah ayatnya, haditsnya, mereka sendiri mengakui tidak ada, kecuali hanya alasan baik. Ini sama saja mereka mengatakan, maaf ya rasulullah, saya lebih mengerti dari Anda,” begitu Khalid Basalamah.
Dari penjelasan Khalid ini, Islam menjadi cupet alias sempit. Terpaku pada contoh verbal. Andai saja Khalid benar, betapi sulit umat Islam dunia untuk mengikutinya. Inilah perbedaan substansial antara Islam Khalid Basalamah (Wahabi) dengan Islam Nusantara, Islam Indonesia, Islam Kita ketika memaknai perintah agama.
Meminjam bahasa Cak Nun, kalau kanjeng Nabi Muhammad disuruh memberi contoh seluruh kebaikan di dunia, ini bisa-bisa stres kanjeng Nabi. Nabi itu memberi contoh yang substantif saja, bukan budaya. Karena budaya masyarakat (dunia) berkembang sesuai dengan daerahnya.
Cak Nun memberi contoh yang mudah untuk kita pahami. Kanjeng Nabi kalau daharan (makan) selalu memakai tiga jari. Tetapi bukan berarti tidak boleh (haram) menggunakan sendok. Mengapa? Karena yang didahar Kanjang Nabi dengan yang kita makan, berbeda.
Rasulullah saw bisa daharan menggunakan tiga jari, karena yang didahar (dimakan) itu kurma. Bagaimana kita bisa meniru, ketika yang kita maka mie godhok?. “Lha kue arep mangan mie godhok (kamu mau kanan mie rebus red.) dengan tiga jari, ya modar kue (hancur kamu red.),” begitu Cak Nun memberi contoh.
Kedua, Cak Nun berani ‘menerabas’ wilayah yang lebih sensitif, tentang anjuran bergembira menyambut datangnya bulan ramadhan. Sering kita dengar, para dai kita menyampaikan, bahwa seorang muslim baru benar imannya, ketika bisa bergembira mendengar ramadhan datang. Sebab bulan mulia ini adalah bulan yang sangat dinanti-nantikan.
Tetapi, kenyataannya, tidak sedikit yang malah bersedih, karena harus berlapar-lapar. Cak Nun tidak mau munafik, ia bedah keaslian manusia menghadapi perintah puasa ini. “Saya mau tanya, jujur! Asline mengkel toh (aslinya benci kan red) disuruh puasa, cuma kamu tidak mau dan tidak berani melawan. Tidak ada ulama yang berani penelitian seperti ini. Aslinya kamu kan tidak suka disuruh puasa, akui saja,” demikian Cak Nun.
Tetapi, Cak Nun punya tafsir sendiri, dan ini tidak akan dilakukan oleh kiai-kiai, apalagi ulama Arab Saudi. Cak Nun kemudian memperhalus kalimat perintah tersebut. Andai saja, sekali lagi, andai saja, kemudian ada pengumuman dari Allah swt. “Wahai umat yang sudah latihan menjadi penduduk Indonesia, karena Aku mempertimbangkan kebingungan nasional yang berkepanjangan, maka, Aku bebaskan Romadhan kali ini, kalian tidak perlu berpuasa,” begitu Cak Nun. Maka, jawabnya pasti, “Yeeech..! Kita akan bilang; Hidup Tuhan, Hidup Tuhan, Hidup Tuhan! Dapurmu (mukamu red.)” kata Cak Nun.
Di sini Cak Nun membeber substansi perintah tersebut. Hati kita (diakui) berat melakukan, tetapi karena saking takutnya kepada Allah swt. maka, perintah itu tetap dikerjakan. Ini jauh lebih bagus, menurut Cak Nun. Kalau kita sudah bahagia memasuki bulan ramadhan, lalu menjalankannya, apa hebatnya? Tetapi, bagi yang tidak suka, dan tetap melaksanakannya, maka, ada kehebatan di sana.
Nah, hujjah yang semacam ini, sulit kita temui kalau tidak di Islam Nusantara.
Ada lagi hujjah yang juga sulit kita temukan pada referensi utama: Alquran dan Alhadits. Misalnya, suatu ketika, KH Mustosa Bisri (Gus Mus) menjelaskan, bahwa, Kanjeng Nabi Muhammad saw itu sangat mencintai budaya lokal. Kanjeng Nabi menggunakan jubah, karena jubah itu, budaya Arab. Maka, orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab juga berjubah.
Andai saja Kanjeng Rasulullah itu lahir di Texas, mungkin saja beliau pakai jeans. Lahir di Indonesia, pakai batik. Artinya betapa Kanjeng Nabi sangat menghargai budaya setempat. Karenanya, jika kita mengharai budaya setempat, maka, kita termasuk melakukan ittiba’ (mengikuti jejak) Nabi Muhammad yang sangat hormat dengan budaya lokal.
Penjelasan Gus Mus ini melahirkan pemahaman lebih jauh. Salat menggunakan batik, bisa jadi mendapat dua pahala. Di samping karena menutup aurat seusai syariat, juga mengukuti kanjeng nabi yang cinta budaya lokal. Berbeda dengan salat yang menggunakan jubah, hanya dapat satu pahala, yakni pahala menutup aurat, tetapi tidak cinta budaya lokal, melainkan cinta budaya Arab.
Jadi, membumikan nilai-nilai Islam Nusantara adalah membumikan Islam Kita sendiri, membumikan budaya lokal di mana substansi ajaran Islam masuk didalamnya. Dan, itu tidak menyalahi Islam yang diajarkan Kanjeng Nabi. Bukankah begitu? Wallahu’alam bishshawab. (*)
*Mokhammad Kaiyis, Pemred Duta Masyarakat. Disampaikan dalam Seminar ‘Menumbuhkembangkan Nilai-Nilai Islam Nusantara’, diadakan Formacida dan PMII PR Adab UINSA, Jumat 29 Juni 2018, di Fakultas Adab dan Humaniora (FAHUM) UIN-SA Surabaya.