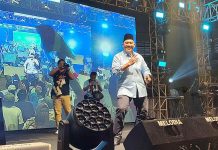Oleh Hamidulloh Ibda, M.Pd
Oleh Hamidulloh Ibda, M.Pd
MELAWAN gelombang “hoax” harus memakai kecerdasan, intelektualitas dan tabayyun. Maka dari itu, gerakan netizen Nahdlatul Ulama (NU) melawan “hoax” tidak boleh sekadar deklarasi. Namun harus diimbangi dengan dengan pengetahuan, strategi dan gerakan intelektual, tabayyun serta istikamah untuk melawan hoax. Sebab, cara mudah menghancurkan NKRI saat ini adalah dengan menyerang dan melemahkan NU dengan strategi pemberitaan negatif, miring, bahkan berbau fitnah yang ditujukan kepada sejumlah kiai dan ulama NU. Contohkan saja pemberitaan tentang Habib Luthfi bin Yahya dan KH. Said Aqil Siradj yang belakangan ini mengusik NU.
Diakui atau tidak, hampir semua masyarakat internet atau netizen saat ini masih bodoh dan belum melek literasi. Mengapa? Netizen sudah tidak lagi memikirkan akurasi, validitas dan reliabilitas berita berupa tulisan, gambar dan video yang disebar bebas di medsos. Akhirnya, berita palsu atau “hoax” yang disebar melalui medsos menimbulkan pertikaian dan memecah belah bangsa, terutama internal NU. Apalagi, saat ini antara berita hoax dan valid di medsos susah dibedakan.
Hal itu dikarenakan masyarakat kurang filter, asal membagikan, kurangnya pengetahuan tentang literasi, jurnalistik, berita, sumber berita, serta minimnya etika dalam bermedsos dan lemahnya tradisi tabayyun (klarifikasi). Apalagi, media online saat ini yang valid, blogger, media online hoax dengan media online yang resmi susah dibedakan. Padahal berita-berita di media online, kebanyakan hanya berita “bombastisme” tanpa mementingkan akurasi, nilai edukasi dan disiplin jurnalistik yang sudah diatur Undang-undang Pers. Kebanyakan media online saat ini hanya mengejar “viewer” tanpa mengutamakan fungsi dan peran pers.
Jiwa komsumtif terhadap informasi medsos baik berupa tulisan, gambar maupun video, juga menjadi penyebab rusaknya dunia jurnalistik di Indonesia. Oleh karena itu, netizen NU sebagai wadah pergerakan di internal NU, harus memiliki jiwa wartawan yang patuh pada kode etik jurnalistik dan mengutamakan kebenaran berita.
Hutan Rimba
Pengguna Facebook di Indonesia tahun 2014 mencapai 77 juta, sementara 2015 mencapai 82 dan sampai Oktober 2016 mencapai 88 juta orang. Sementara pengguna layanan chatting WhatsApp sebanyak 1 miliar pengguna dan Messenger sebanyak 1 miliar pengguna, serta Instagram sebanyak 500 juta pengguna (Kompas, 20/10/2016).
Jumlah ini sangat memukau publik dan sebenarnya berdampak positif terhadap literasi online, namun sayangnya masyarakat belum membuktikan hal itu. Di medsos, para netizen merasa paling benar, pandai dan mudah mengritik, menghakimi dan bahkan menfitnah orang dan golongan lain. Dunia medsos yang kebablasan itulah akhirnya tidak lagi menjadi “taman indah” melainkan menjadi “hutan belantara” yang hukumnya adalah hukum rimba.
Banyaknya akun abal-abal yang mengatasnamakan ulama dan kiai NU juga menjadi problem serius. Penulis sering mengamati, hal itu dipicu karena memang ada tujuan jahat untuk melemahkan NU dari medsos. Secara global, ini adalah dampak perkembangan internet tanpa kontrol dan minimnya budaya jujur.
Dalam perkembangannya, jurnalisme warga (citizen journalism) yang dulu diwadahi media massa, kini berkembang di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lainnya. Perkembangan pesat itulah saat ini menggeser peran jurnalisme yang sudah pakem dan jurnalisme profesional. Etika diabaikan, asal upload (unggah) tanpa mengindahkan dampak dan kebenaran dari berita maupun gambar dan video tersebut.
Contoh kecil saja, ketika ada kecelakaan, seorang wartawan atau jurnalis, tidak akan menayangkan hal-hal berdarah, kepala hancur, atau tangan yang patah akibat terlindas bus. Namun jurnalisme warga melalui media sosial, hal itu diekspose dan mereka justru bangga. Contoh ini hanya sebagian kecil dari kejadian yang sudah ada. Kecenderungan netizen, juga lebih suka informasi “hoax” atau palsu tanpa adanya verifikasi dan konfirmasi. Padahal sebuah berita, dalam kerja jurnalistik harus melalui tahap panjang, memenuhi unsur 5 W + 1 H (What, Who, Why, Where, When dan How) ditambah dengan verifikasi dan dikaji ulang. Dalam tradisi NU, tentu tabayyun harus diutamakan, tidak hanya berkaitan dengan kebenaran ilmu pengetahuan, namun tabayyun juga berfungsi mendeteksi kebenaran berita.
Wartawan atau jurnalis, dalam menjalankan tugasnya juga diuji melalui Uji Kompetensi Wartawan dan harus lolos Standar Kompetensi Wartawan yang ditetapkan Dewan Pers melalui organisasi profesi seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan organisasi pers lainnya (Dewan Pers, 2011). Tapi, bagaimana dengan netizen? Tentu semrawut. Asal memiliki ponsel berbasis Smartphone, mereka bisa membuat ratusan akun Facebook, Twitter, Instragram, juga aplikasi WhatsApp, Blackberry Messengger, Line, Path dan lainnya tanpa kontrol.
Padahal secara teoretis, Muhammad Irfan (2014) menjelaskan netizen berasal dari kata “internet” dan “citizen” yang berarti masyarakat internet. Ia sepadan dengan cyberjournalisme yang bertugas menjadi wartawan online. Akan tetapi, hal itu masih jarang dipahami semua netizen. Padahal, semua pemilik akun medsos, secara tidak langsung, mereka adalah “wartawan” karena mewartakan sesuatu, baik berupa tulisan, gambar, suara maupun video. Akan tetapi, mengapa mereka kebanyakan tidak punya etika dan buta literasi?
Gerakan Intelektual
Dalam konteks ini, netizen NU harus memiliki bekal “gerakan intelektual” yang berarti dibuktikan dengan melakukan klarifikasi dengan konsep akademik dan menggunakan pola kerja jurnalistik. Netizen NU yang didukung akademisi, santri, para politisi dan juga dukungan kiai dan ulama NU, harus membumikan jiwa “melek literasi” dan jurnalistik agar tidak menjadi korban dan bisa melawan hoax. Sebab, kebanyakan netizen awam dengan literasi dan jurnalistik dan akhirnya mereka terjerat UU ITE. Apalagi, tipe netizen kebanyakan hanya iseng, suka narsis dan senang dengan “viralisme” serta lebih percaya isu daripada berita.
Media sosial akan menjadi pedang yang membunuh jika netizen tidak cerdas, bijak, dan menggukan pola pikir dan metode wartawan. Sudah banyak korban medsos yang akhirnya dijebloskan ke penjara. Sebab, saat ini media massa yang sudah pakem, peran dan fungsinya makin tergeserkan dengan hadirnya medsos. Ironisnya, medsos tidak sekadar untuk ajang narsisme, namun sudah menjadi alat propaganda, alat kepentingan politik, bahkan menjadi wahana kejahatan, terorisme, bisnis terlarang, termasuk melemahkan organisasi sebesar NU.
Bermedsos, haruslah memperhatikan beberapa hal. Pertama, menggunakan jiwa dan pola kerja wartawan. Sebab, pola kerja netizen dan wartawan sangat berbeda. Wartawan memakai aturan dan bekerja profesional, sementara netizen asal-asalan tanpa kontrol. Di sinilah peran netizen NU harus berbeda dengan netizen umum yang rata-rata “kesurupan” jika sudah bergaya di medsos.
Emha Ainun Nadjib (2015: 87) menyebut semua orang memiliki pengetahuan tentang hidup. Tapi yang paling tahu hanya tiga, yaitu Tuhan, malaikat dan wartawan. Di dunia pers, wartawan mengetahui sesuatu di balik sesuatu dan bisa membedakan mana yang asli dan yang palsu. Dalam konteks ini, netizen NU perlu membangun jiwa wartawan dengan belajar tentang tulisan, berita, sumber kebenaran dan juga cara mendapatkan kebenaran yang metodologis, sistematis dan ilmiah.
Kedua, memiliki tanggung jawab dan kesadaran klarifikasi sebelum membagikan informasi. Di sinilah letak penting sebagai representasi “gerakan intelektual” sebagai budaya para santri dalam mengamalkan nilai-nilai Aswaja. Tabayyun tidak hanya dipakai dalam kegiatan bahtsul masa’il dan kegiatan kultural di internal NU. Justru tabayyun menjadi pisau tajam untuk menangkal hoax yang memang didesain untuk melemahkan NU sebagai organisasi besar di Indonesia. Apalagi, NU telah mengusung Islam Nusantara dan konsep hubbul wathon (cinta Tanah Air) secara istikamah. Hal itu bagi penjajah dan orang yang memusuhi dan merusak NKRI tentu sangat berbahaya. Maka melemahkan NU jadi tujuan mereka.
Ketiga, berpijak pada media massa pakem. Semua warga NU, selain merujuka media massa pakem yang sudah valid, bisa merujuk pada media valid milik NU seperti NU Online, dan media cetak NU yang diproduksi jelas oleh NU maupun badan otonom NU. Secara sederhana, jika ingin tahu tentang NU, tanyalah pada warga NU dan utamanya pengurus NU, bukan pada yang lain.
Keempat, patuh pada regulasi agar tidak berurusan dengan hukum, khusunya dalam menyikapi banjir informasi yang bertebaran tanpa kontrol tiap detik di medsos. Kelima, pemerintah terutama Kominfo perlu tegas dalam aturan pembuatan akun medsos. Arif (2016) mejelaskan bahwa saat ini pemerintah harus menyeleksi akun medsos dengan syarat yang valid dibuktikan dengan KTP asli. Sebab, banyaknya akun hoax juga karena tidak ada verifikasi yang akhirnya banyak muncul jutaan akun untuk kejahatan.
Tabayyun intelektual dan literasi online tidak hanya berurusan dengan tulisan, gambar, suara dan video, namun juga etika. Artinya, medsos akan bermanfaat jika digunakan untuk kebaikan dan menyebar informasi valid dan mencerahkan. Sebab, medsos hanyalah alat. Ibarat pisau, mau digunakan untuk membutuh atau memotong cabai, itu bergantung penggunanya. Jika tidak ingin terbunuh, maka gunakan medsos sebagaimana mestinya.
Meskipun tidak wartawan profesional, netizen NU juga memiliki tugas laiknya wartawan, karena mereka mewartakan sesuatu. Jika tidak demikian, apa pantas disebut netizen NU? Jadi sudah saatnya netizen NU menjadi garda depan dalam menyebarkan nilai-nilai Aswaja yang menjadi dasar Rahmatal Lilalamin!
Penulis adalah Dosen Tarbiyah STAINU Temanggung