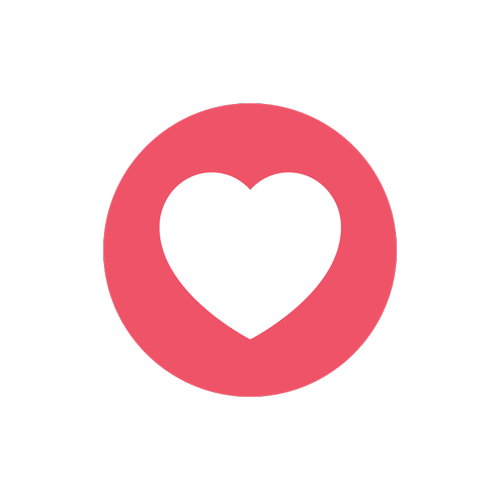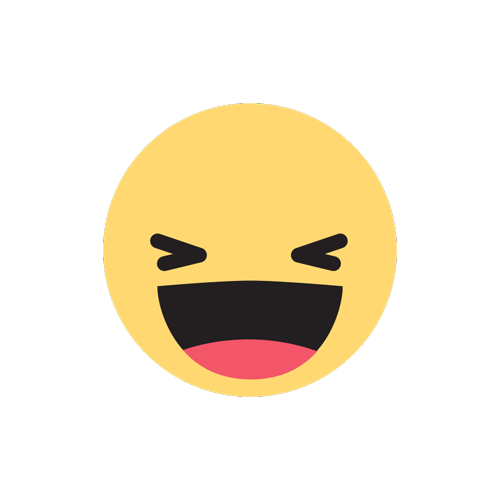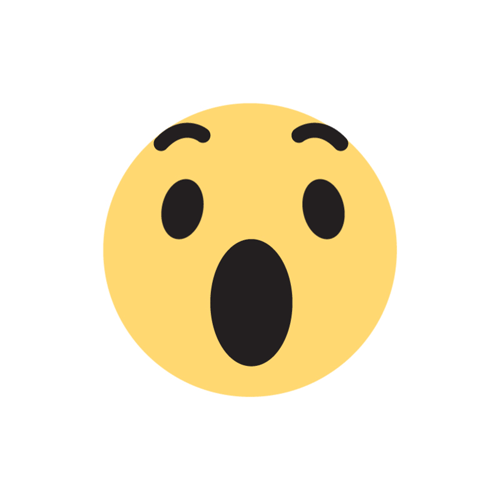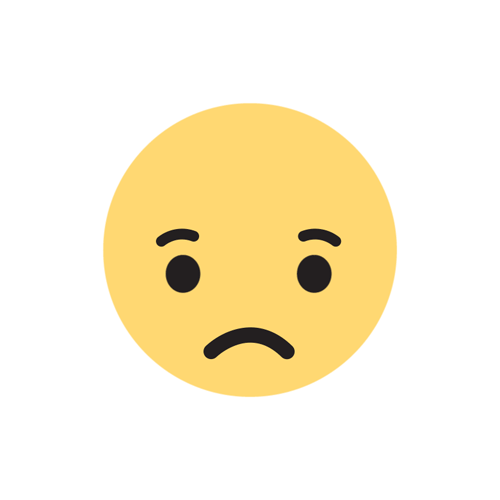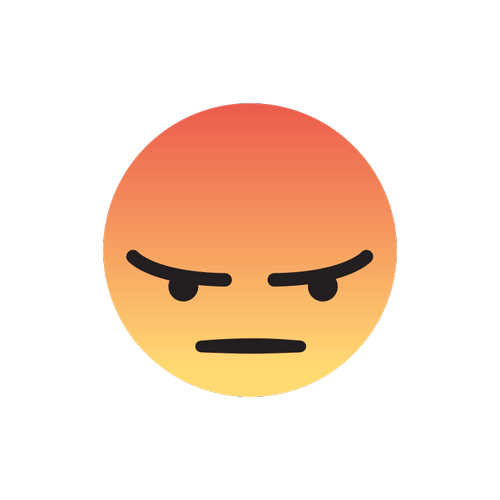Gerakan sosial di Indonesia kerap lahir sebagai respons terhadap ketidakpuasan publik atas kinerja institusi politik. Salah satu fenomena terkini adalah munculnya gerakan Gugat DPR, yang awalnya berfokus pada kritik terhadap lembaga legislatif. Namun, dinamika lapangan menunjukkan bahwa gerakan ini tidak bersifat statis. Pergeseran isu, eskalasi tuntutan, hingga potensi penunggang politik dan proksi asing, menjadikan fenomena ini menarik dikaji secara akademik.
Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif: Latar belakang lahirnya gerakan Gugat DPR, Pergeseran isu setelah tragedi kematian seorang pengemudi ojek online (ojol), Eskalasi tuntutan politik (copot Kapolri). Dugaan keterlibatan aktor domestik maupun proksi asing dalam insiden kerusuhan. Dampak sosial-politik terhadap stabilitas negara dan konsistensi gerakan sosial.
Gerakan Gugat DPR muncul dari kekecewaan masyarakat terhadap kinerja lembaga legislatif yang dinilai: Kurang transparan dalam legislasi, Sarat kepentingan oligarki, Minim akuntabilitas dalam fungsi pengawasan.
Dalam perspektif teori gerakan sosial (Tarrow, 1998; Tilly, 2004), kemunculan gerakan ini dapat dipahami sebagai collective action yang memanfaatkan political opportunity structure berupa rendahnya legitimasi DPR di mata publik.
Tragedi kematian seorang pengemudi ojol menjadi momentum yang menggeser arah gerakan. Peristiwa ini menyentuh dimensi keadilan sosial (social justice) dan kerentanan pekerja informal. Jika sebelumnya gerakan berfokus pada isu kelembagaan yang abstrak, tragedi ini menghadirkan narasi yang lebih personal, emosional, dan dekat dengan pengalaman masyarakat. Dalam kerangka teori framing (Snow & Benford, 1988), tragedi ojol berfungsi sebagai master frame baru yang lebih efektif memobilisasi dukungan publik.
Pergeseran Isu dan Eskalasi Tuntutan Politik
Setelah tragedi, gerakan tidak lagi berhenti pada isu DPR. Terjadi eskalasi tuntutan yang semakin politis, meliputi: Tuntutan Copot Kapolri, Aparat dipandang gagal mengelola situasi dan dianggap represif. Tuntutan ini mencerminkan pergeseran target dari ranah legislatif menuju ranah eksekutif, khususnya institusi keamanan. Tuntutan ke Presiden, Narasi ini merupakan bentuk radikalisasi tuntutan. Presiden dianggap bertanggung jawab atas kondisi politik, ekonomi, dan keamanan. Isu ini jelas keluar dari agenda awal, mengarah pada delegitimasi rezim.
Fenomena ini dapat dijelaskan dengan teori eskalasi konflik (Pruitt & Kim, 2004), di mana konflik yang awalnya terbatas berkembang menjadi konflik yang lebih luas akibat ketidakmampuan meredam isu sejak dini. Selain faktor domestik, terdapat indikasi keterlibatan pihak eksternal. Dalam kajian keamanan internasional, gerakan sosial dapat menjadi bagian dari proxy war—perang asimetris yang menggunakan instrumen non-militer seperti gerakan massa, media, hingga ekonomi.
Indikasi yang menguatkan dugaan adanya penunggang adalah:
• Kerusuhan terstruktur berupa bakar-bakaran dan penjarahan yang tidak sepenuhnya organik.
• Pola komunikasi digital yang menunjukkan mobilisasi opini secara cepat dan sistematis, sebagian diduga melalui akun anonim atau berbasis luar negeri.
• Kepentingan geopolitik asing yang berkaitan dengan stabilitas Indonesia sebagai negara strategis di Asia Tenggara.
Namun, perlu ditekankan bahwa bukti empiris keterlibatan asing masih bersifat indikatif. Analisis ini lebih tepat disebut sebagai hipotesis strategis yang perlu diverifikasi melalui penelitian keamanan dan intelijen.
Dampak Sosial-Politik
Dinamika gerakan ini menghasilkan sejumlah dampak penting:
1. Fragmentasi internal gerakan – terdapat kelompok yang tetap fokus pada DPR, sementara sebagian beralih ke isu sosial-ekonomi dan sebagian lain terseret ke agenda politik ekstrem.
2. Krisis legitimasi – tuntutan terhadap Kapolri dan Presiden menunjukkan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.
3. Kerentanan stabilitas nasional – kerusuhan dan penjarahan menimbulkan kerusakan sosial-ekonomi sekaligus ancaman keamanan.
4. Perpecahan opini publik – masyarakat terbelah antara melihat gerakan sebagai aspirasi murni rakyat atau sebagai agenda yang ditunggangi pihak tertentu.
Kajian ini menunjukkan bahwa gerakan Gugat DPR merupakan fenomena kompleks yang memperlihatkan:
• Fluiditas gerakan sosial: isu dapat berubah drastis akibat momentum tragedi.
• Eskalasi tuntutan politik: dari kritik legislatif, menuju tuntutan terhadap aparat, hingga presiden.
• Potensi infiltrasi: kerusuhan yang menyertai membuka kemungkinan adanya aktor domestik maupun asing yang menunggangi.
Dengan demikian, gerakan ini tidak hanya merefleksikan ketidakpuasan rakyat, tetapi juga mencerminkan rapuhnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, sekaligus membuka ruang bagi perebutan narasi oleh berbagai aktor.
Dinamika Keberlanjutan Gerakan, Peran Pemerintah, dan Jalan Keluar Sosial-Politik
Gerakan Gugat DPR dan eskalasi pasca tragedi ojol menunjukkan dua kemungkinan perkembangan:
Apakah Gerakan Berlanjut hingga September?
Analisis Lapangan: Demonstrasi sebelumnya cenderung muncul dengan pola berulang pada momen-momen politik tertentu (misalnya menjelang sidang tahunan DPR, Hari Kemerdekaan, atau momen legislasi kontroversial). Alasanya adalah Jika tuntutan massa tidak direspons secara memadai, potensi konsolidasi tetap ada, apalagi dengan adanya faktor moral shock (Jasper, 1998) akibat tragedi ojol dan tuduhan represivitas aparat. Indikator Lapangan: Munculnya seruan lanjutan di media sosial, mobilisasi lintas kota, serta dukungan dari kelompok oposisi dan jaringan mahasiswa dapat memperpanjang umur gerakan.
Apakah Gerakan Mereda sebelum September?
Analisis lapangan menunjukkan pola gerakan sosial di Indonesia seringkali bersifat sporadis dan reaktif. Jika tidak ada momentum tambahan (tragedi baru atau isu simbolik), energi massa biasanya menurun. Alsannya adalah : Kapasitas logistik, soliditas organisasi, dan konsistensi framing isu menjadi faktor penentu. Jika gerakan terlalu cepat bergeser dari isu DPR ke isu Presiden tanpa strategi, maka gerakan bisa kehilangan fokus dan dukungan publik.
Apakah Pemerintah Dapat Meredam ?
Pemerintah memiliki dua jalur utama dalam meredam eskalasi:
1). Jalur Represif: fenomena lapangan menunjukkan bahwa aparat keamanan kerap menggunakan pendekatan pengendalian massa yang keras. Namun, pola ini justru berisiko melahirkan backlash dan memperbesar simpati publik pada demonstran. Secara akademik, ini selaras dengan teori repression-mobilization nexus (Della Porta, 1995), yaitu bahwa represi justru bisa memicu perlawanan yang lebih besar.
2). Jalur Akomodatif: Pemerintah bisa menurunkan tensi dengan membuka ruang dialog, menyampaikan komitmen reformasi tertentu, atau memberikan solusi konkret bagi isu yang menyentuh rakyat langsung (regulasi perlindungan pekerja ojol atau menekan pajak serta menekan mahalnya laju belanja barang yang tinggi). Langkah presiden dengan Mengumpulkan 18 ormas Islam merupakan strategi politik meredam gejolak dengan otoritas moral. Langkah ini di pandang mampu mengurangi potensi eskalasi berbasis identitas, namun hanya bersifat sementara jika tidak dibarengi kebijakan substantif.
Dalam perspektif kajian akademik, langkah Presiden bisa dipahami sebagai politik akomodasi—memasukkan kekuatan sosial ke dalam arena negara untuk mengurangi oposisi. Namun, untuk membuat rakyat benar-benar legowo, pemerintah harus melengkapi strategi simbolik ini dengan reformasi kebijakan yang nyata dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Dengan kata lain, kemampuan pemerintah meredam gerakan sangat bergantung pada respons politik yang lebih bijak, bukan semata kekuatan represif.
Agar massa tidak terus memanas dan bisa menerima keadaan dengan lapang dada (legowo), beberapa solusi strategis dapat ditawarkan:
1. Transparansi dan Komunikasi Publik
Pemerintah perlu menyampaikan informasi yang jujur, konsisten, dan transparan terkait tragedi ojol, termasuk investigasi penyebab, tanggung jawab perusahaan aplikasi, dan langkah negara melindungi pekerja informal. Faktanya : distrust publik terhadap DPR dan pemerintah tumbuh karena komunikasi yang dianggap manipulatif. Mengembalikan kepercayaan adalah kunci.
2. Kebijakan Konkret Pro-Rakyat
Regulasi yang melindungi ojol dan pekerja gig economy bisa menjadi langkah nyata. Bantuan sosial, jaminan keselamatan kerja, atau regulasi tarif yang adil dapat mengubah tragedi menjadi momentum perbaikan kebijakan. Membuka ruang pertemuan dengan mahasiswa, serikat pekerja, dan komunitas ojol. Karena seringkali gerakan sosial di Indonesia cenderung mereda jika diberi kanal komunikasi formal.
3. Restorasi Keamanan dengan Humanisme
Aparat perlu mengedepankan pendekatan persuasif ketimbang represif. Insiden bakar-bakaran dan penjarahan harus ditindak secara hukum, tetapi tanpa menggeneralisasi semua demonstran sebagai “perusuh”. Meningkatkan literasi digital, deteksi propaganda asing, serta kerja sama siber. Kasus-kasus sebelumnya dalam beberapa kerusuhan besar, hoaks dan provokasi digital terbukti memperkeruh keadaan.
Gerakan Gugat DPR menunjukkan bagaimana sebuah isu kelembagaan bisa bergeser menjadi gerakan politik-ekonomi dengan daya resonansi lebih besar. Tragedi ojol mempercepat pergeseran itu, sementara tuntutan terhadap Kapolri dan Presiden menandai eskalasi konflik yang serius.
Apakah gerakan ini bertahan sampai September atau mereda, bergantung pada dua hal utama:
a. Apakah pemerintah merespons dengan akomodatif atau represif.
b. Apakah ada momentum baru yang menjaga konsistensi energi massa.
Agar rakyat bisa legowo, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan stabilitas politik dan keamanan. Diperlukan langkah substantif berupa kebijakan pro-rakyat, komunikasi yang jujur, dan ruang dialog inklusif. Jika tidak, gerakan ini akan menjadi preseden baru bagaimana rasa ketidakadilan sosial bisa dengan mudah meluas menjadi krisis legitimasi negara.
Penulis: Ahmad Hasan Afandi, Alumni Fisipol Univ. Brawijaya Malang.