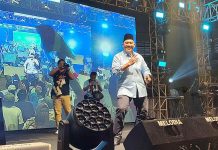JEMBER | duta.co — Serikat Pengajar HAM Indonesia (SEPAHAM) menyebut pemerintah dibawa kendali Joko Widodo bersikap hipokrit.
Penilaian itu disampaikan dalan siaran pers di Universitas Jember, Minggu (10/12/2017), dalam peluncuran buku Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme dan Relativisme di Indonesia.
“Kita meyakini masih ada situasi yang hipokrit, antara upaya pemajuan tetapi pelumpuhan di sisi lain,” terang Al Khanif, Koordinator SEPAHAM sebagaimana disampaikan kepada duta.co Minggu (10/12/2017).
Siaran pers untuk memperingati Hari HAM sedunia 2017 itu diberi judul Hipokrit Hukum dan Pelumpuhan Peran Negara dalan Melindungi dan Memenuhi HAM.
Disebutkan, ada empat situasi yang dinilai bertahan dalam politik pelemahan HAM. Pertama, kebuntuan hukum dan politik dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.
Stigmatisasi (komunisme) dan menguatnya eskalasi kekerasan dalam bentuk teror masyarakat sipil yang dibiarkan negara, memperlihatkan reproduksi politik kekerasan sipil atas warga sipil lainnya.
Sementara di sisi lain, kebijakan hukum dan politik hukum yang ada dalam konteks tahun ketiga pemerintahan Jokowi-JK, sama sekali tak menunjukkan tanda-tanda serius mengungkap dan menyelesaikan kasus.
“Akibatnya, pembiaran dan bahkan tindakan rezim hari ini menguatkan sirkuit impunitas dalam penyelesaiannya,” tegasnya.
Kedua, ekses politik berkembang menjadi tekanan kebebasan warga atas nama NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) ataupun pemaksaan dan kekerasan atas nama agama tertentu dalam mengintervensi penegakan hukum.
“Celakanya, kami mencatat keterlibatan sejumlah penyelenggara negara, institusi militer, yang menekan kebebasan akademik, kebebasan berpendapat dan berserikat atau berkumpul. Kasus maraknya persekusi, pembubaran diskusi di kampus, dan aktifitas ilmiah, memperlihatkan situasi ini,” jelas Al Khanif.
Ketiga, bekerjanya kekuatan oligarki yang ditopang dengan kebijakan hukum negara disertai penundukan kaum cendekia kampus yang menjadi pelumasnya. Ini melahirkan penghancuran sumberdaya alam oleh korporasi dan penyingkiran komunitas masyarakat adat dan petani secara luas.
Kasus eksploitasi tambang, perampasan tanah dan ekspansi perkebunan kelapa sawit, menunjukkan bekerjanya kekuatan itu.
Hukum, terutama hukum administrasi dan mekanisme peradilan TUN, melegitimasi secara efektif digunakan untuk menangguk keuntungan bagi kekuatan oligarki tersebut, sementara jajaran pemerintahan Jokowi-JK seakan lumpuh dalam realitas politik tersebut.
Ia menyontohkan kasus Kendeng (melawan industri tambang), kasus Kulon Progo (infrastruktur bandara), kasus Tumpang Pitu (tambang emas Banyuwangi).
“Hukum, pada akhirnya, berkhidmat semata pada kekuatan ekonomi politik modal besar, dan secara langsung menyingkirkan keadilan eko-sosial,” tambahnya.
Keempat, tren ancaman terhadap kebebasan ekspresi, berkumpul dan berserikat kembali menguat, apalagi dengan lahirnya Perppu Ormas. “Situasi ini diperjelas dengan pembubaran HTI, sementara ormas-ormas radikal dan kerap melakukan kekerasan justru dibiarkan atau cenderung “dirawat” negara,” demikian Al Khanif.
Hipokrit perlakuan negara atas situasi dan pemaknaan ‘radikalisme’ yang tidak ditindaklajuti dengan kejelasan dan ketegasan hukum dan penegakannya, justru menyuburkan benih diskriminasi dan radikalisme itu sendiri.
Kriminalisasi terhadap warga sipil demikian mudah terjadi ketika ekspres media sosial, dengan kritik satir, justru mendapat represi hukum.
Di tengah situasi demikian, ada pula perkembangan positif dalam konteks pemajuan HAM untuk menjadi pijakan politik HAM masa mendatang. Pertama, terpilihnya komisioner baru dan integritas Komnas HAM menjadi harapan baru untuk perubahan strategi mengembangkan kebijakan dan mengawal politik HAM yang lebih baik.
Tentu, kuncinya adalah mengembangkan strategi bersama dan menguatkan peran masyarakat sipil serta keberanian mendorong terobosan hukum dalam melawan impunitas.
Kedua, adanya upaya akademisi mengembangkan kebebasan akademik, kampus dan komunitas akademiknya.
Ketiga, perkembangan politik hukum atas pengakuan aliran kepercayaan di Indonesia. Penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk enam agama yang telah diakui pemerintah dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan .
Ketiga, perkembangan tersebut menjadi penanda baik dalam terus mendorong politik hukum HAM di Indonesia. “Tentunya, kami percaya HAM akan menjadi lebih dijamin bukan atas kedermawanan politik negara, melainkan upaya kecerdasan kolektif yang memberdayakan politik kewargaan untuk perubahan lebih baik,” tutup Al Khanif. (aif)