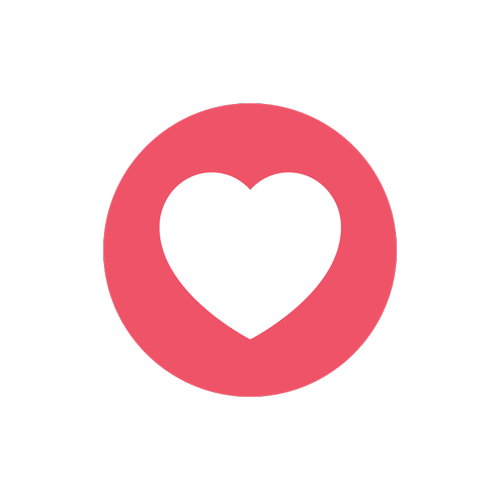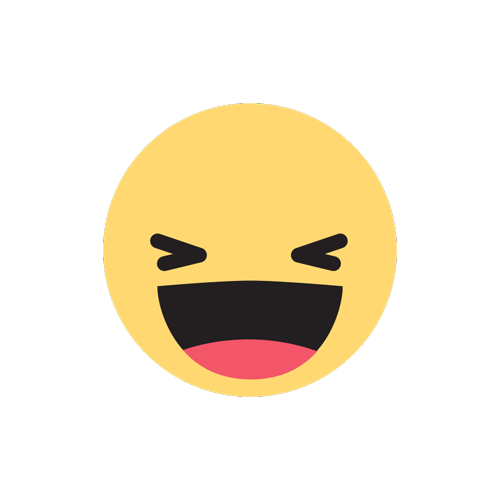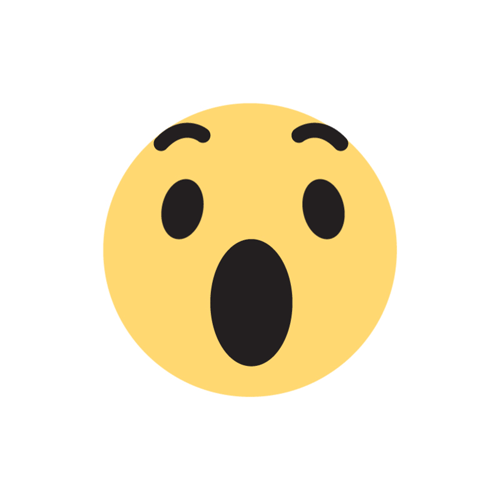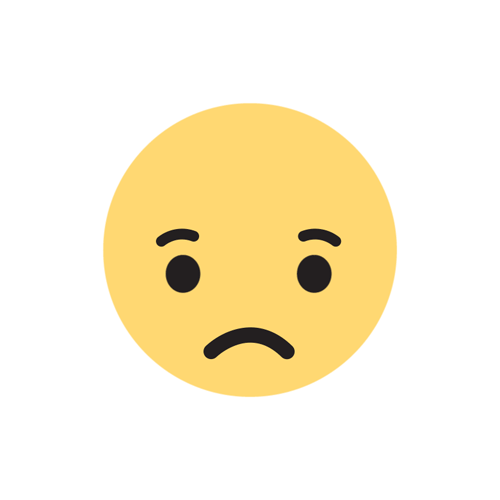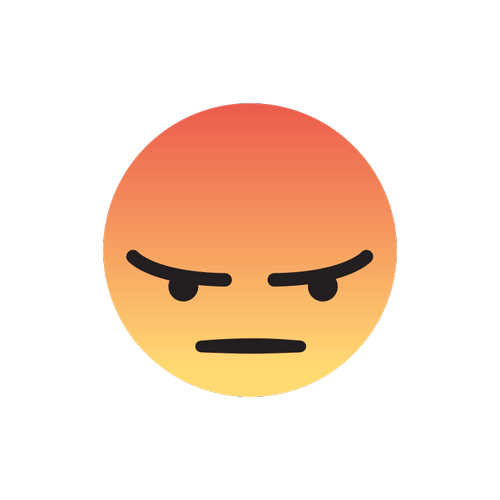“Di sisi lain, kita tahu istilah “ibu kota politik” ini terdengar asing. Di dunia, yang dikenal itu political center, seat of government, atau capital city.”
Catatan*Cak AT*
PELAN-PELAN tapi halus, begitulah cara Presiden Prabowo Subianto memainkan piano peninggalan Jokowi. Tidak dengan gebrakan keras, tidak pula dengan bantingan meja, melainkan dengan satu gesekan lembut: mengganti singkatan.
Ibu Kota Nusantara (IKN), yang semula digadang-gadang sebagai ibu kota negara, kini bermetamorfosis menjadi “Ibu Kota Politik” (IKP), diresmikan dalam sebuah SK Presiden. Persis seperti mengubah resep rendang jadi semur hanya dengan menukar santan dengan kecap.
Saya membayangkan para birokrat tersenyum sambil mengangguk-angguk penuh kepura-puraan: “Wah, cerdas sekali, Pak Presiden. Tidak frontal, tapi mak jleb.” Padahal di hati kecil mereka mungkin bertanya: “Ibu kota politik itu apa, ya?”
Kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris, barangkali Political Capital. Masalahnya, political capital dalam literatur ilmu politik itu artinya “modal politik”, bukan kota. Lah, jadi kita sedang membangun modal atau membangun kota?
Dalam teori Pierre Bourdieu, political capital dipahami sebagai salah satu bentuk capital selain ekonomi, sosial, dan kultural: sebuah akumulasi legitimasi, reputasi, serta posisi simbolik yang memungkinkan aktor politik memengaruhi struktur kekuasaan.
James Coleman menekankan bahwa modal politik adalah sumber daya relasional, diperoleh melalui jaringan sosial dan kepercayaan, yang bisa ditukar dengan kekuasaan atau kebijakan.
Jadi jelas: dalam ilmu politik, political capital adalah abstraksi, bukan topografi. Ia tak pernah dimaknai sebagai wilayah geografis dengan lahan 800 hektare dan jaringan jalan 0,74 indeks aksesibilitas.
Tapi sudahlah. Mari kita coba bayangkan skenario absurd ini. Jika IKN betul-betul jadi “ibu kota politik”, apakah semua kantor partai politik akan pindah ke sana?
Apakah gedung DPR/MPR juga bakal hijrah, sehingga mahasiswa Jakarta nanti hanya bisa demo lewat Zoom dengan background virtual “Gedung DPR Nusantara”? Atau barangkali akan ada “koridor demonstrasi digital” berlisensi, lengkap dengan aplikasi DemoGo yang bisa diunduh di PlayStore.
Di sisi lain, kita tahu istilah “ibu kota politik” ini terdengar asing. Di dunia, yang dikenal itu political center, seat of government, atau capital city.
Tak pernah ada yang secara resmi menyebut “political capital city.” Kalau pun ada, mungkin hanya di buku fiksi distopia, di mana para politisi membangun Disneyland khusus untuk persekongkolan politik, lengkap dengan wahana Roller Coaster of Democracy.
Namun, mari kita jangan buru-buru menertawakan. Mungkin ada logika halus yang hendak dibangun Prabowo: Jakarta biarlah jadi pusat ekonomi, pusat dagang, pusat mall, pusat gosip selebriti.
Sementara Penajam Paser Utara dijadikan pusat politik —tempat para politisi, pejabat ASN, sekitar 1.700 sampai 4.100 jiwa, bermigrasi dengan rapi.
Itulah politik kita: jumlah manusia yang dipindahkan bisa dihitung dengan kalkulator, sementara jumlah drama politik yang ikut pindah tak bisa diukur bahkan dengan algoritma ChatGPT sekalipun.
Kita patut mengapresiasi Prabowo. Ia tidak merusak bangunan Jokowi, hanya mengganti nama pintu gerbangnya. Dari luar tampak sama, di dalamnya berubah fungsi.
IKN versi Jokowi adalah rumah megah untuk seluruh republik, IKN versi Prabowo adalah rumah kontrakan untuk para politisi. Tidak frontal, tapi halus. Seperti orang Jawa yang menolak lamaran jodoh dengan kalimat: “Wah, cocok sih, tapi mungkin rezekinya beda jalur.”
Meski demikian, akal sehat kita masih sempat nyengir. Apa jadinya kalau generasi mendatang membaca buku sejarah dan menemukan kalimat: “Pada 2028, Indonesia memindahkan ibu kotanya, bukan sebagai national capital, melainkan sebagai political capital.”
Mereka pasti mengira kita sedang bercanda. Mirip ketika membaca sejarah Majapahit yang runtuh gara-gara perebutan peti emas, tapi ternyata yang diperebutkan hanya kursi parlemen.
Akhirnya, kita belajar satu hal: politik Indonesia memang piawai mengubah tragedi menjadi komedi, dan sebaliknya. Yang seharusnya jadi agenda besar pembangunan negara, berubah jadi permainan semantik yang bikin rakyat tersenyum pahit.
Tapi jangan salah, dalam humor itu tersimpan pelajaran. Bahwa pembangunan bukan hanya soal beton dan gedung, melainkan juga soal kata-kata.
Sebab, di republik ini, satu kata bisa mengubah nasib sejarah: dari “negara” menjadi “politik.” Dan itulah tragedi yang, untungnya, selalu bisa kita tertawakan.
*Cak AT adalah Ahmadie Thaha. Pengasuh Ma’had Tadabbur al-Qur’an.