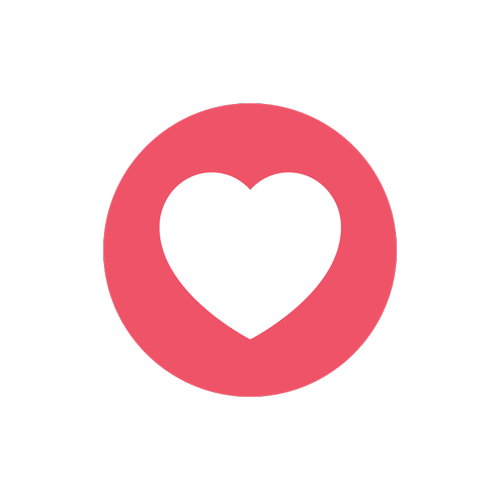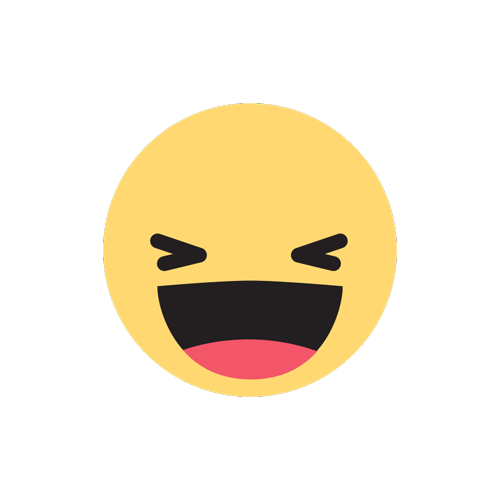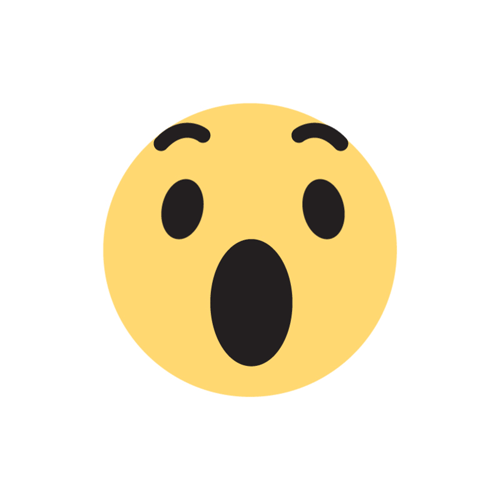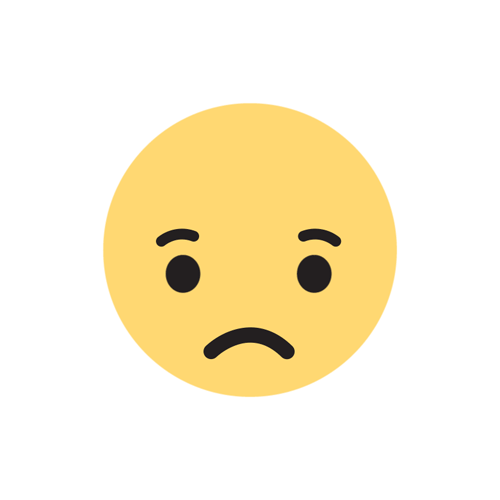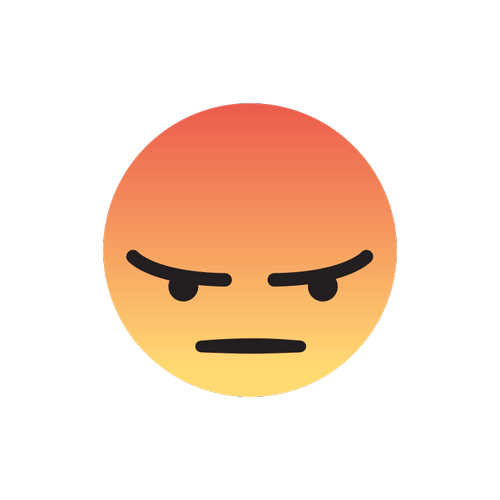“Bayangkan jika skema ini berjalan mulus. Anak Madrasah Technomicro itu tidak lagi menunggu donatur yang tak kunjung datang.”
Catatan Cak AT*
KONON, di sebuah ruang kelas Madrasah Technomicro yang lebih mirip laboratorium sains ketimbang kelas biasa hidup seorang siswa yang dengan tekun meneliti akhirnya menemukan bahan untuk bikin jaket antipeluru. Iya, betul. Anak sekolahan. Jaket antipeluru.
Kita mungkin dulu menemukan seragam yang kancingnya hilang saja sudah dianggap pencapaian rumah tangga. Lha, anak ini bersama timnya meneliti partikel dan kimia superkuat, di ruangan lengkap dengan kabel yang menjuntai seperti akar bakau dan papan tulis penuh rumus yang tampak seperti mantra.
Lha iya, menemukan teknologi pakaian antipeluru, yang kalau di luar negeri ditemukannya, CNN pasti sudah antre wawancara. Saking canggihnya, temuannya didaftarkan sebagai kekayaan intelektual. Dipatenkan. Diberi segel sah bahwa “Ini ciptaan anak Indonesia, bukan impor kiloan dari luar negeri.”
Sertifikatnya pun mengkilap, tebal, wibawa full level. Begitu berharganya sampai pihak madrasah menyimpannya di dasar laci lemari, dibungkus plastik, dijaga dari kelembaban. Dan, Alhamdulillah, tidak — atau setidaknya belum — diseruduk tikus-tikus yang biasanya hobi menggigit barang bersejarah.
Namun, seperti banyak kisah hebat negeri ini, muncul satu pertanyaan besar nan klasik: setelah dipatenkan, lalu mau diapakan? Mau diproduksi massal? Modalnya mana. Mau diajukan pendanaan? Formulirnya tebal, izinnya seperti tumpukan kitab kuning yang kalau dijajar bisa bikin rak ambruk.
Jadilah, pakaian antipeluru paling menjanjikan abad ini parkir cantik sebagai secarik sertifikat yang tak punya kaki untuk berjalan ke pasar industri. Inovasinya melompat, administrasinya tertinggal, dan modalnya menyusut seperti es krim yang dilupakan di terik matahari Depok.
Walakin. Akan tetapi, kini ada seberkas cahaya di ujung terowongan. Bukan lampu kereta. Lampu harapan. Pemerintah —entah karena ilham atau wangsit dari mana, atau mungkin akhirnya sadar bahwa masa depan ekonomi tergantung ide dan kreativitas— meresmikan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.
Bukan dongeng. Resmi, tercatat, dibacakan dalam rapat, dibubuhi persetujuan dua menteri: Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan dan Airlangga Hartarto sebagai Menkoperekonomian. Keduanya sepakat mengucurkan Rp10 triliun khusus untuk KI lewat skema KUR.
Dan dengan itu, kita patut bertepuk tangan: Indonesia melesat ke posisi negara ke-15 yang menyediakan kredit berbasis ide, bukan hanya bangunan, tanah, atau ternak kambing jantan. Mari kita rayakan dengan jutaan syukur alhamdulillah, pemerintah akhirnya tersadar juga.
Untuk pertama kalinya, sertifikat kekayaan intelektual (KI) bukan sekadar dekorasi rapat, bukan pajangan di dinding birokrasi, bukan pula barang keramat yang hanya difoto saat wisuda inovasi. Ia berubah fungsi menjadi agunan. Bisa dinilai. Bisa dinominalkan. Bahkan bisa menjadi modal.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengibarkan bendera: jaminannya ada, hukum siap, pasar menunggu —yang kurang cuma satu: dananya. Nah, dengan KUR berbasis KI berbunga rendah, kekurangan itu hendak ditambal. Bank nantinya akan menaksir nilai KI melalui valuator yang sedang dilatih khusus.
Nilai KI akan dihitung angkanya oleh valuator alias juru nilai, lalu dicairkan dana yang sesuai. Maksudnya, jika diuangkan, KI itu bernilai berapa rupiah. Maka kini, tidak lagi ada alasan bahwa inovasi mandeg karena pemiliknya hanya bersenjatakan ide cemerlang tanpa modal sepeser pun.
Di negeri tetangga Singapura, Jepang, atau Korea Selatan, kebijakan seperti ini sudah membuat startup raksasa tumbuh seperti tauge setelah hujan. Negara-negara itu mengubah KI menjadi bahan bakar ekonomi baru. Dan kini Indonesia, dengan 26 juta pekerja kreatif serta 63 juta UMKM, seperti baru saja menyalakan mesin roketnya sendiri.
Bayangkan jika skema ini berjalan mulus. Anak Madrasah Technomicro itu tidak lagi menunggu donatur yang tak kunjung datang, tidak lagi memelototi laci untuk memastikan sertifikat KI tidak menjadi sarang cicak. Ia bisa mengajukan KUR berbasis KI, memproduksi jaket antipelurunya.
Madrasah, sekolah, pesantren, atau perguruan tinggi bisa bekerja sama dengan industri lokal. Siapa tahu, dalam beberapa tahun kita melihat merek “Technomicro Armor” dipakai pasukan perdamaian RI di misi internasional. Atau dipakai satpam komplek juga boleh, yang penting manfaatnya nyata.
Namun seperti semua cerita bangsa kita, harapan bukan berarti bebas dari risiko. Membuka pintu pembiayaan KI sama dengan membuka pintu keramaian baru: bagaimana memastikan valuator bekerja objektif? Berapa lama proses pencairan?
Siapa pula yang bisa menjamin tidak ada inovator kecil yang justru terpinggirkan karena prosedur di tengah jalan berubah seperti sinetron mengejar rating? Tapi setidaknya, arah anginnya benar. KI mulai naik pangkat: dari warga kelas pinggiran ekonomi menjadi instrumen strategis negara.
Dan di titik ini, kita belajar sesuatu dari jaket antipeluru yang lama terpenjara di dasar laci itu. Bahwa kadang, ide paling cemerlang pun bisa kehilangan sayap jika negara tidak menyediakan angin. Hari ini, angin itu mulai bertiup. Perlahan, tapi terasa.
Semoga anak-anak muda penemu inovasi tidak lagi menua karena menunggu. Semoga sertifikat KI tidak lagi menjadi fosil administratif. Dan semoga kita sadar bahwa masa depan bangsa tidak dibangun oleh beton semata, tetapi oleh gagasan yang diwariskan.
Sebab, terkadang laci yang lama tertutup itu menyimpan masa depan yang sejatinya sudah siap terbang—asal ada yang membuka dan berkata: “Ayo, waktumu sudah tiba.”
*Cak AT adalah Ahmadie Thaha. Pengasuh
Ma’had Tadabbur al-Qur’an.