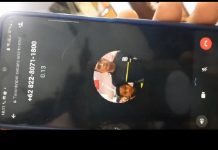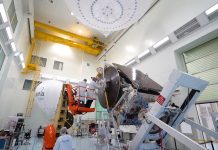Oleh: Suparto Wijoyo*
SURABAYA terlihat berbedak tebal dengan taman-taman yang sumringah berbunga-bunga. Saya tentu berbangga dengan raihan piala dengan tetap mau mendengar rintih lirih bahwa dalam “rahim kota” yang tampak kinclong ini, ternyata membuncah masalah yang tersembunyi di balik panggung kehidupannya. Semua orang menyaksikan gebyar pembangunan Kota Pahlawan yang begitu meriah digeber. Sayang akhir-akhir ini “sang sutradara” menampilkan lakon ontran-ontran penghancuran latar peradaban. Gedung-gedung tinggi dijulangkan dan “Rumah Radio Bung Tomo di Jalan Mawar 10 yang menggerakkan 10 November 1945” diratakan.
Bangunan kolonialis disanjung penuh hormat dengan regulasi cagar budaya sebagai formulasi atas imaji “keluhuran penjajahan”. Terbidik bahwa habitat para pemanggul heroisme perjuangan tidak perlu disemat menjadi rencana yang perlu dikenang. Penghancuran rumah pergerakan itu adalah penistaan sejarah dan perobohan masjid (sebelum jelas arahnya) merupakan keliaran kebijakan yang menghina jamaahnya. Agenda meluluhlantakkan “areal DKS” adalah manifes “perang perkotaan” yang brutal. Kekuasaan itu secara politik memang cenderung manipulasi, maka seni hadir sebagai wahana berkontemplasi. Tata letak dan kemaujudan kata “dewan” untuk parlemen maupun bagi pegiat kesenian adalah cermin harmoni membangun kota yang bernilai.
Ingatan di kota ini kentara dipoles lagi dengan “proyek trem” yang pernah ada untuk disuarakan agar para “kolonialis” bernyanyi merdu: inilah metropolitan yang menghamba keagungan harta pusaka sang penjajah. Ungkapan ini saya pilih sekadar memberi sapa terhadap tindakan “kekerasan kepada Rumah Radio Perjuangan” yang disertai dengan sikap “memberhalakan bangunan tinggalan kaum penjajah”, sambil melihat sebelah mata fungsi masjid di Balai Pemuda. Lagi pula, kalaulah kota ini memang gandrung sebutan water front city, mengapa sibuk “menutup sungai” dan membuka kembali “luka historia” atas nama angkutan massal “trem peninggalan penghisab kekayaan bangsa”? Imperialisme dimodernisasi dengan menepikan “bangunan yang dipercaya hanya menyedot anggaran” dan tidak dapat menghasilkan profit pendapatan asli daerah. Padahal masjid dan “padepokan kesenian” itu adalah penghasil “devisa akhlak”, sehingga Surabaya sampai saat ini terpotret dipenuhi arek-arek yang solider, setia kawan, dan tali duk tali layangan (berani berkorban).
Bisakah Surabaya ditarik kembali ke ornamen “kota yang berakhlak”, bukan kumpulan komunitas yang jor-joran laku konsumtif setarikan nafas gemerlapnya lampu jalan. Jargon Sparkling Surabaya menawarkan mimpi seperti dirumuskan Frans Kafka (1883-1924) sebagai realitas yang belum mampu dijangkau konsepsi. Sinar terang jalanan dan kerlap-kerlip “bola elektrik” yang memantul dari gedung-gedung tinggi seolah berbisik menyapa penghuni Surabaya: “dari sinilah masa depanmu akan diraih”.
Oh… oh.. Pembangunan digencarkan dengan aparteman dan hotel serta jalan lingkar yang menyisir setiap jengkal. Konfigurasi taman-taman indah dan tersusunnya beton-beton angkuh yang tersebar semakin meneguhkan supremasi Surabaya yang merepresentasikan “living the global city” sebagaimana diintrodusir John Eade (1997). Itulah yang terbaca khalayak sebagai ruang tinggal yang memenuhi persyaratan berkelas internasional, our urban future dalam telisik The Worldwatch Institute (2007).
Capaian “lembar penghargaan” merupakan puja-puji yang tetap harus dieja lebih cermat. Bukankah publik Surabaya beberapa hari yang lalu tersentak menyaksikan dahsyatnya banjir seiring hujan yang turun Jumat, 24 November 2017. Seluas 70% wilayahnya terendam dalam kisaran yang sangat mendukacitakan. Bahasa yang paling toleransi pun diusung bahwa ini bukan banjir melainkan genangan meski setinggi “paha orang dewasa”.
Banjir acap datang menerjang saat musim penghujan. Hal ini lazim di banyak wilayah Indonesia dengan dampak merenggut nyawa, kerumun warga terisolasi, dan hancurnya tatanan ekologis. Menyalahkan siklon tropis Cempaka dan Dahlia serta hujan adalah tindakan misdiagnonis. Logika yang naif adalah memutar wewenang agar otoritas pemerintahan terbebas dari tanggung jawab dengan mencatut “tingginya curah hujan serta tumpukan sampah”. Bangsa ini sudah berusia lanjut, sehingga sangat paham dengan siklus cuaca. Pendirian hotel, apartemen, kondominium, ritel-ritel, dan “hutan beton” yang kian masif di Surabaya sejatinya tidak pernah dibayangkan sebelumnya.
Dari “banjir genangan” tersebut dapat diketahui adanya indikasi lunturnya visi ekologi. Urusan taman memang sudah jagonya tetapi itu bukan satu-satunya. Penghilangan “RTH Satelit” dan deforestasi bakau melalui “izin properti” yang merangsek dari arah Surabaya Timur memantik gelegak bahwa institusi birokrasi gagap menghadirkan karakter kotanya. Genangan yang “melumpuhkan sebagian besar teritorial” Surabaya itu tampak jelas sebagai dampak terlekat dari rusaknya ekosistem perkotaan. Kenapa kanal-kanal dan drainase perkotaan mampet? Kenapa “parade beton” digelar tanpa henti? Terhadap hal ini saatnya rakyat mewaspadai hadirnya penyamun politik perkotaan. Negara memikul tanggung jawab hukum dan politik lingkungan atas terjadinya peristiwa “banjir”. Sudah memadaikah apa yang telah mereka persembahkan untuk perlindungan kota selain “iklan penghargaan”?
Saya percaya bahwa penguasa senantiasa berikhtiar. Hujan deras bukanlah alibi utama atas terjadinya banjir tetapi wujud tersumbatnya gorong-gorong dan kanal-kanal kota yang mampu menghantar “persemayaman” air ke lautan. Kali-kali yang “ditidurkan” melalui proyek “selimut beton” adalah contoh paling telanjang “penghancuran ekosistem sungai” di urat nadi Surabaya. Akhirnya, tata lingkungan memang telah dinormakan untuk mengatasi genangan yang mengoyak hayat rakyat. Sebuah “karapan kota” akan penuh kejanggalan apabila tidak ada “sorotan kritis-konstruktif” atasnya, termasuk oleh parlemen kota terhadap peristiwa genangan yang kemarin “bersilaturahmi”. Kita tidak hendak bersaksi: “Surabaya tak seindah Sparklingnya”.
*Akademisi Hukum Perencanaan Kota, dan Koordinator Magister Sains Hukum dan PembangunanSekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga