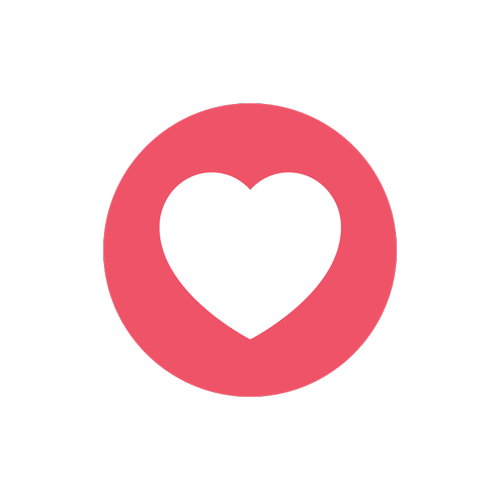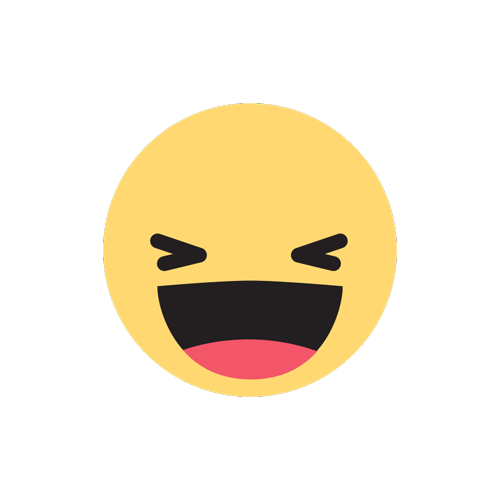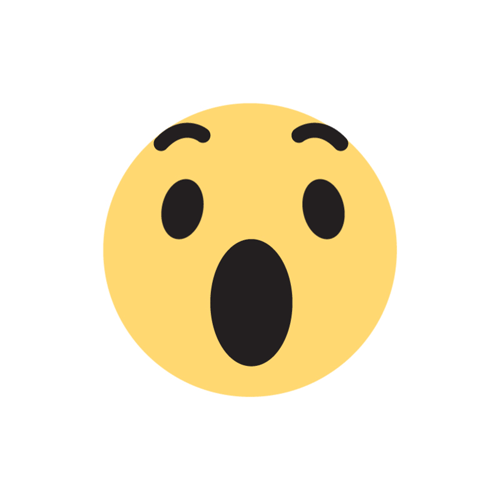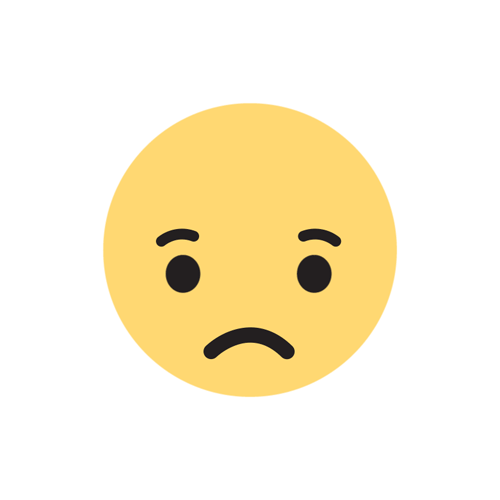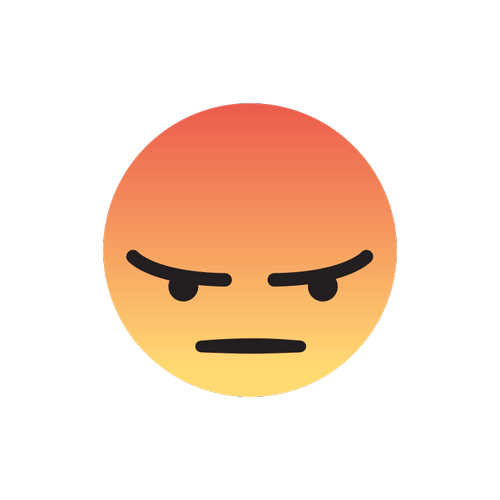Dunia politik memang menggoda. Kekuasaan sering kali dianggap jalan pintas untuk meraih pengaruh, harta, dan kehormatan. Sebelum fenomena aktris dan selebritas ramai masuk ke dunia politik pada awal 2000-an, kita sebenarnya sudah lebih dulu menyaksikan fenomena lain. Munculnya para Gus, anak-anak kiai pesantren, di panggung politik nasional maupun daerah.
Ambisi itu tak tanggung-tanggung. Ada yang mengejar kursi legislatif, bupati, wakil bupati, gubernur, bahkan presiden. Namun, dalam panggung politik yang ditopang rakyat dengan kualitas SDM dan ekonomi yang masih berkembang, hanya ada dua alat utama untuk meraih kursi kekuasaan; uang dan popularitas.
Uang menjelma praktik money politics yang mudah membeli suara. Popularitas bisa lahir dari kerja keras pribadi, tetapi tak sedikit hanya menumpang pada nama besar orang tua yang memiliki pondok pesantren. Karisma warisan masa lalu pesantren sebagai simbol perlawanan di era penjajahan masih menyala, namun kerap dijadikan tiket politik instan.
Di sinilah persoalannya. Budaya santri yang menuntut tawaduk pada kiai kerap disalahartikan. Tawaduk berubah jadi legitimasi instan: cukup berstatus sebagai Gus, maka dianggap pantas duduk di kursi kekuasaan. Padahal, tidak sedikit dari mereka minim kapasitas dalam birokrasi maupun strategi politik sebagai alat perjuangan.
Akibatnya, akar perjuangan moral pesantren kian terlepas dari tanahnya. Dari pewaris spiritual, sebagian Gus bergeser menjadi pewaris politik. Dari pengawal nilai keikhlasan, berubah menjadi pengelola ambisi. Dari simbol kepemimpinan moral, berganti menjadi pemain panggung elektoral.
Fenomena ini nyata terlihat. Ada Gus yang berhasil duduk di kursi bupati dengan bekal nama besar pesantren, namun gagal membangun birokrasi yang bersih. Alih-alih menyejahterakan rakyat, ia justru tersandung kasus korupsi. Ada pula yang meraih kursi legislatif, tetapi kemudian lebih sering tampil di televisi ketimbang turun mendengar suara rakyat di dapilnya. Bahkan, ada yang bermimpi jadi presiden, namun terhenti di tengah jalan karena visi politiknya dangkal, hanya mengandalkan nostalgia masa lalu orang tuanya.
Namun, tentu tidak semua Gus kehilangan arah. Ada segelintir yang mampu membuktikan diri mereka belajar sungguh-sungguh, memahami tata kelola pemerintahan, dan menempatkan politik sebagai jalan perjuangan, bukan pelarian ambisi. Mereka inilah pengecualian yang seharusnya menjadi teladan bahwa darah pesantren bisa bersinergi dengan kapasitas intelektual dan integritas moral.
Tetapi jumlahnya masih kecil. Yang lebih banyak justru terjebak dalam pragmatisme politik. Akibatnya, rakyat khususnya kalangan santri terjebak dalam romantisme simbolik. Mereka memilih bukan karena visi, bukan karena program, tapi semata karena nama besar keluarga pesantren.
Jika pesantren dulu adalah sumur moral, kini ada risiko ia dikerdilkan menjadi pabrik politisi. Inilah yang dimaksud banyak Gus yang kehilangan akar.
Refleksi: Kembali ke Jalan Pesantren
Kini, saatnya pesantren dan santri membuka mata. Tawaduk bukan berarti tunduk buta, apalagi memberi cek kosong kepada siapa pun yang mengatasnamakan darah pesantren. Santri harus kritis, menilai para Gus bukan dari nasab semata, tetapi dari kapasitas, integritas, dan keberpihakannya kepada rakyat.
Pesantren pun perlu menegaskan kembali perannya sebagai penjaga moral bangsa, bukan sekadar lumbung suara. Jika Gus ingin terjun ke politik, biarlah mereka tumbuh sebagai negarawan sejati, bukan hanya pewaris karisma. Sebab bila akar itu hilang, yang tersisa hanyalah nama besar yang rapuh dan pada akhirnya, rakyatlah yang menanggung kecewa.
Oleh:
Abidin, wartawan Duta Masyarakat