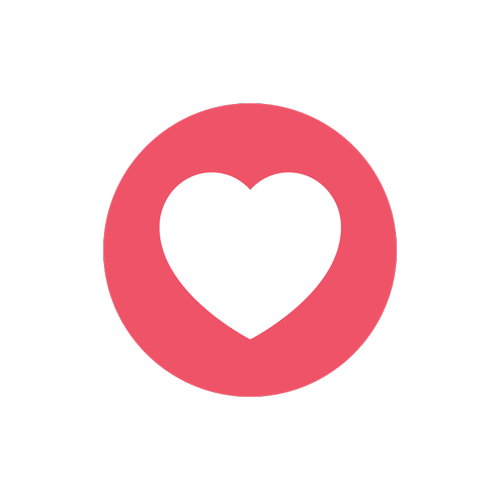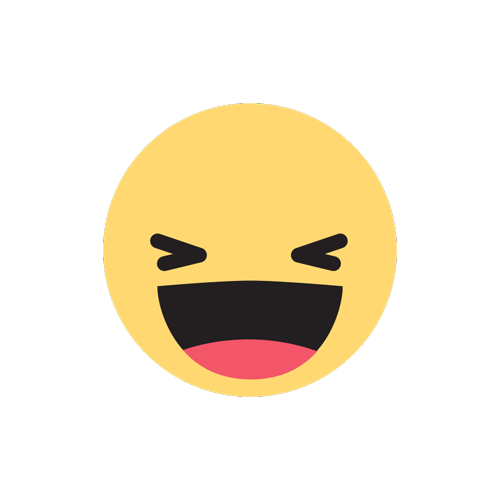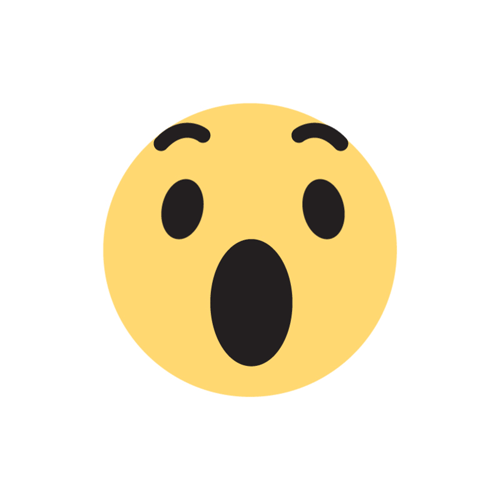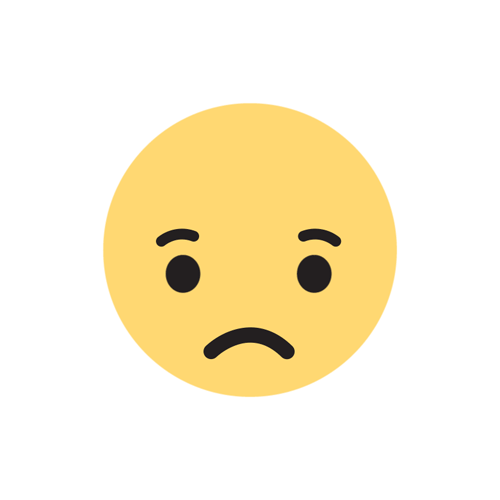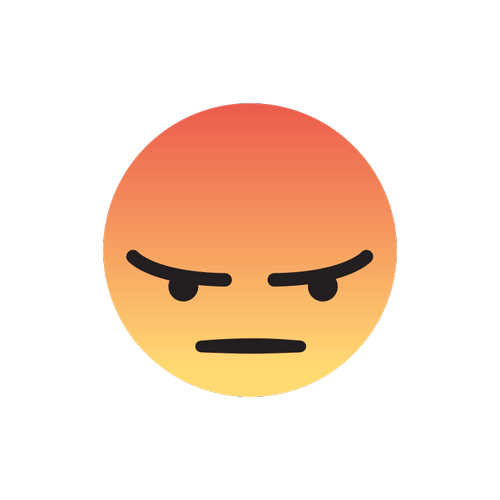Oleh : Dr. Agung Pramujiono, M.Pd.
Lektor Kepala FKIP Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Kepakaran bidang Kesantunan Berbahasa; Pembina HPBI (Himpunan Pembina Bahasa Indonesia) Jawa Timur
Pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dalam forum “Pak Menteri Menyapa Guru Bahasa Indonesia” yang digelar oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (24/6/2025) perlu menjadi bahan refleksi nasional. Mendikdasmen menyampaikan keprihatinan atas makin maraknya penggunaan bahasa kasar dan jorok di ruang publik, menyebut fenomena itu sebagai persoalan yang sudah pada level sangat serius. Pernyataan ini tepat, tetapi patut ditindaklanjuti lebih jauh dari sekedar imbauan moral.
Bahasa tidak pernah hadir dalam ruang yang steril dari pengaruh sosial, budaya, dan politik. Ia bukan hanya alat ukur informasi, tetapi juga sarana ekspresi identitas, resistensi, dan bahkan trauma kolektif. Ketika ruang publik dipenuhi ujaran yang kasar, ini bukan semata refleksi krisis etika individu, tetapi juga tanda bahwa pendidikan bahasa belum sepenuhnya berhasil menjawab kebutuhan zaman.
Sering kali kita terburu-buru melabeli ujaran tertentu sebagai “bahasa jorok” atau “tidak sopan” tanpa memahami konteks penggunaannya. Padahal, apa yang dianggap kasar dalam forum resmi, bisa jadi bermakna keakraban dalam komunitas sebaya. Kata-kata yang di ruang formal dinilai ofensif, dalam ruang digital justru bisa menjadi simbol solidaritas atau ekspresi emosional yang sah. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam menilai bentuk-bentuk bahasa yang digunakan generasi muda hari ini.
Namun demikian, bukan berarti penggunaan bahasa yang menyakiti atau merendahkan orang lain bisa ditoleransi. Yang penting adalah kita menelusuri akar persoalannya: bagaimana bahasa diajarkan di sekolah dan bagaimana peserta didik dibimbing untuk memahami dampak sosial dari setiap ujaran mereka.
Saat ini, pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah memang sudah mulai menjauhi pendekatan struktural yang kaku. Akan tetapi, pembelajaran kita masih lemah dalam membekali peserta didik dengan kompetensi pragmatik, yaitu kemampuan memahami makna ujaran dalam konteks sosial tertentu. Banyak siswa mampu menulis teks deskripsi atau eksposisi dengan baik, tetapi gagal merespon pesan WhatsApp dengan etika komunikasi yang layak.
Di sisi lain, era digital telah mengubah secara radikal cara kita berkomunikasi. Bahasa berkembang menjadi singkat, cepat, dan multimodal. Komunikasi tak hanya dilakukan secara tulis atau lisan, tetapi juga melalui gambar, emoji, video pendek, meme, dan simbol visual lainnya. Bahasa kini tidak hanya persoalan gramatika, tetapi juga soal ekspresi lintas media yang kompleks.
Sayangnya, sistem pendidikan kita belum cukup responsif terhadap realitas ini. Kurikulum bahasa masih belum merespon perkembangan zaman. Padahal, tantangan komunikasi di era digital jauh lebih kompleks dan dinamis. Bahasa kini kerap mengandung ironi, sarkasme, simbol-simbol budaya popular, hingga ujaran yang multitafsir.
Bahasa bukan hanya soal benar dan salah secara tata bahasa. Ia juga mencerminkan cara berpikir, cara memperlakukan orang lain, dan cara membangun relasi sosial. Jika siswa tidak diajarkan untuk memahami bahwa bahasa mereka bisa melukai, merendahkan, atau menyinggung orang lain, maka bahasa akan digunakan dengan sembrono tanpa empati, tanpa kesadaran sosial, dan tanpa tanggung jawab.
Di sinilah peran strategis pendidikan bahasa. Ia harus tampil sebagai ruang pembentukan kesantunan, bukan semata pelajaran teknis. Maka diperlukan perubahan mendasar dalam pendekatan pembelajaran bahasa di sekolah.
Pertama, pembelajaran bahasa harus berorientasi pada fungsi sosial bahasa. Guru perlu mengajak siswa untuk menganalisis bahasa dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks digital. Misalnya, mendiskusikan mengapa kata “anjay” menuai kontroversi, atau bagaimana emoji bisa memperkuat atau mengubah makna kalimat.
Kedua, pembelajaran bahasa harus bersifat multimodal. Anak-anak hidup dalam dunia yang dipenuhi konten visual, audio, dan audiovisual. Pembelajaran bahasa harus mampu menjangkau media seperti vlog, meme, video TikTok, atau infografik. Siswa perlu diajarkan bagaimana menafsirkan, menanggapi, dan memproduksi makna melalui media tersebut. Jika hal ini diabaikan dalam pembelajaran, siswa akan dibiarkan menjelajahi dunia bahasa digital tanpa bimbingan etis.
Ketiga, pembelajaran bahasa harus ditanamkan sebagai bagian dari pendidikan nilai. Bahasa tidak boleh diajarkan sebagai keterampilan netral. Ia harus dipahami sebagai cerminan nilai-nilai kebangsaan, kesantunan, dan kemanusiaan. Misalnya, siswa diajak mendiskusikan isu ujaran kebencian, perundungan, daring, atau stereotip berbasis gender dalam bahasa yang mereka jumpai sehari-hari.
Keempat, guru bahasa harus menjadi fasilitator kritis. Peran guru tidak cukup hanya sebagai pengajar ragam teks, tetapi menjadi pendamping yang membimbing siswa menavigasi dinamika bahasa di tengah masyarakat. Aktivitas seperti membuat podcast tentang esai, refleksi ujaran di media sosial, atau vlog kesantunan digital bisa membuka ruang pembelajaran yang lebih bermakna.
Pernyataan Mendikdasmen dalam forum tersebut seharusnya menjadi momentum penting bagi evaluasi nasional terhadap cara mengajarkan bahasa. Jika ingin membentuk generasi muda yang santun dan cerdas secara sosial, maka pembelajaran bahasa harus lebih kontekstual, relevan, dan humanis. Inovasi dalam pembelajaran bukan hanya sekadar persoalan aplikasi teknologi, tetapi soal keberanian untuk menjadikan bahasa sebagai alat ekspresi diri yang santun dan bertanggung jawab.
Bahasa adalah cermin cara kita berpikir dan memperlakukan sesama. Jika ingin membangun bangsa yang beradab, maka kita harus mulai mengajarkan anak-anak untuk berbahasa dengan hati. Berbahasa dengan empati dan tanggung jawab. (*)