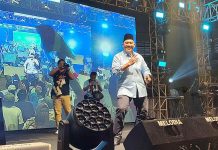Oleh: Suparto Wijoyo*
SUGUHAN aneh-aneh tengah dipertontonkan dalam riuh yang melelehkan air mata duka. Dunia pendidikan dilanda “gerhana total” nestapa, di samping munculnya keberanian selaksa sosok ananda Zaadit Taqwa, ketua BEM UI, pemberi Kartu Kuning, ataupun kegembiraan yang ganjil atas perilaku penguasa “melempar barang dari kendaraan negara kepada warga yang menyambutnya di tepian jalan”, di selisik adanya “nyawa yang teregang dari seorang guru”. Zaadit Taqwa memerankan “ghirah intelektual” mahasiswa. Sebuah kepatutan yang layak diapresiasi tanpa perlu diintimidasi dengan tampilan pengelola pendidikan tinggi yang terkesan “menjadi hulubalang kekuasaan”. Mahasiswa yang mengekspresikan “naluri moralitas kecerdasannya” tidak elok dikritik dengan “penguasaan konsepsi ekonomi” dan “diarak ke Asmat” atau disanksi dengan “rambu akademik” yang menodai “acara terhormat”. Biarlah “drama pementasan daya kritis mahasiswa itu menapaki sejarahnya. Dan Zaadit Taqwa “membuat sejarah” itu dengan kita-kita, orang tua yang diharap lebih bijak menyikapinya, tidak perlu “mendestorsi martabat” keilmuan personalnya.
Hari-hari ini pun terdapat gegemparan yang mengguncang dunia pendidikan dari SMAN 1 Torjun, Sampang, Madura. Achmad Budi Cahyanto, guru honorer ini tewas di tangan muridnya sendiri, HZF, pada Kamis, 1 Februari 2018. Kabar kematiannya membanjiri pemberitaan laksana air bah yang menggenangi seluruh segmen ruang publik dan membuncahkan rasa perih, geram, duka-lara yang mengaduk-aduk kewarasan. Tidak pernah terbayang dalam imaji yang paling liar sekali pun di benak kami, para pendidik, bahwa kelak mengalami sebuah realitas seperti yang menimpa guru Budi. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang menyesakkan dada sambil menyimak ke arah mana pendulum kebijakan negara menyikapinya.
Harkat, martabat, dan kehormatan kaum pendidik “dilumuri darah” oleh anak didiknya sendiri. Fakta yang menyakitkan sekaligus menyembulkan titik kritis terkuaknya problema yang menggelayut di langit-langit ruang kelas. Situasinya nyaris seperceritaan di novel Old Gringo karya Carlos Fuentes (1928-2012), sastrawan dan intelektual terkemuka Meksiko yang membesut Gringo tua, pelintas perbatasan, datang ke Meksiko untuk mati. Guru Budi sejatinya bukan Gringo tetapi kisahnya ternarasikan benar adanya: Guru Budi datang (mendidik) untuk mati. Nasib yang bisa menimpa siapa saja dalam rentang tarikh pengajaran anak-anak abad ke-21. Miris tetapi inilah cerita yang telah membunyikan peluit panjang “kelamnya rezim persekolahan”.
Sudah terlalu banyak kisah sedih yang dialami guru yang selalu “diburu” siswa dan orang tuanya, akibat “tindakan mendisiplinkan”. Anak-anak yang “dihukum jewer” atau “berjemur di halaman” amatlah lazim di era saya sekolah. Di zaman now, hal itu sering “dikriminalisasi” sebagai bentuk “pelanggaran HAM anak” dengan konsekuensi ikutan perilaku tertentu, berupa hadirnya “anak-anak cengeng” maupun orang-orang tua “super protektif nan arogan”. Daulat guru untuk mendidik (bukan sekadar mengajar) sedang digerus dengan target tersembunyi yang terasakan adalah munculnya fenomena anak-anak “bermental rapuh”, jauh dari watak dasar Pancasila. Mengikuti bahasa dalam buku Paulo Freire on Higher Education: A Dialogue at The National University of Mexico (1994), anak didik demikian itu dikhawatirkan membawa benih-benih kerentanan dan kelemahannya sendiri yang kelicikannya selalu muncul, melalui hak keilmuan yang bersifat epistemis borjuis universal.
Substansi pendidikan menurut Pasal 31 UUD 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional adalah hadirnya manusia-manusia Indonesia yang “berilmu, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia”. Dengan demikian penyelenggaraan sekolah dikonstruksi ideal sebagai wahana membentuk manusia berbudi pekerti luhur. Guru dan dosen harus mempunyai otoritas tugas ideologis serta kecendikiaan dalam membangun insan mulia sesuai pesan UUD 1945 tanpa intervensi “kerumunan wali siswa yang jumawa”. Pada lingkup ini ingatan tertuju ke kitab Ihya’ ‘Ulumuddin mahakarya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali (1058-1111) yang sangat populer di kalangan pesantren. Al-Ghazali meliterasikan tugas utama guru di antaranya adalah: “menasihati murid dan mencegahnya dari akhlak tercela”. Guru Budi dari kronologis kasusnya seperti yang diwartakan banyak media amatlah terang bahwa beliau telah menjalankan tugas secara profesional sesuai mandat yuridis maupun ideologis-religius pendidikan.
Amanat yang diemban guru sejatinya sangat bernas sehingga posisinya sangat spesial dalam tradisi regulasi kenegaraan klasik. Di zaman old, sewaktu Kejayaan Imperium Majapahit (1293-1525) telah ada regulasi yang melindungi guru dari “persekusi-caci maki” (wakparusya) maupun dandaparusya (memukul, menusuk, melempari batu, menyakiti, membunuh) di Kitab Perundang-undangan (Kutara Manawa Dharmasastra). Kitab Hukum Majapahit ini berisi 20 bab dan 275 pasal, khusus mengenai proteksi atas profesi guru secara utuh dapat dibaca Pasal 220-246 yang dirumuskan sesuai dengan azas ajaran para brahmana yang tertuang di Bab 70 Nitisastra. Terbunyikan di Nitisastra dimaksud: Yen kowe dosa marang sato kewan bakal nemu paukuman sapuluh tahun lawase, mangkono unining pawulang. Yen dosa marang sapadha-padhamu manungsa, bakal disiksa satus tahun lawase ana ing naraka. Yen marang pangeran (sinatria) sewu tahun. Dene yeng kowe dosa marang guru, siksamu bakal tanpa wates, langgeng ing salawase.
Dari norma yang terkandung dalam Nitisastra termaksud diketahui bahwa apabila seseorang berdosa kepada hewan dihukum sepuluh tahun, kepada sesama manusia dipidana seratus tahun, pada kesatria (bangsawan) sanksinya seribu tahun, adapun kepada guru siksanya abadi, tanpa batas, selama-lamanya. I Agustirto Surayadu (2016) dalam terbitan Kakawin Nagarakertagama menegaskan betapa pentingnya peran guru bagi manusia, masyarakat, dan bangsa. Ratusan tahun yang lampau Nitisastra meletakkan dasar-dasar pendidikan dan penghormatan kepada guru, maka menjadi sangat naif apabila di zaman yang berbilang modern justru “menistakan guru” dengan bungkus hak-hak hukum. Perlindungan murid memanglah mutlak tetapi tidak diseyogiakan untuk mengkriminalisasi guru yang mendidik, oleh pihak-pihak yang sok jagoan.
Apa yang menimpa Guru Budi menjadi momentum menata kembali relasi harmonis tanpa “intimidasi” antara guru, sekolah, orang tua, dan pemerintah. Saya percaya kejadian Guru Budi “mendidik menjemput maut” ini tidak akan terulang kembali di NKRI, senafas “pantun santun” berikut:
Gendang gendut, tali kecapi
Kenyang perut senanglah hati
Pinggang tak retak, nasi tak dingin
Tuan tak hendak, kami tak ingin.
*Kolomnis, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga